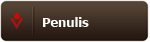Nyai Dan Noni
Anindita S Thayf memulai riwayat kerja sebagai penulis cerita pendek anak-anak. Novel anak-anaknya yang berjudul Keajaiban Ila terpilih sebagai Pemenang I pada Sayembara Menulis Novel Anak 2005 dan nominator Mizan Award 2006 untuk kategori “Cerita Anak dengan Ending Terbaik”. Novel ini diterbitkan oleh penerbit Dar! Mizan, 2005.
Kini, Anindita lebih dikenal sebagai penulis novel sastra. Novel karyanya berjudul Jejak Kala terpilih sebagai Pemenang Harapan I pada Lomba Penulisan Novel Inspirasi Penerbit Andi 2008. Novel ini diterbitkan oleh penerbit Andi, Yogyakarta, 2008, dan terpilih sebagai Peraih Penghargaan Sastra dari Pusat Bahasa Propinsi DIY Yogyakarta pada tahun 2010. Adapun novelnya yang berjudul Tanah Tabu mendapat predikat Pemenang I pada Sayembara Menulis Novel Dewan Kesenian Jakarta 2008. Novel ini diterbitkan oleh penerbit Gramedia Pustaka Utama, 2009, dan masuk finalis 5 besar dalam Khatulistiwa Award 2009.Kini penulis tinggal di lereng Gunung Merapi, Yogyakarta, Indonesia.
Hak cipta © 2015 ada pada Anindita S. Thayf. Terbit atas izin dari penulis. Hak cipta terjemahan © 2015 oleh Stefanny Irawan.
***
Nyai Dan Noni
(Nyai)
Malam sudah datang lagi, yang kesepuluh, kau mendesah. Kakimu tertuntun menuju tempatmu yang biasa: pojok paling dalam. Relung paling hangat dan tersembunyi dimana kau selalu setia menunggu kunjungan subuh. Kau duduk sambil menajamkan pendengaran, cerabih binatang malam membuatmu merasa seolah sedang menyaksikan pagelaran wayang, bukannya berada di tempat yang menakutkan. Ada suara khas sang dalang. Nyanyian mendayu para sinden. Alunan gending yang akrab. Sesekali, kau bahkan merasa bisa mendengar seruan penonton dan gema tepuk tangan mereka. Semua itu memesonamu. Menghanyutkan sadar sampai tiba-tiba secubit rasa geli menyentilmu. Rupanya, ada yang sedang mengerikiti kakimu. Kecoak! Sertamerta kau bergerak menjauh. Tapi hanya sebatas itu. Tidak sampai menjerit panik—sebab itu bukan kau.
Kau memang seorang perempuan, tapi tidak seperti dia yang datang empat hari lalu. Yang cengeng dan manja. Yang peka dan perasa. Dia yang kau benci karena telah memaksamu berbagi tempat sempit ini. Lebih daripada itu, kau membenci semua yang ada pada dirinya; rambut pirang yang mengingatkanmu pada masa kejayaanmu dulu, bola mata yang membiru gundu dan terlihat begitu angkuh, juga kulit sewarna roti gandum, bahkan suaranya yang mirip dengkur palsu kucing.
Uhh! Kau sangat membenci yang terakhir itu—dasar bangsa penipu! Membuatmu kerap disesaki keinginan untuk mencekiknya. Menguburkan kuku-kukumu pada daging pucat leher jenjangnya. Kau yakin bisa membunuhnya. Mematahkan batang lehernya dengan cepat. Bukankah tanganmu terbukti cukup kuat karena terbiasa mencabut rumput dan memeras cucian? Bukankah pula tubuh perempuan itu tampak serupa tunggul pisang kering, yang besar tapi rapuh?
Tanpa sadar, bibirmu memainkan ringis kemenangan. Dengan membunuhnya, kau berharap mendapat sedikit kesenangan. Mendadak, tanganmu bergerak begitu cepat. Langsung menuju sasaran. Dan…
Plakk! Kriek!
Denyar kematian seketika terasa. Ada yang mati tanpa sempat lari. Kecoak itu. Kau tersenyum senang. Kebencianmu sedikit terlampiaskan.
***
(Noni)
Sebenarnya, kau sangat suka malam. Remang-remangnya kau anggap romantis. Dinginnya menuntunmu pada pendiangan cinta yang membara. Apalagi ketika sinar purnama menyirami tubuh dan rambut pirangmu maka saat itulah mimpi terindahmu menjadi nyata.
Kini, yang terjadi adalah sebaliknya. Kau sangat membenci malam. Malam telah mewujud monster mimpi buruk paling seram. Yang mendatangkan dingin dan mampu meradangkan tulang. Yang mengundang sejumlah makhluk kecil menjijikkan untuk berpesta di luar sarang. Namun, yang paling mengerikan adalah kengerian yang membuatmu selalu berjaga-jaga setiap kali sore mulai mengajak matahari melarikan diri seperti saat ini.
Kau sudah hapal, angin yang lembab akan datang dari arah kiri. Karena itu, kau sengaja memilih duduk di sudut kiri ruangan paling luar. Merapatkan tubuh letihmu pada dinding. Mencoba memulung sisa kehangatan yang masih ada, tapi sia-sia. Tempat terhangat di ruangan ini sudah dikuasai oleh perempuan itu. Yang kasar dan tidak beradab. Si pemarah yang keras kepala. Dia yang kau benci karena membuatmu merasa selalu terancam. Lebih daripada itu, kau membenci semua yang ada pada dirinya; rambut hitam mengikal, bola mata sewarna jelaga yang menyorot tajam, suara yang sekeras salakan anjing, juga kulit kecoklatan milik pribumi, mengenangkan kau pada masa lalu mu.
Uhh! Kau sangat benci pada bangsa itu—dasar bangsa rendahan! Kau tiba-tiba ingin menggigit lehernya. Menanamkan geligimu yang putih-kuat di sana, tepat di urat besar. Kau yakin bisa membunuhnya. Membuat darahnya meruah.
Ayahmu adalah seorang dokter yang sering membagi ilmunya tentang bagian tubuh manusia yang mematikan jika terluka. Kebiasaan perempuan itu duduk sambil menutup mata. Mudah sekali menyerangnya.
Tanpa sadar, ujung bibirmu menukik aneh. Dengan membunuhnya, kau berharap mendapat sedikit ketenangan. Kau baru saja ingin menyusun sebuah rencana ketika tiba-tiba…
Plakk! Kriek!
Ada yang bergema dari sudut ruang tempat perempuan itu bertahta. Suara nyaring yang mengusir hening dan menggerakkan kepalamu untuk berpaling. Di sana, dalam remang, kau menyaksikan pemandangan yang membuatmu bergidik. Di atas lantai, seekor kecoak terkapar mati dengan perut pecah. Dan, di telapak tangan perempuan itulah terlihat isi perutnya.
Huekk! Tak tahan, kau muntah.
***
“Sudah cukup! Kau telah membuat sabarku habis. Benar-benar perempuan sial, Kau. Sial!” terdengar teriakan kesal si perempuan berambut hitam pada perempuan berambut pirang, yang langsung disusul dengan terjangan penuh kemarahan. Gerakan anjing pendendam.
“Tunggu dulu! Tunggu! Ada apa denganmu?! Kau mau membunuhku, ya? Dasar gila! Kau sudah gila!” pekik panik si pirang berhamburan tanpa sela. Dia benar-benar tidak menduga. Serangan si rambut hitam terlalu kalap untuk dihentikan. Sebagai anak dari keluarga terhormat yang selalu menjaga sikap, situasi ini baru baginya. Ia tidak pernah terlibat perkelahian. Para penjaga selalu ada. Tapi kini, dinding penjara Jepang telah mengurungnya. Dia bukan lagi noni terhormat seperti dulu. Dia terbuang di sini. Tidak berarti.
“Kau telah menghinaku, Perempuan Sial! Kau barusan muntah di depanku. Apakah kau sengaja, hah?!” perempuan berambut hitam balas menjerit sepenuh paru-paru. Saat ini, dia merasa telah mencapai puncak jemu. Emosinya membumbung. Inginnya terus mengamuk. Keluwesan sikapnya yang dulu mampu menggaet hati seorang meneer hingga menjadikannya nyai, dipaksa menguap oleh kejamnya penjara Jepang. Dia bukan lagi nyai meneer Administratur tersayang seperti dulu. Dia terbelenggu di sini. Tidak bernilai.
“Tidak! Tidak begitu. Kau salah paham. Salah!” Si pirang masih mencoba menghentikan serangan. Tapi, si rambut hitam sudah gelap hati. Serangannya makin menyakiti. Serangan pelampiasan.
“Kau telah mengotori tempat ini dengan bau busuk sisa makananmu, Juffrouw! Kau akan kubunuh. Kubunuh!” Si rambut hitam lantas menduduki perut si pirang. Berusaha menjepit tubuh lawannya, yang terus memberontak, dengan kedua kakinya yang kuat hingga meletupkan serangkaian jerit histeris dari mulut si pirang.
“Godverdomme. Perutku! Perutku!!!”
Mendengar umpatan dalam bahasa asing itu, perempuan berambut hitam malah semakin kalap.
“Pikirmu, aku tidak tahu apa yang kau katakan itu, hah?! Dasar perempuan asing tidak tahu diri. Penjajah sialan! Kafir!”
“Kaulau bangsa jongos yang tidak tahu diri. Perempuan bodoh! Mulut kotor! Kau yang kafir!”
Tak terhindarkan, ruang penjara sempit itu berubah menjadi kancah pergumulan. Tubuh-tubuh bergelut dalam amuk. Mencoba saling remuk dengan gigi dan kuku. Kulit pun terkuak. Daging terkoyak. Rambut-rambut tercerabut. Semuanya menghamburkan darah. Hingga…
Disertai pekik marah, tiga orang sipir penjara berkulit kunyit dan bermata kuaci menyerbu masuk ke tengah arena pergumulan. Mencoba memisahkan kedua perempuan yang lepas kendali itu dengan kasar. Dengan pangkal popor senapan dan sepatu lars. Dengan tamparan dan makian. Sebagai balasannya, erangan demi erangan saling bertalun. Jerit kesakitan pecah. Rintihan ampun menyela. Sebagai jawaban, caci maki dan suara tamparan diterima oleh perempuan-perempuan itu.
“Tutup mulutmu, Pelacur! Beginilah kalian akan selalu diperlakukan jika terus membuat kacau. Anjing-anjing betina gila!”
Malam kembali sepi ketika derap tiga pasang sepatu itu bergerak menjauhi penjara, meninggalkan dua sosok tubuh yang terkapar kesakitan dalam paluh darah.
***
(Nyai)
Kau memaksa membuka matamu yang bengkak. Rasanya berat dan perih. Tapi kau ingin melihat, meskipun hanya merah yang pertama kali tampak. Darah. Dengan menahan sakit, kau mencoba bergerak—tidak bisa. Lalu, kepalamu berusaha berputar—ternyata bisa. Sedikit gerak memutar ke kanan. Dan, saat itulah kau melihat dia. Si pirang.
Dia terbaring meringkuk serupa bayi dalam rahim. Terlihat selemah kulit jagung. Wajahnya menengadah ke arahmu; pucat, penuh lebam, bernoda darah. Noda yang memudarkan kecantikannya dan menyembunyikan matanya yang terpejam. Kau melirik bagian bawah tubuhnya yang bermandikan darah. Sudah matikah dia? Tanpa diundang, ibamu muncul.
Entah apa yang telah membawa seorang gadis pirang cantik sepertinya masuk ke dalam neraka dunia ini. Dalam hati, kau mencoba menebak. Apakah dia tidak sempat kabur bersama keluarganya saat Jepang menyerbu? Ataukah, dia diculik dari rumah?
“Ah, keluarga. Rumah,” desahmu pilu. Lalu, terbayanglah kisah hidupmu.
Seandainya Belanda tidak pernah kalah perang dan Jepang tidak menemukan negeri ini, kau meramalkan kalau hidupmu akan bahagia selalu. Dimanja oleh tuanmu. Dilayani para babu. Dibanggakan bapak-ibu. Sungguh indah hidupmu dulu, meskipun hanya menjadi nyai.
Tapi hidup memang penuh kejutan. Ketika Jepang datang, suamimu malah pergi. Kembali ke negaranya tanpa mau membawamu. Alasannya, tidak ada tempat untukmu di sana. Ah, betapa laki-laki itu telah melukai setiamu. Membiarkanmu menjadi harta rampasan perang bersama barang peninggalannya yang lain.
“Dasar kafir!” begitulah makimu selalu. Sejak itu, kau sangat membenci setiap orang berkulit pucat, termasuk si perempuan berambut pirang. Namun kini, keadaannya tidak jauh beda darimu. Haruskah kau tetap membencinya?
***
(Noni)
Kau tidak bisa bergerak. Tak mampu merasakan apa-apa. Mungkin tubuhmu melumpuh atau kau sudah mati. Tapi rasa hangat bercampur nyeri yang datang kemudian dari arah selangkang menyadarkanmu bahwa kau masih hidup. Tapi…
“Perutku,” kau mendesis lemah dengan kekhawatiran meraja. Bayimu yang baru berusia dua bulan sedang tertidur lelap di dalam sana. Kau bertanya-tanya bagaimana keadaannya; semoga ia selamat. Namun, kesakitan yang merebak jelas dari balik kulit perutmu langsung memberikan jawaban.
“Tidak ada. Dia sudah tidak ada!” Kau memekik lirih. Matamu dipaksa membuka oleh kucuran air mata yang menderas. Saat itulah kau melihat dia. Si rambut hitam.
Dia terbaring terlentang dengan wajah menengok ke arahmu. Begitu mengenaskan; bengkak, penuh darah kering, bibirnya sobek. Matanya terbuka setengah dan terlihat hampa sinar. Sudah matikah dia? Tanpa diduga, rasa kasihanmu timbul.
Entah apa yang membuat seorang perempuan pribumi menjadi tawanan Jepang. Dalam hati, kau mencoba menebak. Apakah dia seorang mata-mata yang dikhianati seseorang? Atau, apakah dia telah melakukan kesalahan?
“Ah, pengkhianatan. Kesalahan,” gumammu penuh sesal karena teringat kisahmu sendiri.
Seandainya kau mau mendengar perkataan orang tuamu dan tidak menuruti gelora cinta muda, tentulah kini kau sudah berada di atas kapal menuju daratan Kincir Angin bersama mereka. Tapi cinta telah meniupkan jampinya kepadamu.
Kau terbius kejantanan seorang laki-laki pribumi. Terpesona sopan santunnya sebagai pegawai ayahmu yang setia. Kau pun nekat melanggar batas. Menjalin kasih terlarang. Memasrahkan diri pada dosa…. hingga kau hamil. Dengan terpaksa, semuanya berjalan sesuai keinginanmu. Kalian akan dinikahkan seminggu lagi. Sungguh indah jika rencana itu terwujud, begitu pikirmu, meskipun harus mengorbankan mereka yang kau cintai: keluarga.
Namun, hidup selalu punya rencana rahasia. Kemenangan bangsa kuning. Kekalahan bangsa putih. Seluruh keluargamu bergegas mengungsi, kecuali kau, yang lebih memilih mengikuti pribumi itu. Calon ayah bayimu. Sang cinta sejati. Sebagai balasan, tanpa malu, dia mengabdi pada Saudara Tua berkulit kuning yang baru dikenalnya. Tanpa cinta, dia menyerahkanmu sebagai bukti kesetiaan.
“Dasar pribumi!” begitulah makimu selalu. Sejak itu, kau sangat membenci setiap penduduk asli, termasuk si rambut hitam. Tapi kini, keadaannya tidak jauh berbeda darimu. Haruskah kau tetap membencinya?
***
Kedua perempuan itu masih sibuk dengan luka dan pikirannya masing-masing. Di saat yang sama, derap langkah berpasang-pasang sepatu terdengar mendekat. Para sipir membuka pintu, mendekati dua sosok tubuh yang tergeletak lemah di atas lantai. Satu per satu, tubuh-tubuh itu digerayangi dengan kasar.
“Air. Air,” si rambut hitam mengerang.
“Dokter. Aku perlu dokter,” si pirang meminta.
Namun, sejak dulu, hidup memang tidak pernah adil kepada kaum perempuan. Tanpa setahu keduanya, kengerian yang sebenarnya baru saja akan terjadi. Tangan-tangan berkulit kuning itu merobek pakaian mereka satu per satu. Sejumlah laki-laki dengan mata-mata sipit yang memerah dan menyorotkan nafsu liar mulai memperkosa keduanya. Nyai dan noni terlambat untuk menyadari bahwa seharusnya mereka tidak saling membenci seperti ini; bahwa sebenarnya musuh mereka tiada lain adalah laki-laki.