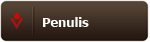Mata di Bibir Subuh
Artie Ahmad, lahir di Salatiga 21 November 1994. Saat ini tinggal di Yogyakarta. Selain menulis cerita pendek, dia juga menulis novel. Beberapa bukunya seperti, novel ‘Sunyi di Dada Sumirah’ terbit di Penerbit Buku Mojok, cetakan pertama 2018 dan cetakan kedua terbit 2020, kumpulan cerita pendek ‘Cinta yang Bodoh Harus Diakhiri’ diterbitkan Penerbit Buku Mojok, cetakan pertama tahun 2019 dan cetakan kedua tahun 2020, novela terbarunya berjudul ‘Manusia-Manusia Teluk’ terbit 2020 di Penerbit Buku Mojok. Cerita-cerita pendeknya dimuat media massa seperti koran Tempo, Jawa Pos, Republika, Solopos, Kedaulatan Rakyat, Tribun Jabar, Minggu Pagi, Haluan, Detik.com dan beberapa media massa lainnya.
Artie bisa dihubungi di adekartie@gmail.com.
Terbit bulan Juni 2020. Hak cipta ©2020 ada pada Artie Ahmad. Terbit atas izin dari penulis. Hak cipta terjemahan ©2020 ada pada Oni Suryaman.
Mata di Bibir Subuh
Suara azan Subuh terdengar, merambat dari corong pelantang suara di masjid. Bergetar masuk ke dalam gendang telinga orang-orang yang masih terlelap. Suara Pak Modin yang terdengar lantang itu juga ditangkap telinga Muzaini. Azan masih terdengar, menggelitik telinga Muzaini. Tapi, meski azan itu masuk ke telinga dan mengetuk-ketuk gendang telinganya, Muzaini seakan tak berdaya. Matanya seolah terkena getah nangka. Lengket, sulit untuk dibuka. Muzaini berusaha membuka mata, namun rasa kantuk yang dirasakannya sangat keterlaluan. Muzaini tak kuasa melawan, dia kembali bergelung di tilam.
Suara azan Pak Modin telah lesap, Subuh telah lama lewat. Dalam mimpi di kepalanya, Muzaini menangkap bayang Wak Rohim. Dulu saat dia masih anak-anak, Wak Rohim gurunya mengaji di surau desa. Dalam gambar di mimpinya itu, Wak Rohim berdiri membawa rotan yang dipergunakan untuk memukul pantat para muridnya yang hanya main-main saat mengaji. Muzaini tergagap, ketika melihat Wak Rohim berjalan ke arahnya. Rotan di tangannya diayun-ayunkan. Bibirnya tersenyum simpul. Tapi begitulah wajah Wak Rohim ketika hendak menghukum muridnya.
“Muz! Kau tak menjalankan perintah Allah dengan baik ya? Kau meleng ya?” Suara Wak Rohim terdengar lantang.
Muzaini tak kuasa menjawab. Dia hanya menggeleng-geleng. Wajahnya pucat pasi, keringat dinginnya mengalir.
“Kau, Muzaini Samsyudin! Berani tak menjalankan perintah Gusti Allah? Muridku yang dulu berjanji akan menjadi manusia baik. Kau bohong denganku?” Wak Rohim semakin dekat. Kumisnya yang melintang dengan jambang lebat itu semakin menambah kesan angker di wajahnya.
“Bukan begitu, Wak Guru. Saya sudah berusaha bangun. Tapi tak kuasa. Mata saya lengket seperti kena getah nangka,” Muzaini menggigil.
“Alasan saja kau, Muz. Menyesal aku dulu tak memukulmu lebih keras dengan rotan ini. Kini kau jadi seorang pembangkang.” Wak Rohim mengangkat rotannya tinggi-tinggi.
Muzaini ingin berlari menghindar, tapi tak bisa. Tangan kiri Wak Rohim menggamit lengannya. Tangan itu mencengkeram Muzaini erat-erat. Napas Muzaini tersengal, tapi dia seolah tak memiliki tenaga untuk lari dari Wak Rohim.
“Oh, Muz. Betapa berubahnya engkau sekarang ini? Aku tak menduga kau akan berubah seperti sekarang,” Wak Rohim menurunkan tangannya yang memegang rotan, cengkeraman di lengan Muzaini mengendur, lalu dihempaskan begitu saja.
“Tak ada yang berubah di diri saya, Wak Guru. Tak ada yang lain saya rasa. Saya hanya sering kelelahan setelah bekerja di kota,” Muzaini menatap Wak Rohim dengan getar suara yang tak bisa ditahan.
Wak Rohim mengangkat wajahnya, ditatapnya Muzaini lekat-lekat. Seringai di bibirnya terlihat.
“Tak ada yang berubah dengan dirimu? Kau bercanda! Kini kau lalai akan semuanya. Sembahyangmu tak lagi sebaik dulu. Dan, kau lupa akan janjimu,” Wak Rohim berdiri di depan Muzaini dengan gagah. Sarungnya yang putih bersih dengan corak bunga-bunga kecil berwarna hitam berkibar-kibar ditiup angin. “Dulu, kau bilang jika sudah banyak uang dan dapat pekerjaan bagus, kau akan membantu merawat gubuk kecil tempat anak-anak desa mengaji. Tapi seolah kau lupa dengan janjimu itu. Jangankan membantu merawatnya, bahkan kau pun tak lagi mau menengoknya.”
***
Muzaini terbangun dari tidurnya. Matanya sudah leluasa dibuka meski agak berat. Muzaini tak mengerti, mengapa Wak Rohim datang di mimpinya hari ini, dengan keadaan yang membuatnya bergidik pula. Sudah lama sejak dia bekerja di luar kota, orang-orang di desanya teramat jarang berkunjung ke mimpinya. Muzaini saban malam memang bermimpi di saat tidur, tapi itu bukan memimpikan orangorang di desanya yang telah lama dia kenal. Di mimpi Muzaini selepas kerja di kota besar ini, yang sering bertandang adalah kawan-kawan kenalannya, atasan di kantor yang sering mengejar-ngejar tenggat waktu pekerjaan, pemilik kamar sewa yang suka menagih padahal belum waktunya, atau yang kerap datang di mimpinya seorang Manisa. Manisa, kawan sekantornya yang berwajah manis dengan perangai lembut itu. Wajah yang menjadi kembang tidur Muzaini bahkan selepas pertama kali mereka berjumpa.
Tertegun Muzaini mendengar ucapan Wak Rohim. Dia tepekur beberapa saat. Matanya nyalang menatap lantai. Bibirnya bergetar. Dia ingat sekarang, memanglah dulu dia sempat bernazar apabila telah mendapat pekerjaan dengan gaji yang baik, dia akan membantu merawat surau kecil untuk mengaji yang sering disebut gubuk oleh Wak Rohim. Tapi, sudah lebih lima tahun bekerja dengan gaji yang baik, belum pernah dia membagi rezekinya untuk surau kecil tua tempatnya mengaji dulu. Entah hari baik apa yang didapatkannya, hari ini Wak Rohim datang ke mimpinya, dan seolah menagih janji yang telah sekian lama tak juga dia tepati.
***
Sepanjang hari, mimpi itu lekat di ingatannya. Di kantor, di warteg tempat dia makan siang, ingatan tentang mimpi bertemu Wak Rohim selalu bertandang. Bahkan ketika dia bertemu dengan Manisa pun, untuk kali pertama Muzaini tak tertarik untuk menanggapi perempuan muda itu. Muzaini merasa lesu. Bahkan ketika pulang bekerja, dia langsung mengurung diri di kamar sewa. Muzaini berdiam diri di tilam kamarnya. Sampai akhirnya dia lelap. Tertidur sampai azan Subuh berkumandang.
Kali ini Muzaini begitu leluasa membuka mata. Tak lama setelah terjaga dia menyeret kakinya masuk ke dalam kamar mandi, dia menunaikan wudu lalu bersembahyang Subuh. Selepas sembahyang itulah, pikiran jernih itu muncul. Tiga pekan lagi dia akan libur panjang selama satu pekan, saat itu kesempatan baik untuknya pulang guna menemui Wak Rohim untuk membayar tunai janjinya dulu.
***
Mata Muzaini terbuka. Subuh menjalar masuk ke bus yang dia tumpangi. Suara azan dari masjid-masjid di pinggir jalan terdengar. Muzaini mengejap-ejapkan kedua matanya. Sebentar lagi bus antar kota yang dia naiki akan sampai ke pemberhentian terakhir, terminal yang paling dekat dengan desanya.
Sesampai di terminal, dengan semangat Muzaini memanggil ojek yang mangkal di sekitar terminal. Meski masih sedikit merasa kantuk lantaran kelelahan setelah menempuh perjalanan selama 12 jam perjalanan, Muzaini sangat bersemangat untuk pulang ke desanya kali ini.
Di dalam ranselnya, Muzaini telah menyiapkan sebuah amplop berisi uang yang akan disampaikannya untuk Wak Rohim guna memperbaiki suraunya. Surau yang mungkin kini sudah bertambah reyot lantaran aus dimakan usia. Muzaini pun tahu, bagaimana keuangan guru mengajinya itu. Anak-anak yang diajar mengaji tak ditarik bayaran, apabila ada yang memberikan uang, banyak kesempatan Wak Rohim menolaknya. Baginya, menerima uang dari orangtua muridnya yang memiliki nasib keuangan seperti dirinya hanya akan menambah sengsara kedua belah pihak. Orangtua murid akan sengsara lantaran anggaran untuk hidup berkurang, dan Wak Rohim akan sengsara lantaran batinnya tak tenang menerima uang dari orangtua muridnya yang juga kesusahan.
Muzaini berjalan ke rumahnya. Dia mengurungkan diri untuk terus ke rumah Wak Rohim yang rumahnya di batas desa tetangga. Turun dari ojek, dia merasakan sangat letih meski semangatnya untuk bersua dengan Wak Rohim masih berkobarkobar. Pintu belakang tak terkunci. Muzaini mencari-cari ibunya, tapi yang dicari tak ada. Mungkin ibunya sedang ke pasar. Pesan kepulangannya telah disampaikan ke ibunya sejak beberapa hari yang lalu, namun Muzaini tak mengatakan bahwa dia perlu juga bertemu Wak Rohim.
Lepas siang Muzaini baru berkesempatan untuk pergi keluar rumah. Ibu sedang ada tamu untuk membicarakan pekerjaan. Mungkin itu pembeli yang akan membeli beras hasil panen milik ibu. Diam-diam Muzaini pergi ke rumah Wak Rohim. Tapi di tengah jalan dia bertemu beberapa orang. Mereka berduyun-duyun berjalan ke arah rumah Wak Rohim. Muzaini melihat mereka dengan tatapan bingung. Seorang anak muda berusia belasan tahun juga turut berjalan ke arah rumah Wak Rohim, dengan cepat Muzaini bertanya.
“Adik, mau ke mana kalian ini? Kenapa beramai-ramai?” Muzaini bertanya sembari tersenyum ramah.
“Oh, Bang Muz. iya, kami akan melaksanakan kenduri,” sahut pemuda itu sembari menyalami Muzaini.
“Kenduri? Kenduri di mana?” Muzaini bertanya lagi.
“Kenduri ke rumah Wak Guru Rohim.”
“Kenduri untuk apa?” Muzaini semakin kebingungan. Ada acara apakah sampai dilaksanakan kenduri di rumah Wak Rohim.
“Kenduri untuk memeringati empat puluh hari kepergian Wak Guru Rohim menghadap Gusti Allah.” Sahut pemuda itu sembari menatap Muzaini dengan tatapan terheran-heran. Dia menatap Muzaini dengan keheranan, sepertinya dia tak menyangka, kalau Muzaini belum tahu bahwa Wak Guru Rohim sudah meninggal.
Muzaini tak bisa berkata-kata. Kepalanya mendadak terasa pening. Kabar yang dia terima seolah menggetarkan hatinya. Dengan langkah yang seakan limbung, Muzaini berjalan ke arah rumah Wak Rohim. Di sana orang-orang sudah banyak yang datang. Doa dihantarkan untuk Wak Rohim. Tangis Muzaini tak bisa ditahan. Penyesalannya semakin menjadi, ketika melihat surau kecil tempat Wak Rohim mengajar mengaji telah rubuh.
“Muzaini, kau juga ke sini ternyata?”
Muzaini menoleh, ibunya sudah berdiri di belakang tubuhnya.
“Ibu kenapa tak berbagi kabar jika Wak Rohim meninggal?” tanya Muzaini masih terisak.
“Ibu lupa mau berkabar denganmu. Tiap kali ibu telepon, kau selalu cepatcepat menutup lantaran sibuk. Setelahnya ibu selalu lupa mengabarimu.” Ibunya mengamati Muzaini dengan iba.
Mata Muzaini menyapu rumah Wak Rohim dan surau tempatnya mengaji dulu. Surau itu kini hanya tinggal puing-puing yang menyisakan kayu-kayu tua yang sudah lapuk. Tangis Muzaini tak bisa berhenti, dengan erat tangan kanannya mencengkeram amplop berisi uang untuk membantu mengurus surau kecil tempat Wak Rohim mengajar.
“Maafkan saya, Wak Guru. Maafkan saya karena sangat terlambat menemuimu.” Isak Muzaini sembari memandang surau kecil tempatnya belajar mengaji dulu yang kini hanya menyisakan puing-puing.
***