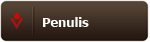Pekik Burung Kedasi di Tepi Kahayan
Han Gagas lahir di Ponorogo, 21 Oktober 1977. Dia alumni jurusan geodesi UGM Yogyakarta. Cerpennya dimuat media massa seperti Horison, Kompas, Tempo, Republika, dan Suara Merdeka. Karyanya yang terbit, diantaranya novel Orang-orang Gila (Buku Mojok, 2018). Novelnya Balada Sepasang Kekasih Gila pemenang lomba Falcon Script Hunt 2020 akan difilmkan Falconpicture dan catatan pengalamannya selama tinggal di Yerusalem berjudul Adzan di Israel akan diterbitkan Penerbit Gading pada akhir tahun 2021.
Karya terbarunya, kumpulan cerpen Sepasang Mata Gagak di Yerusalem diterbitkan Penerbit Interlude pada bulan Juni, 2021.
Saat ini tinggal di Solo, Jawa Tengah, selain menulis juga mengelola media daring Nongkrong.co
Penulis dapat dihubungi melalui surel: han.gagas@gmail.com
Pekik Burung Kedasi di Tepi Kahayan
Setelah berkuliah selama lima tahun di Yogyakarta, Mawinei baru bisa pulang kampung ke desanya yang terletak jauh di pedalaman Kalimantan Tengah. Dia menyimpan kerinduan yang amat sangat pada keluarga dan kawan-kawan masa kecilnya yang mengajaknya berkumpul kembali.
Kerinduan yang begitu kuat membuatnya rela menempuh perjalanan panjang dengan bis kota dari Yogyakarta ke Surabaya, kemudian naik kapal laut sehari semalam ke Pelabuhan Sampit, di Kalimantan Tengah. Dari sini, dia menempuh jalur darat dengan bis kota ke Palangkaraya dan berlanjut ke kampungnya yang terletak di Kabupaten Gunung Mas di tepi Sungai Kahayan. Di kendaraan, dia mendengar para penumpang sedang membicarakan pembukaan Asian Games 2018 di Jakarta yang dibuka Presiden Jokowi dengan meriah saat dia masih di kapal laut semalam.
Semua orang menyambut kedatangan Mawinei sebagai satu-satunya perempuan yang jadi sarjana di kampung ini. Mawinei diharapkan bisa mengangkat mutu kehidupan orang tuanya, juga kaum di desanya sebagai keturunan Dayak Ngaju. Rumah betang, rumah panjang Dayak, dihiasi janur dan ramai didatangi banyak orang, termasuk Danum, Simpei, dan Ekot. Mereka adalah anak tetangga dan teman main Mawinei sejak anak-anak.
Berbagai makanan tersaji. Masakan kesukaan yang diharapkan Mawinei juga ada. Kandas sarai, sambal serai yang dicampur dengan ikan baung bakar, menjadi pelepas kerinduannya akan kelezatan masakan Dayak yang khas. Mawinei mendekati Danum yang berkumpul dengan Simpei dan Ekot. Mereka makan bersama sambil bersendau gurau. Bapak-bapak mengobrol dan tertawa terbahak-bahak sembari minum baram, minuman keras yang terbuat dari peragian air beras dan singkong. Baram dalam botol dituangkan dalam gelas-gelas kecil yang beredar dari satu tangan pria ke tangan pria lain. Semua terlihat bergembira, makan bersama.
Namun, Mawinei merasa ada yang lain, ada sesuatu yang tengah terjadi, yang belum dia ketahui. Dalam kegembiraan orang-orang itu, Mawinei merasakan ada kegelisahan yang samar yang coba disembunyikan. Sejak kecil, Mawinei seperti memiliki kepekaan menduga kecemasan.
Benar pula, sehari setelah Mawinei tiba di kampungnya, ketakutan menyeruak tiba-tiba di pagi buta, saat Mina, Bibi, Sanja berteriak minta tolong. “Tolong! Hanjak, Hanjak berak darah!”
Kabut pagi berangsur menghilang berganti dengan terang tanah. Orang-orang berdatangan. Tampak Mina Sanja kebingungan, wajahnya dibasahi air mata.
Balian, bapa dukun, segera dipanggil. Lelaki tua itu datang dengan raut muka tenang. Dia duduk dan mulai menyandah, menerawang untuk melihat sebab penyakit. Dia melanjutkannya dengan upacara sangiang, pengobatan dengan bantuan roh leluhur. Tubuh kurus balian terlihat bergetar seperti kerasukan roh. Setelah kembali tersadar, dia berbicara dengan pembantu utamanya dalam urusan perdukunan. Lelaki itu segera berlari mengajak para tetangga masuk hutan, mendongkel beberapa tanaman untuk diambil akar dan dedaunannya.
Daun dan akar rumput bulu ditumbuk, lalu dibalurkan di pusar Hanjak. Ada pula yang menyeduh dedaunan itu, dan air saringannya diminumkan ke Hanjak. Akar halalang dan bopot turut pula ditumbuk dan diseduh dengan air panas, kemudian diminumkan. Ketiga jenis tanaman ini diyakini sebagai obat sakit perut dan muntaberak, serta dapat mengatasi pendarahan.
Sehari kemudian, anehnya, keadaan Hanjak memburuk. Mina Sanja bingung bukan kepalang. Walau muntahberaknya berhenti, suhu tubuh Hanjak masih panas sekali. Biasanya, setelah diobati balian, orang sakit jadi sembuh. Namun kali ini keadaan tidak berubah jadi baik. Seperti ada keganjilan yang terjadi.
Udara memang terasa lebih menyengat kulit, dan angin seperti jarang berembus. Alam seperti berubah, tidak seperti biasanya. Langit sepenuhnya biru, tidak ada awan bergerombol sedikit pun. Burung kedasih yang dipercayai penduduk sebagai penanda keburukan dan kematian bercokol di pucuk pohon meranti, berbunyi nyaring, suaranya seperti memekik-mekik.
Paras wajah Hanjak tampak pucat dan bibirnya membiru. Tubuhnya kejang-kejang hebat, matanya terbelalak, dadanya tersengal-sengal seperti orang yang kehabisan napas. Tanpa siapapun duga, Hanjak mengembuskan napas terakhir.
Mina Sanja hanya mampu menangis.
***
Sehari setelah Hanjak dimakamkan, Danum datang berkunjung Mawinei. Mawinei tersenyum sumringah. Mereka kawan karib selama bersekolah di SD Bukit Tunggal, dan telah lama tidak berakrab-akraban lagi. Sebelum pergi kuliah, Mawinei juga bersekolah SMA di Palangkaraya., Karena jaraknya jauh, dia kos di sana, sedangkan Danum tetap tinggal di desa. Orang tuanya tidak memiliki biaya untuk menyekolahkannya tinggi-tinggi. Untuk sekian tahun, kedua dara ini pun tidak bisa bertemu karena terpisahkan jarak.
“Narai kabar, apa kabar?” kata Danum dengan hati senang, senyumnya merekah lebar. Dia memeluk erat Mawinei yang balas memeluknya dengan hangat.
“Kabar bahalap, en ikau kenampi, kabarku baik, dan kamu? Mawinei memegang kedua bahu Danum, lalu melangkah mundur dan menatap temannya dengan saksama.
Danum tersenyum lebar. Sambil memegang lengan Mawinei, dia berkata, “Kabarkuh bahalap.”
Mereka melepas pelukan, dan duduk bersebelahan di kursi serambi.
“Udara terasa panas ya…” kata Mawinei sambil mengipas-ngipaskan jemarinya ke muka.
“Iya.” Danum terlihat sedih. Dia menarik napas panjang lalu berkata, “awalnya aku kira cuaca yang panas ini membawa penyakit pada warga. Namun, setelah apa yang terjadi pada Hanjak, kemarin, aku yakin semua ini karena Sungai Kahayan yang kotor.”
“Kahayan kotor?” tanya Mawinei sambil menatap sepasang mata Danum yang resah.
“Kau belum tahu, sungai yang kita sering main dulu, kini sangat kotor, airnya bikin gatal-gatal. Tambang-tambang itu buang limbah ke sungai.”
“Tambang?” tanya Mawinei tidak mengerti.
Danum mengangguk mantap.
Benar pula, Mawinei melihat sebagian besar anak yang bermain gundu kakinya busik, korengan.
“Kau sarjana ilmu lingkungan kan, kau bisa teliti air sungai nanti,” kata Danum. Mawinei mengangguk sambil tersenyum.
***
Mawinei dan Danum melangkah melewati kebun durian dan rotan milik Bapa Dukun. Setelah melewati pohon cempedak yang buahnya sering mereka nikmati semasa kecil, mereka tiba di setapak penuh rerumputan. Tampak beberapa huma di lereng bukit terlihat kehijauan penuh kebun sayur yang subur.
Langkah mereka tiba di bibir sungai, dan terkejutlah Mawinei ketika melihat sungai. “Wah, airnya coklat!” teriaknya.
“Sudah tak jernih seperti dulu, padahal lima tahun lalu masih jernih. Katanya karena lahan gambut di hulu sana yang bikin coklat,” kata Danum dengan muka yang sedih.
“Bukan, dulu sungai ini jernih, aneh, sekarang seperti berlumpur,” selidik Mawinei sambil menatap pinggiran sungai.
“Kau masih ingat kan, dulu masa kita kecil, juga kadang minum air sungai ini, tanpa pakai direbus, perut juga tak sakit.” Suara Danum bergetar. Dia mengarahkan pandangannya jauh mengikuti alur sungai yang seperti lumpur cair dengan garis-garis berkilauan di permukaannya.
Mawinei mengangguk. Ingatannya merawang ke waktu masa sekolah dasarnya. Bersama Simpei, Ekot, dan anak-anak lain, mereka sering bermain di situ saat sungai mendangkal. Air sangat jernih dan surut meninggalkan pinggiran yang landai, berpasir agak putih ⸺ tidak berlumpur seperti ini. Mereka asyik bermain pengantin-pengantinan. Danum jadi pasangannya Simpei. Ekot jadi penghulu, dipasangi jenggot dari sabut kelapa di dagunya dengan cara dilem dengan pulut. Si penghulu duduk di gundukan pasir yang dibentuk seperti singgasana. Mawinei jadi saksi pernikahan, ditambah seorang anak lain. Beberapa anak menonton sambil cekikikan.
Hujan yang sebelumnya gerimis, tiba-tiba berubah deras dalam waktu cepat. Upacara perkawinan anak-anak itu langsung buyar. Mereka berlarian cepat untuk kembali ke betang, tetapi jalan setapak sungguh licin membuat sebagian bocah terjatuh dengan bokong kesakitan. Mereka yang tidak jatuh, menertawainya. Sesampainya di rumah, semua anak dimarahi orang tuanya masing-masing. Pagi buta saat berangkat sekolah, sebagian memperlihatkan pahanya yang memerah bekas cubitan ibunya.
Mawinei tersenyum-senyum saat mengingat kejadian itu.
Danum menepuk bahu Mawinei, menyadarkannya dari lamunan.
“Seperti ada bau, tercemar ini,” kata Mawinei setelah mendekatkan tangkupan air di tangan ke hidungnya. Air sungai tampak berminyak, ada cairan tertentu yang tidak menyatu dengan air. Angin berembus kencang. Rambut Mawinei yang sepinggang sebagian berterbangan, menutupi parasnya yang tampak prihatin. Tangannya segera merapikan rambutnya kembali. Dia berkata, “Aku ingin lihat tambang yang kau katakan. Mari kita pergi ke sana.”
“Jangan, jauh di hulu,” kata Danum mencegah, sebelum lanjut, “harus naik perahu. Besok saja sambil ajak Ekot dan Simpei.”
***
Besok paginya, sesudah subuh, Mawinei telah bersama Danum. Simpei dan Ekot juga sudah bergabung. Mereka berempat berkumpul di jalan masuk dermaga kecil di pinggir sungai. Lanting-lanting mulai terlihat. Rumah-rumah yang berdiri di atas sungai itu mengandalkan tiang-tiang kayu ulin yang kokoh, serta didirikan di atas gelondongan kayu dan ditambatkan pada pohon atau tonggak-tonggak yang ditanam di daratan tepi sungai. Beberapa perahu tertambat di pokok-pokok kayu atau tiang-tiang beton. Beberapa lentera di perahu dan di lanting-lanting yang belum dimatikan, masih berpendar syahdu.
Mawinei bersama teman-temannya berniat berangkat pagi-pagi agar waktu lebih panjang karena berharap bisa kembali ke rumah sebelum gelap malam. Gelapnya subuh menuju pagi tidak membuat mereka takut, justru merasa segar.
Mereka berjalan mendekati pinggir sungai, menyusuri dermaga kecil dengan papan-papan kayu dari ulin sebagai jembatan yang menghubungkan perahu dan kapal. Gelaran air sungai yang sebelumnya gelap mulai berkilauan oleh sinar matahari pagi. Ufuk timur berwarna kuning terang. Cahaya matahari yang lembut, membuat orang-orang tampak bersemangat di pagi hari itu.
Seorang bapak mendekati Ekot, dan berbicara tentang harga, sambil menunjuk beberapa perahu ketinting yang tertambat di tepi sungai. Ekot menyanggupi. Mereka menyewa perahu khas Kalimantan yang bisa menampung empat sampai sepuluh orang itu untuk menyusuri sungai hingga sejauh mungkin ke hulu.
Air muka Mawinei tampak sangat gembira, sudah lama dia tidak menyusuri sungai dengan perahu ketinting.
Danum juga terlihat senang saat masuk perahu.
“Kau masih ingat nggak, dulu sering renang di situ,” tunjuk Ekot ke sungai belakang lanting-lanting.
“Iya, tentu, di situ kan?” tunjuk Simpei ke lanting paling besar di antara lanting-lanting lain.
“Oh ya, betul.” Wajah Ekot jadi cerah, tampak gembira membicarakan masa anak-anak yang bahagia.
“Tapi kau takut jumpalitan, payah, kau hanya berani terjun, hahaha,” ejek Simpei.
“Ya lompatanlah,” balas Ekot.
“Iya tapi jumpalitan takut, wekwekwek.” Simpei memukul lengan Ekot membuatnya mengaduh sakit.
Namun, sedetik kemudian Ekot tidak lagi meringis kesakitan, tapi nyengir cengengesan.
“Iya, ngaku kalah, tapi siapa yang berani renang menyeberang, ayo siapa?” ledeknya. Dan Simpei pun terpaksa mengangguk sambil menunjuk Ekot. Memang Ekot anak paling berani berenang menyeberang sungai walaupun arusnya deras. Anak-anak lain takut keterbawa arus. Mereka hanya berenang sepanjang tepian.
Mereka, sebagaimana anak-anak Kalimantan lain di tepi Sungai Kahayan, tidak perlu belajar renang pada siapa pun. Kehidupan nenek moyang mereka tidak pernah jauh dari kehidupan sungai. Sejak bayi, mereka sudah dimandikan di sungai. Oleh ibu, tubuh mereka diapung-apungkan di air, sehingga secara alami sejak kecil sudah pandai mengapung. Makin beranjak besar, biasanya sepulang sekolah pada siang jelang sore hari, saat masih terik, mereka akan terjun ke sungai, berenang sepuasnya, dengan gaya apa pun yang mereka bisa lakukan. Ada gaya katak, lumba-lumba, bebas, macam-macamlah, yang penting bisa berenang dan tidak tenggelam. Sesekali mereka juga membawa bola untuk permainan, lempar sana lempar sini, diperebutkan.
Juru mudi perahu duduk paling belakang mengendalikan perahu dengan mesinnya, terkadang menggeser tungkai mesin ke kiri dan ke kanan mengikuti jalur sungai.
Ekot duduk paling depan, disusul Simpei, Mawinei, dan Danum.
Suara mesin menderu, menyibak air, menciptakan arus dan mendorong perahu melaju kencang. Zaman dulu, perahu didayung dengan bilah kayu ulin yang liat dan kuat. Kini alat yang canggih telah memudahkan manusia untuk bisa cepat sampai tujuan.
Sungai membentang lebar kecoklatan. Gelaran airnya beriak-riak. Beberapa perahu melintas berlawanan arah. Di antaranya seorang nelayan dengan jala di perahunya, tampak hendak menjaring ikan di sungai.
Di bantaran kedua sisi sungai, tumbuh pepohonan lebat. Rimbunan bambu, serta pohon buah-buahan macam pisang, nangka, durian, karamunting, dan jambu monyet juga banyak tumbuh.
Tanah Kalimantan yang bergambut merupakan lahan subur untuk pohon-pohon buah semacam itu. Sungai besar ini mengalir sepanjang enam ratus kilometer dari Pegunungan Muller atau Pegunungan Raya yang membelah Palangkaraya, Kabupaten Pulang Pisau, dan Kabupaten Gunung Mas di Kalimantan Tengah, sampai akhirnya bermuara di Laut Jawa.
Simpei mengeluarkan rokoknya, mengambilnya sebatang. Korek api digeretnya, lalu ujung rokok itu disentuhkannya pada api. Simpei mengisap dalam-dalam rokoknya, lalu memberikan bungkusan rokok beserta koreknya kepada Ekot.
Ekot menolak halus.
Wajah Simpei tampak nikmat setelah mengisap rokok sembari menikmati empasan angin di atas perahu yang melaju.
Pohon loa, yang kokoh dan besar, sesekali terlihat di tepi sungai menjadi tameng agar pinggiran sungai tidak tergerus. Buah-buahnya yang merah disukai monyet, tupai, dan burung.,
Perahu makin menjauhi permukiman. Lanting-lanting sudah tidak kelihatan. Sesekali terdengar bunyi burung-burung dan pekik bekantan dari hutan. Pinggir-pinggir sungai masih ditumbuhi pepohonan dan rimbunan hutan karamunting.
Mereka menyusuri sungai di bawah jembatan dan makin melaju menuju hulu. Wajah pinggir-pinggir sungai mulai berbeda. Daratan pinggir sungai banyak terbuka lebar oleh kegiatan masyarakat. Air terlihat makin coklat dan berbuih.
“Orang-orang sukanya ikut-ikutan, karena harga karet mahal, semua pada nanam karet, hutan pada ditebangi untuk diganti kebun karet. Kini orang-orang pada keblinger menanam sawit, kalau sawit milik rakyat tak seberapa, tapi kalau milik perusahaan sampai ribuan hektar, pohon-pohon hutan habis ditebangi,” keluh Ekot.
“Harga karet sudah lama turun, orang-orang tak mau menyadap getah karet lagi, sekarang lihat, kerjaan masyarakat cari emas,” tunjuk Simpei.
Di daratan terlihat kegiatan masyarakat menambang emas. Tanah-tanah di pinggir sungai telah rusak, tidak ada kehijaun tanaman sama sekali. Tanah berlumpur coklat menciptakan air berbuih yang kotor. Daratan jadi becek, penuh kubangan air coklat. Alat tambang, sebuah kotak yang menyambung panjang dan lurus untuk “menangkap” emas, menjulur hingga ke sungai.
Gubuk-gubuk penambang berserakan di dekat mesin diesel. Dan selang-selang besar menggelontorkan air ke bawah. Tanah-tanah bagian atas sungai tergerus dengan kocoran air yang disemburkan oleh selang-selang raksasa, membuat daratan pinggir sungai longsor dan langsung terjun ke sungai, tak hanya menciptakan kerusakan sungai tapi juga pendangkalan.
Bahkan sebagian alat-alat tambang itu berdiri di atas sungai, berlandaskan kayu-kayu ulin seperti rumah-rumah lanting. Pipa-pipa membentang ke sana-sini, mencurahkan air kotor, menggempur tanah, dan membuang segala lumpur langsung ke sungai.
Sungai tidak hanya berlumpur, tetapi juga bercampur dengan minyak tumpahan solar sisa mesin diesel. Kilau-kilau minyak di permukaan air sungai memendar berwarna kebiruan tersapu cahaya matahari, mengilat-ngilat berbentuk bundaran-bundaran yang kemudian hanyut menjauh. Mesin terus menderu, tanpa henti, menggaruk tanah dasar sungai yang diyakini ada bijih-bijih emas. Kilau-kilau minyak itu bercampur dengan merkuri yang sangat berbahaya bagi lingkungan hidup. Dengan memanfaatkan sifat merkuri yang berupa air raksa sebagai pelarut, nantinya emas akan dengan sendirinya terpisahkan dari bebatuan lainnya.
“Berarti karena tambang-tambang ini yang bikin perut anak-anak sakit, pada gatal-gatal semua, karena merkuri,” kata Mawinei.
Danum mengangguk mantap.
Perahu mereka berjalan pelan. Ekot mengeluarkan kameranya, dan sesekali dengan diam-diam memotret kegiatan tambang emas itu. Beberapa penambang tampak waspada saat perahu mereka agak dekat.
“Kini hal sama terulang, bukan Belanda atau Jepang yang kita lawan, tapi keserakahan manusia merusak alam, dan yang paling menyedihkan mereka sebangsa dengan kita,” kata Ekot sedih.
“Anugerah Tuhan sesungguhnya tak pernah sepadan dengan uang,” tambah Mawinei.
Perahu terus melaju, dan Mawinei tampak makin prihatin melihat begitu banyak tambang bertebaran di pinggir-pinggir sungai. Sekelompok orang menjalankan alat yang berbeda dengan sebelumnya yang mereka lihat, ditambah kapal keruk dan pompa air. Alat itu makin besar daya rusaknya dalam menggerus bibir sungai, menciptakan lumpur dan endapan-endapan kotor yang jauh lebih banyak. Di sepanjang bantaran sungai, terdapat banyak lubang menganga berisi lumpur.
“Besok aku akan menemui Idris, kawanku di LSM. Kita tak bisa biarkan ini terus terjadi,” kata Ekot.
“Kalian belum tahu yang terjadi di hutan sana,” Simpei menunjuk ke ladang gundul di perbukitan samping kanan dari sungai dan lanjut, “itu tambang batubara yang jauh lebih besar membuat hutan gundul. Tak hanya itu, juga kebun sawit milik perusahaan,” tambah Simpei.
“Iya itu juga. Beberapa anak mati tenggelam saat bermain di bekas galian tambang yang dibiarkan terbengkalai,” sahut Ekot dengan wajah meredam amarah.
“Yang jadi danau itu?” tanya Simpei.
Ekot mengangguk.
“Kita tak bisa biarkan semua kejahatan ini terus berlangsung!” teriak Mawinei
***
Beberapa hari kemudian, Idris, Ekot, dan Mawinei menemui pegawai pemerintah daerah yang bertugas mengurusi bagian pertambangan. Danum dan Simpei terpaksa menunggu di luar karena hanya dibatasi tiga orang yang bisa masuk ruangan petugas. Mereka sebelumnya telah mengambil contoh air sungai dan Mawinei menelitinya di makmal di Kota Kuala Kurun. Hasilnya menunjukkan terjadi pencemaran air sungai yang sangat tinggi.
“Sebagian besar tak berizin,” kata pegawai itu.
“Kami tak bisa melarang karena mesin tambang mereka berdiri di atas tanah hak mereka. Punya surat izin tanah juga,” tambahnya.
“Iya Pak, tapi akibatnya terjadi pencemaran lingkungan, dampaknya ke kita semua, kepentingan bersama atas sungai itu terganggu,” kata Idris keras.
“Masalahnya, alasan mereka itu untuk mata pencaharian, untuk cari nafkah. Kalau dihentikan, apa kalian mau ngasih mereka pekerjaan, ngasih mereka makan?” sahut bapak itu tidak mau kalah.
“Ya tetap harus ditertibkan, Pak. Bukan masalah orang cari nafkah, tapi tambang itu pakai merkuri, Pak, itu yang berbahaya,” jawab Ekot tegas.
“Jangan sampai ada yang kehilangan nyawa, Pak,” Mawinei ikut tambah kata, wajahnya tampak geram. “Banyak yang sakit perut, mencret,” katanya dengan gusar.
Mawinei menyerahkan berkas keluhan warga di kampungnya yang sudah ditandatangani banyak orang.
Ekot menyerahkan berbagai foto dan bukti rekaman kegiatan tambang itu.
Idris menyerahkan hasil penelitian air sungai dari makmal.
“Iya kalian tunggu saja, kami akan segera bertindak.” kata petugas yang mulai mengerti kerisauan anak-anak muda itu setelah melihat bukti-bukti yang lengkap.
***
Sebulan setelah pertemuan itu, tambang-tambang tidak berizin dihentikan. Bahan merkuri disita. Namun, banyak tambang lain yang masih berjalan. Suatu perusahaan tambang yang mendapat dukungan kekuasaan yang sangat besar mengajukan para pengacara untuk melawan laporan LSM yang dipimpin Idris. Para pegawai pemerintah daerah itu pun tidak mampu bertindak lebih jauh lagi.
“Setidaknya kita telah berjuang, pencemaran air sungai ini telah berkurang,” kata Mawinei mencoba sedikit menenangkan Idris yang masih tidak terima.
Danum mendesah, matanya menerawang gelisah.
Simpei menghisap rokoknya dalam-dalam.
“Tambang-tambang besar, terutama batubara, sulit dihentikan karena menghasilkan pendapatan yang besar bagi pemerintah,” kata Ekot dengan wajah masam.
“Jadi, perjuangan kita masih panjang, kawan,” kata Mawinei yang disambut anggukan kawan-kawannya.
“Iya dan jangan mudah menyerah!” seru Danum tegas.
*****