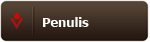Kain Tapis Mak Unyan
Jauza Imani, ibu dua anak laki-laki, mulai giat menulis sejak 2016. Tulisannya tergabung dalam beberapa buku kumpulan, baik cerpen, cerita anak, maupun puisi.
Bekerja sama dengan penyair Kurnia Effendi menerbitkan buku puisi berjudul Piknikita (Penerbit Basabasi, 2021). Cerita anak Cerita Pertama Untuk Rara, diterbitkannya sendiri pada September 2021 melalui Penerbit Epigraf. Kumpulan puisi tunggal, Hujan Kau Selalu Begitu, diterbitkannya sendiri pada Maret 2017 melalui Penerbit Gong Publishing.
Siger Nunu Ketinggalan terpilih sebagai salah satu dari lima naskah cernak terbaik dalam Sayembara Cerita Anak yang diselenggarakan oleh Toonesia x IKSI yang diumumkan pada 22 November 2022 bertajuk Tak Kenal Maka Tak Indonesia.
Kini Jauza giat di Dewan Kesenian Lampung, tergabung dalam Penyair Perempuan Indonesia, Komunitas Nulis Aja Dulu, Dapur Sastra Jakarta, Hari Puisi Indonesia, serta beberapa kelompok sastra lainnya.
Pertanyaan terbaik dari Jauza Imani: Apakah ada saran khusus untuk melatih kepekaan calon penulis agar dapat menangkap inti dari peristiwa yang mampu menghanyutkan perasaan pembaca?
Jauza dapat dihubungi melalui surel: nurhikmah.imani126@gmail.com dan telepon/WA 081-1122-2126.
*****
Kain Tapis Mak Unyan
Berita tentang hilangnya kain tapis di Pekon Way Sindi membuat desa di Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung itu geger! Berita itu bukan sekadar berita biasa. Kain tapis itu akan digunakan sebagai penutup jenazah Mak Unyan, dukun beranak desa itu yang meninggal dunia pada dini hari.
“Di dipa tapis seno?” Terdengar suara Masri yang menggelegar di tengah suasana duka. Lelaki tua berperawakan kurus tinggi itu menanyakan keberadaan kain tapis milik Mak Unyan yang dibuat saat istrinya itu masih remaja. “Khadu kusegok ko, tibungkus dilom lemari!” Dalam logat bahasa Lampung yang kental, Masri seolah-olah berbicara kepada semua pelayat yang hadir di rumahnya. Dia merasa sudah membungkus dan menyimpan kain itu dalam lemari.
Tangan Masri bergetar saat mengaduk-aduk isi lemari kayu yang sudah reyot dimakan usia. Pakaian sederhana milik Mak Unyan berserakan di lantai. Baju dan celana panjang miliknya pun ikut terjelempah. Masri penasaran karena baru dua minggu lalu dia merapikan lemari bersama Mak Unyan usai salat Subuh berjamaah di rumah.
***
Masri masih ingat betul saat istrinya mengeluarkan bungkusan kain tapis itu dan menunjukkan kepadanya. Seolah-olah pertanda bahwa kain itu hendak digunakannya dalam waktu dekat.
Terdengar kembali pertanyaan Mak Unyan, “Sudah berapa puluh tahun usia tapis ini, ya?” yang dijawabnya sendiri, “Lupa, saya.” Tangannya yang renta merentangkan satu-satunya kain yang dia banggakan. Setidaknya, dengan kain tapis itu dia bangga dilahirkan sebagai gadis Lampung.
Pikiran Masri sekadar menerawang ke saat itu. “Ai, nah! Lupa juga, saya!” timpalnya sambil tertawa kecil memperlihatkan gigi ompongnya. Gigi sampingnya di kanan dan kiri tampak jelas sesaat dia lanjut, “Waktu itu kamu sikop nihan!” Masri teringat memuji istrinya yang cantik jelita di saat hari bahagia mereka. “Saya tunggu kamu sampai selesai membuat tapis itu. Biar bisa saya lamar. Dan, kamu memakainya saat pernikahan kita.”
Larut dalam kenangan, Masri mendekati Mak Unyan yang saat itu duduk di ranjang besi peninggalan neneknya. Bentangan kain tapis masih di pangkuan istrinya. Masri ikut memegang ujung kain tapis itu. Warna benang emasnya belum memudar. Hasil sulaman tangan Unyan – sangat rapat dan rapi sesuai dengan sifatnya yang rajin dan telaten, apalagi dalam merawat bayi. Pantas saja dia menjadi dukun beranak yang terkenal. Dalam hati, Masri mengucap syukur bisa mempersunting Unyan yang menjadi rebutan pemuda-pemuda sebaya di kampungnya sekian tahun yang lalu.
Di benak Masri muncul kembali secara jelas Mak Unyan yang tersenyum bahagia karena dia masih ingat kisah kain tapis itu dan pernikahan mereka. Ingatan Masri melayang ke masa lalu. Usai akad nikah dinyatakan sah oleh para saksi barulah Unyan keluar dari kamar. Semua mata memandang ke arahnya dengan decak kagum. Kecantikan istrinya menjadi sempurna karena dia mengenakan kain tapis yang indah ⸺ susunan benang emasnya rapat dan halus serta berkilau memukau ⸺ hasil sulamannya sendiri.
Masri teringat Mak Unyan yang masih saja tersipu bila dibilang cantik olehnya. Saat itu, kedua tangan yang digunakan Mak Unyan untuk membantu persalinan sebagai dukun beranak di pekon Way Sindi, menutupi wajahnya yang bersemu merah. Semua guratan berebut tampil di wajahnya yang kini tidak berdaging lagi seperti dahulu. Masri mengundang kembali dan mempertahankan kenangan itu.
“Selamat, ya! Anakmu perempuan.” Ucapan seusai membantu persalinan seorang warga itu selalu dilanjutkan dengan pesan khas Mak Unyan. “Dang lupa, sanak muleimu ditawaiko napis!” Dia selalu mengingatkan warga yang ditolongnya untuk mengajari anak gadisnya membuat tapis.
Bagi masyarakat adat Lampung di kampung mereka, membuat kain tapis adalah keharusan. Sejak kecil, sepulang sekolah, selain mengaji, anak-anak perempuan belajar menenun dan menyulam kain yang berbentuk sarung itu dengan benang emas atau benang perak. Coraknya pun beragam. Di antaranya adalah Raja Medal yang menampilkan pernak-pernik berbentuk manusia; Laut Linau yang menunjukkan kupu-kupu; dan Tapis Inuh yang terpengaruh oleh hal-hal tersangkut dengan laut.
Masri yakin, tentu saja Unyan tidak akan lupa dengan tata cara menapis yang merupakan peninggalan leluhur ratusan tahun lalu. Tapis Inuh yang dipilihnya terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya yang akrab dengan laut, misalnya, kapal, rumput laut, dan hewan laut. Meski penyelesaian membuat kain tapis itu memakan waktu berbulan-bulan, Unyan dan perempuan lain di kampungnya tetap bersabar bahkan seakan berlomba merampungkannya. Kelak, saat hari pernikahan mereka tiba, kain tapis itu akan dipakainya sebagai seorang pengantin. Demikian juga saat kematian datang, sebagai penghargaan dan penghormatan terakhir, kain tapis itu pula yang akan digunakan untuk menutup jenazahnya.
***
Masri masih mencari kain tapis Mak Unyan. Kini pencarian berpindah ke lemari di kamar Bayan, anak lelaki semata wayang yang hingga kini belum menikah. Mekhanai Tuha. Selama ini Bayan tidak tertarik dengan gadis-gadis di desanya. Katanya, dia tidak menemukan seorang mulei yang sepandai ibunya dalam hal membuat tapis. Konon, hasil sulam tapis seorang perempuan bisa menunjukkan sifat sang pembuatnya, apakah dia seorang yang penyabar, penyayang, pemarah, rajin, pemalas, atau yang lainnya.
Ada satu gadis yang paling dewasa umurnya di antara mereka. Gadis itu, Suri namanya, terkenal paling lamban dalam menapis. Bahkan Suri tertinggal jauh oleh penapis-penapis di bawah usianya. Sudah lama dia menaruh hati kepada Bayan. Meski lambat, lantaran berharap barangkali saja Bayan berkenan melamarnya, dia berusaha menyelesaikan tapisnya. Namun, Bayan tidak mengacuhkannya.
Sambil melihat ayahnya mencari kain tapis di lemarinya, Bayan teringat saat Mak Unyan bertanya, “Kapan kamu menikah, Bayan?”
Bayan memahami perasaan ibunya yang sudah tua. Pasti, dia ingin mendampingi anaknya hingga ke pelaminan dan mewariskan kain tapis buatannya kepada menantu dan cucunya kelak, andai dia sudah tiada.
“Nantilah, Mak,” Bayan teringat dia menjawab pelan saat itu.
“Mak khadu tuha,” terngiang di kuping Bayan ucapan ibunya yang lirih. Karena tidak ingin melukai hati ibunya, saat itu Bayan hanya terdiam. Sedangkan, ibunya seakan-akan memberi restu dengan berkata, “Suri anak baik, lajulah! Mak lihat dia menapis Inuh juga seperti Mak,”
“Jangan paksa Bayan, Mak,” Bayan ingat kembali ketika membujuk pelan ibunya seraya melangkah meninggalkannya.
“Bukan memaksa. Kekalau kalian berjodoh!” Suara ibunya yang berandai-andai, sayup-sayup masih terdengar di telinga Bayan.
***
Berita meninggalnya Mak Unyan dan hilangnya kain tapisnya menyebar cepat terbawa angin. Para tetangga dan kerabat yang datang selain sebagai pelayat juga ingin membuktikan kebenaran berita itu. Mereka seolah-olah berebut cepat datang untuk berbelasungkawa sekaligus menaruh tanda kasih. Mereka agaknya juga mencari bahan cerita.
Sebagian besar pelayat pasti tidak percaya dengan pemandangan di depan matanya – jenazah Mak Unyan tanpa kain tapis. Hampir tidak mungkin perempuan yang telah menikah tidak memiliki tapis buatannya sendiri. Apalagi Mak Unyan yang sesekali terlihat mendatangi gadis-gadis yang sedang menapis selama ini dikenal sebagai orang yang cerewet mengingatkan akan pentingnya anak gadis membuat tapis.
Detak jam dinding di ruang tamu tidak pernah berhenti. Namun, bagi Bayan kehidupannya seakan-akan sudah berakhir. Dia berduka kehilangan ibunya. Terbayang hari-hari indah bersamanya. Namun, suara ayahnya yang menggelegar menyadarkannya dari lamunan panjang.
“Bayan! Niku pandai di dipa tapis seno?” tanya Masri kepada Bayan, memastikan tahu tidaknya Bayan tentang keberadaan tapis Mak Unyan. “Ngeliak tapis seno, mawat?” tanya Masri, memastikan sekali lagi.
“Nyak mak pandai,” jawab Bayan. Suara lemahnya berusaha meyakinkan ayahnya bahwa dia tidak tahu. Pikirannya yang sedang kalut memaksanya berkata bohong kepada ayahnya di depan jenazah ibunya. Keributan yang ditimbulkan oleh lenyapnya kain tapis itu kini menyadarkannya betapa pentingnya benda itu bagi keluarga dan masyarakat adat di kampungnya.
Rumah panggung itu kian ramai didatangi tetangga. Pasangan sandal berjajar di anak tangga pertama dan kedua bagian bawah. Meski angin berembus dari sela-sela susunan kayu, ruangan itu terasa gerah karena banyak orang.
Masri membuka satu dari dua daun jendela lebar di sisi kanan ruangan. Dia sejenak memandangi kebun rambutan di samping rumah. Dengan begitu dia dapat menyembunyikan mata merahnya dari pandangan orang-orang. Dia berusaha menjinakkan gemuruh di dadanya yang menderanya sejak diketahuinya kain Mak Unyan tidak ada di lemari. Suara ayam jago berkeruyuk semakin jelas terdengar. Masri mendengarnya seperti celoteh cibiran yang dilagukan.
“Bayan, coba kamu pinjam saja tapis milik kerabat. Tidak apa. Usahakan agar ibumu bertapis, setidaknya sesaat sebelum dimakamkan, sebagai bentuk penghormatan kepada almarhumah,” bisik seorang pengtuha, orang yang dituakan di pekon Way Sindi, kepada Bayan. Sang pengtuha itu tidak ingin pelayat yang mestinya berduka malah bergunjing tentang hilangnya tapis Mak Unyan.
Di saat Bayan mengangguk menyetujui saran sang pengtuha, Suri datang bersama keluarganya. Mendengar kabar hilangnya tapis Mak Unyan, Suri, yang rumahnya tidak jauh dari rumah Mak Unyan, teringat kebaikan Mak Unyan selama ini sebagai tetangga dekatnya. Suri meminta izin kepada keluarganya dan bergegas kembali ke rumahnya. Dia berniat untuk meminjamkan kain tapis yang baru saja diselesaikannya.
“Nerima nihan, Suri.” Bayan mengucapkan terima kasih dan menerima kain tapis dari tangan Suri. Pandangan mereka sesaat bertemu. Bayan sempat melihat kesungguhan di mata Suri. Bayan seakan menemukan bukti dari kata-kata ibunya kala itu. Benar, Suri adalah perempuan yang baik.
“Jejama, dengan senang hati,” jawab Suri pelan tetapi hangat. Baru saat itulah dia bertatapan langsung dengan Bayan. Suri merasakan jantungnya berdegup lebih cepat. Dalam hatinya dia bertanya, mengapa selama ini, laki-laki yang berada di hadapannya itu, begitu acuh kepadanya? Dengan sedikit kikuk Suri membantu melepas ikatan pada bungkusan kain itu dan membiarkan Bayan yang membentangkannya.
Bayan mengganti kain panjang yang menutupi jenazah Mak Unyan dengan kain tapis milik Suri, perempuan yang pernah dipuji ibunya, tetapi selama ini tidak dia pedulikan. Ada rasa sesal menyusup di hatinya yang sedang berduka. Sementara itu, Suri tampak ikhlas kain tapisnya digunakan pertama kali untuk kematian Mak Unyan, bukan di hari pernikahan dirinya. Rasa haru pun diam-diam menyelinap di hati Suri.
Suasana duka dan khidmat berlangsung di ujung persemayaman jenazah Mak Unyan. Sejak tadi di rumah kayu itu ayat-ayat Alquran dilantunkan. Sesekali terdengar isak tangis dari beberapa pelayat yang datang bercampur dengan bisik-bisik tentang Suri dan Bayan.
Masri berhenti mencari kain tapis Mak Unyan ketika dilihatnya jenazah istrinya sudah tertutup tapis. Meski demikian, amarah di wajahnya sulit disembunyikan. Di antara sedih dan kesal dia mencoba bersabar sambil menerima uluran tangan pelayat yang turut berbelasungkawa.
Bayan terduduk lemas di samping jenazah ibunya. Dia tidak sanggup berdiri menegakkan badan untuk memberi penghormatan kepada para pelayat yang masih berdatangan. Ingatannya melayang kepada perempuan bule yang dia temui di Pulau Pisang seminggu lalu.
“Sarrah.” Suara perempuan bule itu masih terngiang-ngiang di telinga Bayan saat dia menyebutkan namanya dan menjabat tangan Bayan. Kecantikannya membuat Bayan terpukau dan tidak bisa melupakannya. Wisatawan dari Australia yang baru saja dikenalnya itu berbicara banyak tentang indahnya kebudayaan Indonesia. Salah satunya adalah kain tapis, warisan budaya takbenda dari Lampung. Dia sengaja datang ke Indonesia, khususnya ke Provinsi Lampung, untuk mengadakan penelitian tentang tapis dan menuliskannya.
“Saya datang ke sini untuk melihat kain tapis,” ujar Sarrah saat itu dengan bersemangat meski terbata karena menggunakan bahasa Indonesia. “Saya dengar kain tapis yang dibuat di desa ini terkenal karena sulamnya rapi dan coraknya indah,” lanjutnya.
“Betul sekali!” ucap Bayan dengan bangga. Dia merasa bisa membuktikannya. Dia melihat sendiri bagaimana indahnya kain tapis yang dibuat oleh gadis-gadis di desanya. Apalagi kain tapis milik ibunya.
***
Sekarang, sambil duduk di samping jenazah ibunya, Bayan mengutuk dirinya sendiri. Berkali-kali dia mengusap wajah dan kepalanya. Dia seperti melihat ratusan gulungan benang emas. Bahan untuk menyulam kain tapis itu menari-nari mengelilinginya. Wajah ibunya yang sudah tertutup rapat di sampingnya pun tampak di pelupuk mata.
Bayan menyesali tindakannya yang gegabah tanpa berpikir panjang. Kini, meski jenazah ibunya sudah ditutupi oleh kain tapis milik Suri, tetapi hati Bayan justru semakin galau. Dia membayangkan ibunya yang bersusah-payah membuat kain tapis. Namun, di akhir hidupnya, kain itu malah tidak bisa digunakan untuk dirinya sendiri. Bayan tiba-tiba beranjak dari tempat duduknya menuju pintu.
“Bayan! Bayan! Haga dipa?” Suara-suara para pelayat yang menanyakan dia hendak ke mana, tidak dihiraukannya – termasuk panggilan ayahnya dan Suri. Bayan mula-mula melangkah cepat, kemudian berlari dan terus berlari menembus semak belukar. Hatinya berteriak dalam kebimbangannya.
Bayan tahu harus ke mana dia menuju, ya, ke arah pondok kecil tidak jauh dari pantai yang jendelanya menghadap ke laut. Jarak sekira tiga kilometer itu berusaha ditempuhnya dengan melalui jalanan tidak biasa agar tidak terlihat orang. Dia harus mendapatkan kembali kain tapis milik ibunya, sebelum jenazah Mak Unyan terlanjur dibawa ke luar rumah untuk dikebumikan.
*****