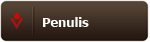Aku Tidak Ingin Tubuh Ranummu
Ouda Teda Ena lahir di Sleman, 17 Oktober 1970. Menyelesaikan sarjana dan magister di Pendidikan Bahasa Inggris, Universitas Sanata Dharma, sedangkan gelar doktor pendidikan diperolehnya dari Loyola University Chicago, Amerika Serikat. Sekarang Ouda adalah dosen di almamaternya, Pendidikan Bahasa Inggris, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta. Senang menulis di waktu luangnya, terutama menulis puisi dan cerita kilat. Tulisannya telah dibukukan dalam novelet Arok Berkaca Dedes: Sebuah Novelet Intrik Politik Berdarah, Perempuan dalam Almari: Kumpulan Puisi, dan Hampir Chairil: Kumpulan Kisah Kilat.
Ouda bisa dihubungi di ouda.art@gmail.com
Hak cipta ©2018 ada pada Ouda Teda Ena. Terbit atas izin dari penulis. Hak cipta terjemahan ©2018 ada pada Laura Harsoyo.
Aku Tak Ingin Tubuh Ranummu
Lelaki itu sudah mengawasinya semenjak belia. Mulai dari ia masih kuncup, lalu ketika mekar. Dia seperti terbius baunya yang semerbak segar. Tiap pagi dia mengintip dari jendela sambil menghisap rokok kreteknya. Asap dikepulkan perlahan keluar dari mulutnya bersama baris-baris mantra. Matanya jalang dan nanar, ingin segera memetiknya jika saatnya tiba.
***
Sejak semalam tidurnya telah tak nyenyak. Bantalnya yang hangat, sarung tenunnya yang lembut tak mampu melelapkan tidurnya. Ayam masih berkokok bersahutan sesekali. Langit di timur mulai berwarna biru cerah. Embun di daunan mulai menjatuhkan diri ke tanah. Lelaki itu tak sabar menunggu matahari. Dia kalungkan sarungnya ke leher dan bergegas ke sumur. Ditimbanya seember air, dibasuhnya wajahnya untuk mengusir sisa-sisa kantuk.
Diambilnya keranjang bambu. Tangga bambu ditentengnya. Dia pandangi perdu kopinya, rimbun dan subur, buahnya yang ranum memerah menyembul di ranting-ranting di antara dedaunan yang hijau tua atau menguning. Segera dipasangnya tangga bambu menyeruak ke dalam kerimbunan pokok kopi. Perlahan-lahan dia naiki tangganya, setapak demi setapak. Setiap naik satu langkah, nafasnya menghirup dalam-dalam segar udara pagi yang dipenuhi wangi daun dan buah kopi.
Pada sebuah ranting yang besar dia mendadak berhenti. Sepasang mata hitam coklat sebesar kelereng melotot menatapnya. Tatapan yang penuh kebencian, penuh kemarahan, bercampur sedikit ketakutan. Gigi tajam dan runcing dia pamerkan penuh ancaman.
Lelaki itu terkesiap, darahnya mendidih memanaskan kepala. Dia tahan marahnya dalam kemeretuk giginya.
Mata mereka beradu.
Degup jantung lelaki itu menggetarkan ranting-ranting pohon kopi. Cemburunya memuncak, memompa seluruh darahnya ke kepala. Sejenak hilang akal sehatnya. Didih darah di nadi-nadinya menggetarkan tubuhnya. Hampir saja tangannya yang kokoh menghantam remukan kepala binatang jalang yang mendahuluinya memetiki buah kopinya.
Kesadaran kemanusiaan dan kasihnya kepada alam mengekang gerakan tangannya, yang didorong oleh sebuah naluri kebinatangan. Lalu rasa cintanya menyunggingkan senyum.
“Aku manusia dan kau adalah binatang.” Bisiknya kepada si luwak yang mencuri buah kopinya.
Mata luwak itu masih melotot, giginya masih menyeringai. Wajah marah penuh kebencian. Dia mendesis seakan ingin menerkam leher si lelaki dan membunuhnya. Luwak itu merasa terdesak dan akan melakukan apa saja untuk tetap dapat menikmati ranum merah buah-buah kopi itu.
“Aku dikarunia hati untuk mencinta dan kau hanya dikarunia naluri untuk bernafsu.” Berbisik lagi lelaki itu pada si luwak.
Luwak itu tetap pada marahnya. Matanya semakin melotot, seringainya semakin penuh nafsu membunuh.
“Kau tak paham kawan. Kau hanya tergiur pada kemolekan ranum merah daging buah kopi. Kau tak paham sejatinya kopi.” Suara lelaki itu tetap berbisik.
Ia tak mau mengusik luwak yang marah. Ia tak mau membahayakan diri sendiri.
“Kau hanya suka daging buahnya yang merah ranum manis segar berair. Ambilah kawan… ambilah. Makanlah sepuasmu, aku tak butuh itu.” Lelaki itu tersenyum pada binatang yang marah itu.
“Aku rela menunggu kau membuangnya dari ususmu. Kau hanya mengunyah dagingnya, lalu membiarkannya bercampur kotoran dilorong-lorong ususmu yang menjijikan. Tapi disitulah hatinya ditempa. Ketika kau membuangnya, ketika kau tak telah menikmati daging dari tubuhnya, yang tersisa hanyalah hatinya. Hati semulia mutiara hitam.” Lelaki itu mulai menuruni tangga perlahan. Merelakan buah-buah kopinya dilalap rakus sang luwak.
“Kalau kau paham bahasaku, kuberitahukan padamu, sejatinya kopi ada di bijinya, di hatinya.” Bisiknya pada si luwak sebelum dia meninggalkannya.
“Dan hati sebutir kopi pun harus rela hancur dan diseduh supaya ia mengeluarkan wangi, memberikan rasa sehingga hati seorang manusia tertambat padanya,” guman lelaki itu sambil menimang sebutir kopi di tangannya.
***