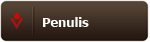Belenggu Emas
Iksaka Banu lahir di Yogyakarta, 7 Oktober 1964. Menamatkan kuliah di Jurusan Desain Grafis, Fakultas Seni Rupa dan Desain, Institut Teknologi Bandung. Iksaka mulai menulis sejak usia sepuluh tahun. Majalah Kawanku dan Rubrik Anak Kompas memuatkan tulisannya. Pada tahun 2000, cerita pendeknya dimuat di majalah Matra, Femina, Horison, dan Koran Tempo. “Mawar di Kanal Macan” dan “Semua untuk Hindia” terpilih menjadi salah satu dari 20 cerpen terbaik Indonesia versi Pena Kencana berturut-turut tahun 2008 dan 2009. Kumpulan cerpennya “Semua Untuk Hindia,” (Gramedia 2014), meraih penghargaan Kusala Sastra Khatulistiwa untuk kategori prosa.
Iksaka bisa dihubungi di iksaka@yahoo.com
Hak cipta ©2017 ada pada Iksaka Banu. Terbit atas izin dari penulis. Hak cipta terjemahan ©2017 ada pada Maya Denisa Saputra.
***
Belenggu Emas
Ruang tamu ini sangat nyaman. Mungkin karena semua jendelanya dibuka lebar sehingga udara sejuk Koto Gadang bisa leluasa masuk, membawa pergi sisa kepenatan tubuh akibat terguncang-guncang selama enam jam di dalam kereta api uap milik Soematra Staatsspoorwegen yang bertolak dari Padang kemarin siang.
Kulirik Nyonya Joanna Adriana Westenenk yang duduk di sebelahku. Kurasa ia juga merasakan keletihan yang sama meski sudah terbiasa bertandang ke wilayah-wilayah jauh semacam ini.
Tujuh tahun yang lalu, suaminya Louis Constant Westenenk, menjadi terkenal karena keberhasilannya dalam mengatasi Kerusuhan Kamang yang disebabkan penolakan penerapan pajak di Kamang pada bulan Juni 1908. Kini ia menjabat sebagai Residen Benkoelen.
Aku berteman baik dengan Nyonya Westenenk, tetapi tidak menduga bahwa ia benar-benar menepati janji, mengajakku ke tempat ini. Sebuah tempat yang menurutnya akan membuat mata sekaligus hatiku terbuka lebar. Tentu saja perjalanan ini di luar kegiatan resmi suaminya. Dan aku merasa sedikit nekat bepergian sejauh ini hanya berdua saja dengan Nyonya Westenenk. Bertiga, sebetulnya. Karena selalu ada ajudan yang menemani Nyonya Westenenk.
“Louis tak bisa menemani,” kata Nyonya Westenenk kemarin. “Ada sejumlah acara di Padang bersama Asisten Residen dan para pemuka adat setempat.”
Aku mengiyakan. Seharusnya suamiku juga diundang mengikuti acara itu, tetapi ia telanjur ditugaskan kantornya ke Solok bersama beberapa Kepala Insinyur lain. Bulan lalu ia sudah mengirim surat permintaan maaf kepada Asisten Residen.
Maka, di sinilah aku sekarang. Bebas mengikuti kata hati. Ya, sudah lama aku menginginkan petualangan liar semacam ini, meski tampaknya aku harus lebih sering melatih kesabaran, duduk berlama-lama di atas bangku kereta api yang keras. Setiba di Fort de Kock, kami beristirahat semalam, lalu pagi hari tadi berkereta kuda ke tempat ini.
Tak jauh berbeda dengan rumah-rumah Hindia lain yang biasa dimiliki pejabat bumiputera terpandang, rumah besar. Empat keping jendela gaya Prancis menjadi penyeimbang di kiri-kanannya pintu depan. Ada pula bangunan tambahan, memanjang di kedua sisi rumah utama. Mirip ruang kelas. Itulah bagian yang sesungguhnya paling penting dari bangunan ini. Ingin sekali aku segera melongok isinya, yang konon telah membuat gempar banyak pejabat Belanda di seantero Hindia. Tetapi tentu saja aku harus sabar menunggu hingga tuan rumah muncul.
“Onne biasa datang sekitar jam setengah sepuluh,” kata wanita dalam busana Minang yang tadi menyambut kami. “Dan bila tak ada keperluan lain Onne akan terus di sini hingga sore hari,” sambungnya sambil menyuguhkan dua cangkir teh hangat serta sejumlah kudapan. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Zaiza, atau barangkali nama lain yang kurang-lebih berbunyi seperti itu. Bahasa Melayunya bercampur dengan logat setempat. Agak sulit bagi telingaku yang sudah sangat terbiasa mendengar Bahasa Melayu Batavia atau Melayu Jawa.
“Terima kasih. Kami memang datang terlalu pagi. Tak apa, kami akan menanti kedatangan beliau.” Nyonya Westenenk mengangguk.
Zaiza minta izin kembali ke belakang.
“Onne adalah nama panggilan wanita yang akan kita temui nanti,” bisik Nyonya Westenenk. “Artinya: kakak.”
Aku mengangguk, lalu memutar pandangan ke beberapa sudut ruangan. Di hadapanku, dekat jendela, berderet buku berbahasa Belanda, Arab, dan Melayu. Tersimpan rapi di dalam sebuah lemari berkaca dengan empat ambalan. Di ujung kanan ada rak pendek, sarat tumpukan koran terbitan dalam dan luar negeri. Sementara di sisi kiri tergantung sebuah potongan kain yang dikerjakan dengan kehalusan yang menakjubkan. Mungkin itu salah satu contoh tenunan yang dikerjakan di sini. Dan terakhir, di atas meja, tampak terbitan terbaru sebuah koran yang belum lama ini menjadi perbincangan hangat di antara kami. Benar-benar ruang tamu yang sarat peradaban.
Bukan hal aneh menjumpai pemandangan serupa itu di ruang tamu para pejabat Belanda. Tetapi saat ini aku tengah berada di dalam sebuah bangunan yang jauh dari keramaian kota, milik seorang pribumi. Tepatnya, seorang wanita pribumi.
Seolah mengerti yang kupikirkan, Nyonya Westenenk menyentuh pundakku sembari melempar senyum.
“Ini belum semuanya, Nellie,” bisiknya. “Tunggu sampai kau berbicara dengannya. Dengarkan pemikiran-pemikirannya.”
“Ya, Nyonya,” sahutku. “Banyak berita tentang orang ini. Seharusnya aku malu. Ia berani menyuarakan dirinya sendiri di tengah tekanan hebat lingkungannya. Sementara aku, lihatlah, betapa menyedihkan diriku di hadapan suami.”
“Berhentilah menyalahkan diri.” Nyonya Westenenk memperbaiki letak sarung tangan putih berpola renda yang dikenakannya. “Hindia Belanda tidak sama dengan Eropa. Di sini semua berjalan lebih lambat. Bahkan orang kulit putih pun tak bisa melangkah gegas. Tetapi bukan berarti kita tak sudi merentangkan kedua tangan lebar-lebar menyambut perubahan yang sedang menggeliat. Perubahan yang sebentar lagi membuat lompatan besar di seluruh penjuru dunia ini. Di Barat, di Timur, di seluruh penjuru dunia, wanita sedang bergerak.”
“Dan suami Anda sungguh luar biasa, membiarkan Anda pergi ke sini hanya ditemani olehku dan seorang ajudan, sementara aku harus mencuri waktu selagi suami bertugas ke luar kota.”
Kulirik jendela. Tampak Joep, ajudan Tuan Westenenk sedang asyik bercakap dengan kusir kereta yang tadi mengantar kami ke sini.
“Louis sama saja dengan pria-pria lain di dunia. Pernah terlihat rapuh, tidak percaya diri, bahkan sangat tidak ramah kepadaku saat berkobar kerusuhan Kamang tujuh tahun lalu,” Nyonya Westenenk kembali memahat senyum tipis di wajahnya yang tirus. “Tetapi setelah perang berlalu, ia kembali seperti yang kukenal sebelumnya. Memberi banyak kelonggaran. Dengar, aku tak ingin mencampuri urusan rumah tanggamu. Aku lebih dahulu kenal dengan Theodor Makenbrug, suamimu, dibandingkan dirimu. Ia teman dekat Louis. Sejauh yang kutahu, tak ada yang salah dengannya. Kalau tampak keras, barangkali karena ia mengkhawatirkanmu. Belum terbiasa melihat istrinya ikut sengsara, berpindah-pindah rumah di negeri ini. Louis dulu juga begitu.”
“Saya rasa semua memang tergantung dari mana kita melihat, Nyonya. Betul, ia baik hati dan setia. Itu satu hal,” kataku sambil bangkit, berjalan mendekati dinding dekat lemari buku yang menyimpan foto keluarga. Cukup aneh melihat banyak foto manusia di rumah ini. Biasanya, sesuai tafsir agama yang mereka anut, keluarga Muslim Minang pantang memindahkan wajah ke atas sehelai kertas foto. Aku dengar, menurut mereka haram membuat tiruan ciptaan Allah. Tetapi rupanya keluarga ini bukan hanya terbiasa berfoto, mereka tahu persis bagaimana tampil anggun di depan kamera. Anak-anak lelaki berdiri gagah dalam seragam kelasi Victoria seperti yang biasa dikenakan para sinyo Belanda, sementara anak-anak perempuan mengenakan gaun dan sepatu putih. Dari semua sosok yang terpampang di situ, harus kuakui bahwa pemilik rumah ini ternyata memang telah memiliki tatapan sangat tajam sejak masa kanak-kanak.
“Theo setia. Aku tidak mengeluhkan Theo dari sisi itu,” aku melanjutkan bicara. “Dan barangkali Anda benar. Masuk akal bila semua itu membuatnya sangat khawatir. Tetapi untuk hal lain…” aku tidak merampungkan kalimat, karena kulihat Nyonya Westenenk tidak menyimak. Ia sibuk membolak-balik koran yang ia ambil dari rak. Kuurungkan pula niat untuk mengajaknya kembali membicarakan pokok masalah awal.
Ya, aku tidak mengeluhkan Theo dari sisi kebaikan hati dan kesetiaan. Tak pernah kudengar sedikit pun berita miring tentang dirinya. Padahal setiap malam hampir semua kelab, baik di Batavia, Bandung, atau Semarang sarat kisah perselingkuhan. Mulai dari yang menggelikan, hingga yang mengerikan.
Aku bertemu Theo pertama kali di Singapura pada suatu petang yang sejuk oleh siraman hujan tiga tahun lalu. Seorang teman ayahku berulang tahun. Kami merayakannya dengan meriah di Singapore Club, sebuah perkumpulan para pialang saham yang terletak di lantai atas Hotel Adelphi. Sejak kematian Ibu, aku sering menemani Ayah pergi ke segala pelosok. Termasuk menghadiri acara di tempat-tempat khusus semacam ini. Dan seperti mendiang Ibu dahulu, aku juga berperan sebagai malaikat penjaga. Tak ingin melihat Ayah kelewat mabuk sehingga harus digotong pulang.
Malam itu, kubiarkan Ayah melayari kegembiraan masa lalu bersama teman-temannya di meja bilyar, sementara aku memilih menyendiri di kursi besar dekat beranda dengan sebuah buku, mengenakan kebaya putih, serta sarung panjang. Menjauh dari gerombolan lelaki yang tak putus berteriak, “Boy, lagi, setengah!” sambil mengacungkan gelas wiski kosong kepada pelayan.
Beberapa wanita berkumpul juga di ruangan ini, tetapi tak ada seorang pun yang kukenal, dan aku terlalu malas untuk berbasa-basi. Jadi, kubenamkan saja wajahku pada halaman buku.
Maka di sudut itulah beberapa saat kemudian, seperti penyulap yang muncul secara gaib dari balik tirai, seorang pria mendadak berdiri di depanku, mengangsurkan segelas cherry brandy. Wajahnya sangat Belanda. Penuh sudut di sana sini. Di atas bibir, sepotong kumis berwarna gelap menjulur rapi. Serasi dengan jas hitam yang dikenakannya.
“Lihatlah, betapa meriah malam ini. Seorang bidadari berkulit putih dalam balutan sarung Melayu, berkelana menyusuri bait-bait Tagore,” katanya. “Tetapi kusarankan engkau mencoba dahulu sekecap dua kecap minuman ini. Dan aku menyebut diriku sendiri Makenburg. Theodor. Panggil saja Theo. Insinyur di salah satu perusahaan ayahmu.”
“Cornelia. Nellie. Terima kasih. Suka Tagore?” kujemput gelas dari tangannya seraya mengutuk dalam hati keisengan ayahku menyodorkan orang ini. Tapi tidak seperti pria-pria pilihan Ayah sebelumnya, kurasa kali ini aku bertemu orang yang bisa kupertimbangkan lebih jauh. Ya. Getaran halus itu. Aku bisa merasakannya.
“Aku sering mendengar orang membicarakan Gitanjali.” Sangat berhati-hati Theo duduk di sebelahku. “Sayang sekali, untuk lelaki yang setiap hari bergaul dengan besi, mur, dan beton, sangat langka kesempatanku membaca karya sastra dunia. Tetapi engkau boleh yakin bahwa aku tidak melewatkan Max Havelaar. Sungguh berguna untuk orang yang ingin bertandang ke negeri asal kisah itu ditulis.”
“Itu salah satu buku kesukaanku. Setelah membaca, ada semacam panggilan untuk memperbaiki keadaan di sana. Seperti yang dikatakan Rudyard Kipling dalam salah satu sajaknya…”
“The White Man’s Burden?” potong Theo.
Kutinju lengannya sambil mecibirkan bibir. “Lihat, ada seorang pendusta di sini. Kau penggemar sastra pula rupanya!”
Kami tergelak.
“Engkau menyukai wanita yang gemar membaca buku sastra?” pancingku.
Theo mengangkat bahu, memanjangkan bibir sejenak sebelum menjawab sambil tersenyum, “Asakan ia juga gemar membaca buku resep makanan Eropa dan Hindia.”
“Ah, tidak suka wanita yang mandiri? Bagaimana pendapatmu tentang Aletta Jacobs?”
“Demi Tuhan, Nellie. Kita sedang berada di tengah suasana gembira. Dan kau mengajakku berkelahi!” seru Theo sambil mengangkat kedua tangan, memasang kuda-kuda bertinju.
Kami tertawa.
Itu pembicaraan awal kami yang sangat bersahaja. Setelah itu, Theo mulai kerap bertandang ke rumah kami di Singapura. Sekali-dua mengajak aku dan Ayah bersantap malam di luar. Enam bulan kemudian kami menikah. Menjelang dua tahun usia pernikahan, setelah lelah menunggu kehadiran jabang bayi yang tak kunjung tiba, memaksa agar diperbolehkan mengikuti Theo menduduki posnya yang baru di Batavia. Melalui pertengkaran sengit, akhirnya Theo bersedia membawaku serta.
Kami tinggal di kawasan Gunung Sahari. Sebuah wilayah dekat pantai. Udara di situ sangat panas dan lembab. Tiada hari tanpa keringat, sehingga aku lebih sering mengenakan kain-kebaya dibandingkan pakaian Eropa. Seperti anjuran seorang rekan wanita Ayah, aku selalu mengenakan kebaya putih. Selain memantulkan panas, putih adalah warna kebaya kelas atas yang sebaiknya dipilih oleh wanita Eropa bila ingin memakai busana gaya tropis. Aku juga semakin terampil menggulung rambut tinggi-tinggi. Kini leher dan kuduk terbebas dari rasa gatal akibat panas.
“Aduh, Nyonya. Cantiknya!” Asih, babu kami, menggoda.
“Seperti Dewi Nawangwulan,” Mang Udin, kusir bendi langganan kami ikut menimpali. Entah apa yang ada di pikiran mereka melihatku berpakaian seperti itu. Tetapi menurutku mereka tampak senang.
Setelah kami pindah ke Padang, aku tetap berpenampilan demikian. Awalnya Theo tidak memberi tanggapan apapun soal rambut dan pakaianku. Namun pada suatu sore tiba-tiba ia mengajakku duduk di tuinhuis, jauh dari penglihatan para jongos dan babu kami.
“Ada baiknya engkau tidak terlalu sering berpakaian seperti itu,” ia menunjuk kebaya dan kainku. “Terutama di tanah Sumatera ini. Barangkali akan jauh lebih baik bila engkau tidak pernah lagi mengenakan semua itu.”
“Oh, mengapa?” aku terperanjat. “Apakah aku melanggar suatu larangan yang dikeramatkan di sini?”
Theo mengisi pipa gadingnya dengan tembakau. “Memang, ada kaitannya dengan mereka, tapi ini soal lain. Bukan perkara keramat. Coba pindahkan sebentar sudut pandangmu ke pihak kita.”
Aku terdiam. Berusaha berpikir keras, namun tetap tidak menemukan sesuatu yang keliru. Sebenarnya aku bahkan samasekali tak mengerti apa yang dikatakan oleh suamiku.
“The white man’s burden. Ingat?” Theo meloloskan serangkaian asap dari mulutnya beberapa kali. “Kita ingin mengubah keadaan, mengubah mereka. Bukan berubah menjadi mereka. Bukan merendahkan diri di hadapan para babu, jongos, atau tukang bendi. Aku tak pernah suka dengan orang Inggris, tetapi aku setuju pendapat Raffles dan Kipling. Orang kulit putih harus menjadi teladan untuk segala hal. Termasuk berbusana. Coba lihat, meski Raffles sangat memahami budaya daerah, bahkan menulis buku tentang Hindia, ia melarang pejabat memakai kain atau mengunyah sirih.”
“Ah, begitu rupanya,” aku menghela napas. “Tadinya kukira aku telah melanggar aturan setempat. Ternyata persoalannya jauh lebih sederhana.”
“Ini bukan persoalan ringan,” mendadak suara Theo meninggi membuatku menarik tubuh ke belakang.
“Maaf,” kataku lirih. “Tetapi hampir semua istri pejabat Eropa di Singapura tidak risih mengenakan sarung atau cheong sam. Para suami bahkan secara berkala mengenakan baju gaya Tiongkok. Sejauh yang kuingat, hal itu tidak menurunkan wibawa mereka di depan jongos maupun babu. Di Batavia kemarin, semua warga Belanda juga memakai sarung, kebaya, dan baju takwa. Engkau tidak merasa terganggu?”
“Kita bukan di Batavia,” Theo mengetuk pipa, membuang sisa abu. “Di sini orang masih mudah menghunus parang untuk alasan yang sulit kita cerna. Kita harus tegas, sedikit keras. Harus diingatkan bahwa jarak dengan kita tetap ada. Salah satunya dengan cara saling menjaga kehormatan. Mengenakan busana masing-masing. Jarak dan ketegasan akan memunculkan rasa segan, yang pada gilirannya akan membangun kepatuhan. Setelah patuh, mereka bisa kita didik, kita bentuk menjadi lebih baik. Semua untuk kebaikan mereka juga akhirnya. Dan tentu semua ada tahapannya. Bayangkan, di belakang kita boleh jadi mereka membuat lelucon. Menganggap kita seperti badut saat mengenakan busana mereka. Bagaimana pula perasaanmu melihat seorang jongos memakai jas?”
“Jongos? Tentu saja. Tetapi para bupati kerap mengenakan jas dan baju pesiar gaya Eropa. Kita tidak keberatan, bukan? Dan Nyonya Westenenk….”
“Ah, Adriana itu. Meski istri pejabat tinggi, ia jenis wanita yang tidak bisa kau jadikan panutan. Kehadirannya di rumah sangat langka. Kasihan Louis. Adriana tidak bisa seenaknya mempergunakan dalih pekerjaan sosial untuk bepergian ke sana ke mari tanpa suami di sisinya.”
“Ia tidak plesir, Theo. Aku tahu apa yang ia lakukan dengan wanita-wanita pribumi, baik di Agam maupun di Benkoelen. Ia memberi ruang bagi mereka untuk berkembang. Dan setahuku suaminya mendukung.”
“Louis tak tahu apa-apa tentang tata krama. Itulah yang memaksaku menemuimu sore ini. Aku tak mau kau bertingkah seperti Adriana. Ia seperti penyakit menular. Siapa yang ia dekati, berubah menjadi liar. Aku tak ingin orang bergunjing tentang dirimu. Selain itu, hendak kalian apakan wanita-wanita pribumi itu? Kalian ingin mereka melompat-lompat dengan kaki terangkat ke atas menari cancan? Di Eropa, engkau mungkin bisa jungkir balik menabrak tradisi. Seperti Aletta Jacobs, pujaanmu itu. Bekerja di luar rumah atas nama sendiri. Bahkan menuntut hak memilih wakil rakyat. Tetapi sekali lagi, tidak di sini!” Theo menyimpan pipanya lalu masuk ke dalam rumah, meninggalkanku sendiri ditaman dengan sejuta kegundahan.
Hari itu senantiasa kuingat dalam hidup, karena merupakan awal pertikaian tak berkesudahan dengan suamiku. Ada saja yang ia persoalkan. Pilihan makanan, cara bicara dengan babu, jongos, atau larangan bergaul dengan seorang nyai yang tinggal di dekat kami. Celakanya, semua selalu berujung pada pengurangan hak-hak istimewaku. Semakin lama ruang gerakku semakin sempit. Belakangan, lewat sebuah keributan hebat, ia tidak lagi memperbolehkanku membeli koran walau masih boleh menikmati buku. Kubalas perlakuannya dengan pindah tidur ke kamar lain. Kukunci pintu. Lalu kuhabiskan malam-malam panjang dengan menulis sajak atau karangan lain dalam berlembar kertas.
Akhirnya kemarin, saat Theo sedang pergi ke Solok, aku nekat mengikuti ajakan Nyonya Westenenk ke Koto Gadang. Kusuap jongos dan babu agar tidak menceritakan peristiwa ini kepada Theo. Ini kesempatan langka. Aku harus bertemu dengan wanita Minang yang luar biasa ini. Wanita yang telah menjadi ilham banyak orang di Hindia. Yang telah mendirikan sekolah, memberi bekal ketrampilan menenun, menjahit, serta membordir bagi kaumnya, agar tidak semata menggantungkan nafkah dari belas kasihan suami, atau sekadar menjadi perhiasan tak bernyawa. Serta yang paling penting, agar tidak jatuh kelembah nista, menyewakan tubuh untuk bertahan hidup saat suami mereka meninggal.
Tiga tahun lalu wanita ini bahkan maju lagi selangkah, menjadi pemimpin sebuah surat kabar khusus wanita. Sungguh, semakin bulat tekadku ke sini. Aku ingin diperbolehkan sesekali mengisi ruang pendapat pembaca di dalam surat kabarnya. Membantunya membuka belenggu emas yang sering dipasang kaum pria untuk mengecoh wanita.
“Ah, Nellie. Apakah tumpukan buku itu mengganggu pendengaranmu?” suara serak Nyonya Westenenk menarik sukmaku kembali ke ruang tamu besar yang sejuk ini. “Lihat, yang kau tunggu sudah datang. Pendiri sekolah Amai Setia dan pemilik suratkabar Soenting Melajoe. Beliau sendiri. Tak lain dan tak bukan.”
Kuikuti arah pandang Nyonya Westenenk.
Seorang wanita berusia tiga puluhan berdiri di pintu masuk. Kulihat wanita yang kuimpikan itu. Berdiri dengan tas rotan tersampir di pundak. Ia lebih pendek dari yang kubayangkan. Bahkan terlihat semakin mungil dengan kain ikat berwarna kesumba di kepalanya. Tetapi aku bisa melihat jelas semangat hidup yang berkobar dari kedua belah matanya. Juga dari kuatnya genggaman saat ia menyambut uluran tanganku serta berkata dengan suara lantang dalam bahasa Belanda yang sangat fasih, “Ik ben Roehana Koeddoes. Welkom op de ambachtschool genaamd Amai Setia. Van mevrouw Westenenk heb ik vernomen dat u een interessant manuscript over vrouwen heeft voor mijn krant. Saya Roehana Koeddoes. Selamat datang di Sekolah Kerajinan Amai Setia. Saya dengar dari Nyonya Westenenk Anda punya banyak naskah menarik tentang dunia wanita untuk surat kabar saya?”
***