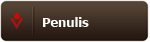Dasamuka (Bab 9)
Pemenang penghargaan Junaedi Setiyono sejak 1997 mengajar di almamaternya: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Universitas Muhammadiyah Purworejo, Jawa Tengah.
Junaedi tertarik menulis fiksi sejarah yang berkaitan dengan Perang Jawa (1825-1830). Naskah novel pertamanya, Glonggong, (Serambi 2007) memenangkan Sayembara Menulis Novel Dewan Kesenian Jakarta Tahun 2006 dan masuk pilihan terakhir Khatulistiwa Literary Award Tahun 2008. Novel keduanya, Arumdalu (Serambi 2010) memenangkan pilihan Khatulistiwa Literary Award Tahun 2010. Pada 2012, naskah novel ketiganya, Dasamuka (Ombak 2017) kembali memenangkan Sayembara Menulis Novel Dewan Kesenian Jakarta. Pada tahun yang sama, novel tersebut diterjemahkan dalam Bahasa Inggris dan diterbitkan oleh Dalang Publishing. Pada tahun 2020 Dasamuka meraih pemenang penghargaan sastra dari KEMDIKBUD.
Junaedi berharap bisa membagi keyakinannya bahwa manusia sudah semestinya bebas dari sekat-sekat suku, agama, bangsa, atau golongan melalui penulisan. Dia percaya bahwa sastra mampu mempersatukan umat manusia seluruh dunia.
Di samping mengerjakan novel sejarah berikutnya, yang berlatar kerajaan Jawa di Abad ke-12, Junaedi mengadakan penelitian tentang pengajaran Bahasa Inggris yang dapat mendukung pengajaran Bahasa Indonesia di Indonesia.
Junaedi dapat dihubungi lewat alamat surelnya: junaedi.setiyono@yahoo.co.id
Bab 9
Rara Ireng sudah mulai terbiasa hidup sebagai buronan. Dia sudah memakai pakaian terbaiknya yang dilengkapi dengan gelang dan kalung pemberian Danar. Bagi Rara Ireng, perjalanan ke Salatiga punya makna istimewa: dia akan bertemu dengan keluarga suaminya untuk pertama kalinya. Kecantikannya yang menyala sungguh berkebalikan dengan keadaan di sekitarnya.
Berjalan di antara mayat-mayat berkubang darah di halaman depan rumah menjadikan batin Rara Ireng terguncang. Dengan tubuh menggigil dia menaiki tangga kereta yang dikusiri oleh Kang Bewok. Dengan cepat mereka meninggalkan tempat persembunyiannya.
Danar dan Den Wahyana duduk siaga menghadap ke belakang membuka mata waspada mengamati jalanan di belakangnya. Mereka masing-masing siap dengan dua senapan berpelor.
Siang itu mega putih menyeraki langit biru. Awan-awan itu bentuknya cukup aneh, panjang-panjang menyerupai tombak-tombak yang dijajarkan. Sudah lebih dari empat belas kilometer jarak ditempuh oleh kereta kuda itu. Mereka sudah bisa sedikit santai dan berani melihat ke arah lain, tidak selalu ke arah belakang. Sampai tiba-tiba mereka melihat dua titik di kejauhan.
Pegangan tangan Den Wahyana pada gagang senapan kembali mengencang.
Dua titik yang makin membesar yang akhirnya mewujud dua orang penunggang kuda yang dicongklang meninggalkan kepulan debu kekuningan di belakangnya. Segera setelah itu tampak penunggang kuda lainnya mengikuti dua penunggang kuda itu. Sekarang mereka menjelma menjadi sepasukan prajurit berkuda yang menderap mendekati kereta.
Den Wahyana menepuk bahu Dasamuka, “Kita mulai permainan kita hari ini. Mungkin permainan yang paling seru.”
“Ya, Den. Aku sudah siap,” kata Danar mantap sambil menoleh ke arah istrinya. “Diajeng, kau berlututlah di bawah. Gelar saja jarit-jaritmu di lantai kereta, agar guncangannya tidak menyakiti lututmu. Ada sedikit urusan yang perlu kami selesaikan secepatnya.”
Penunggang kuda yang ada di paling depan makin mendekati kereta kuda, namun Kang Bewok, atas perintah Den Wahyana, tidak menambah kecepatannya. Menurut bekas panglima perang itu tidak ada gunanya berpacu dengan kuda-kuda perang milik keraton.
“Jangan menembak kalau mereka tidak memulainya,” Den Wahyana memperingatkan.
“Kelihatannya mereka sudah siap menembaki kereta kita.”
“Begitu mereka memulai, langsung saja kau balas. Aku bagian yang kiri, kau yang kanan.”
Dan, meletuslah bunyi tembakan pertama dari penunggang kuda paling depan. Tembakan itu berhasil membuat kuda-kuda kereta menjadi oleng dengan derap lari yang tidak lagi berirama. Namun, tembakan jitu Den Wahyana telah berhasil menjungkalkan penunggang kuda yang mungkin tidak mengira akan ada perlawanan yang begitu cepat terencana. Penunggang kuda satunya langsung mengendurkan laju kudanya, dia tidak ingin bernasib seperti temannya. Dia memberi perintah pada penunggang lainnya yang sudah menyusul untuk menyebar.
Danar mencoba menghitung kuda-kuda garang yang dicongklang untuk mengejar keretanya. Ada dua puluh pemburu. Sekarang lima di antaranya berusaha mendekat dari arah kiri, sedang lima lainnya dari arah kanan. Pengejar yang lain tampak menjaga jarak.
Den Wahyana dan Danar saling pandang, keduanya sepakat untuk menghabisi sebelum dihabisi. Mereka membidik para penunggang kuda yang melaju hendak menjajari kereta. Ada empat penunggang terpental dan terguling di jalanan. Satu penunggang kuda yang berhasil menggapai atap kereta langsung muntah darah setelah tulang iganya rontok disodok gagang senapan Danar. Sebelum pemburu itu terlontar ke jalanan, Danar sempat melihat kalung yang melingkari lehernya yang menunjukkan jati diri pasukan khusus keraton. Lima penunggang kuda lainnya memperlambat kudanya, mereka menjauh tapi masih pada sisi kanan dan kiri kereta.
Lima belas penunggang kuda yang ada dibelakang sudah mulai menghujani kereta dengan tembakan-tembakan. Jelas itu pertanda kekalapan. Peluru-peluru berdesingan di sekitar kereta. Agaknya mereka mengubah siasat. Bila tadi mereka ingin menangkap penumpang kereta hidup-hidup, sekarang mereka sudah tidak peduli lagi akan hidup-mati orang yang hendak dibekuknya.
Den Wahyana pun sudah tidak lagi segan-segan memuntahkan pelornya ke arah gerombolan yang mengejarnya. Lagi, tiga pemburu sudah terjengkang sebelum bergulingan di atas tanah berdebu. Masih ada dua belas pemburu yang mengejar dan menembaki kereta dengan gencar.
Den Wahyana dan Danar sudah hampir kehabisan peluru. Pada saat Danar mengisi pelor senapannya, didengarnya suara rintihan.
Rara Ireng yang duduk berlutut dengan kepala tertelungkup mengerang lirih.
Danar segera merambat mundur dan merangkul tubuh yang terguncang-guncang itu. Begitu tangannya basah oleh darah, sambari dengan hati-hati merebahkan istrinya di kursi kereta, dia berteriak ke Kang Bewok.
Tidak ada jawaban dan Danar melihat tubuh kusir itu oleng sebelum rubuh ke samping. Darah memancar keluar dari luka tembak pada bagian rusuknya. Satu tangannya masih memegang tali kendali.
Pada saat Den Wahyana sudah kembali menewaskan tiga orang pemburunya, tubuh Kang Bewok sudah terguling di lantai kereta.
Sekarang tinggal sembilan orang pemburunya yang masih dengan buas mengejarnya.
Begitu menyadari mesiu sudah habis, Den Wahyana mengeluarkan tombak-tombak kecilnya.
Seakan sudah mengerti apa yang tengah bergolak di benak Den Wahyana, Danar yang sudah menggantikan kusir, memperlambat keretanya. Dia meneriakkan kata-kata sandi pada Den Wahyana sebelum dia bawa kereta menepi ke kiri. Sawah yang membentang di kanan jalanan telah menguatkan keputusannya. Saat kesembilan pemburunya sudah berderet berada di kanan kereta, dengan tiba-tiba, kereta dibelokkannya dengan tajam ke arah sawah yang menguning di sebelah kanannya.
Benturan dahsyat tak dapat dihindarkan. Para penunggang kuda bertumbangan sebelum akhirnya bergulingan di jalanan. Ada dua pemburu yang terlindas roda kereta. Kereta yang berderak-derak masuk ke sawah yang sudah siap dipanen itu berhenti setelah salah satu rodanya lepas menggelinding.
Den Wahyana, yang sudah memperkirakan apa yang hendak dilakukan Danar, segera melompat turun dan menghunjamkan tombak-tombak yang sudah dipersiapkannya di dada dan perut para pemburunya yang bergelimpangan di jalanan dan di persawahan. Dia juga melihat ada tiga penunggang kuda yang berhasil lepas dari terkaman bahaya yang diciptakan Danar. Mereka sudah memutuskan untuk lari secepatnya dan sejauhnya untuk menyelamatkan nyawanya masing-masing. Sementara itu dua lainnya sedang berusaha keluar dari kubangan lumpur sawah.
Danar melompat keluar dari kereta. Dia menghabiskan sisa peluru senapannya untuk menjungkalkan dua orang yang mencoba lari. Pada saat dia memburu yang lainnya, Danar mendengar bunyi tembakan di belakangnya. Dia tahu bahwa Den Wahyana menghabisi nyawa dua orang lainnya yang terperosok di kubangan lumpur sawah. Orang yang dikejarnya menggunakan tenaga yang masih tersisa padanya untuk lari secepat yang dia dapat. Dengan bersenjatakan tombak Danar terus memburunya. Tak lama kemudian orang itu kehabisan tenaga dan jatuh tersungkur dengan wajah menelungkup di tanah.
“Siapa yang menyuruhmu!” teriak Danar pada orang yang jatuh tengkurap di tanah persawahan. Danar tidak mendengar adanya jawaban. Dengan kakinya, tubuh orang itu digelimpangkan. Sekarang orang itu terbaring telentang.
“Paman Mangli? Kaukah itu, Paman?” mata Danar tak berkedip menatap wajah orang yang sudah hampir seluruhnya tersaput oleh hitamnya lumpur dan dan merahnya darah.
“Bunuh aku, Danar,” lenguh orang yang telentang dengan kedua tangan menjulur ke arah Danar.
“Siapa yang menyuruh Paman memburuku?” Danar tak mempedulikan erangan pamannya.
“Bunuh aku, Danar,” pinta orang itu sekali lagi. Suaranya tidak lebih keras dari keresek daun padi yang dihembus angin.
“Kalau kau merahasiakan siapa orang yang menyuruhmu, tentu aku tak segan-segan membunuhmu. Siapa orang yang mengupahmu? Jawab!”
“Bunuh … bunuh saja aku ….”
Tombak yang erat dipegang Danar menancap dalam, mengoyak jantung Den Mas Mangli. Semburat darah segar muncrat memerciki dahi Danar.
Sekarat yang sangat singkat. Hanya ada suara berkeruh-keruh di tenggorokan sebelum lepasnya nyawa.
“Danar! Kautolong istrimu!” teriakan Den Wahyana telah menyadarkannya dari gejolak perasaannya. Dia telah menghabisi nyawa kakak ibunya, pamannya sendiri, orang yang pernah begitu sering membawanya berkuda ketika dia masih kanak-kanak dulu.
Danar bergegas meninggalkan mayat pamannya dan tergopoh mendatangi istrinya di kereta yang terpuruk miring.
Rara Ireng masih berada di atas kursi kereta. Hanya saja sekarang tubuhnya sudah bersandar pada dinding kereta yang miring. Bercak darah yang ditinggalkan tubuhnya yang bergeser tampak memerahi kursi kereta dan jarit-jarit bikinan Nyi Canting di bawahnya. Jarit truntum yang dipakainyalah yang paling banyak terbercaki noda darah.
Danar tak bisa berkata apa-apa, tak mampu berbuat apa-apa. Danar hanya bisa mencium kening istrinya yang sudah pasi memucat. Hangat airmata suaminya menetes didahinya.
“Kakang Danar,” Rara Ireng merintih lirih.
Danar masih tak mampu berkata-kata.
“Kalau aku mati … Kakang akan menikah lagi?” suaranya nyaris tak terdengar. Bulu mata lentiknya bergerak-gerak.
Danar masih juga tak mampu berkata-kata. Dia cuma bisa menggeleng-gelengkan kepalanya.
“Terima kasih, Kakang .…” Dan kemudian terkulailah tubuh Rara Ireng, tubuh yang sudah berhasil menjaga kesucian sebagai seorang istri.
Danar, lelaki yang biasa hidup bersama kerasnya kerikil jalanan dan kotornya lumpur selokan, tersedu-sedu pilu di sampingnya. Lalu, dengan tangan lunglai, dia ambil dan kumpulkan satu persatu jarit-jarit yang kusut tertindih tubuh. Kemudian, dengan kaki gontai, dia bawa dan gelarkan jarit-jarit yang basah ternoda darah. Rara Ireng, yang dengan lembut dibopong dan dibaringkan Danar di atas jarit-jarit kesayangannya, tampak begitu jelita, sejelita Nawangwulan sang bidadari yang tengah tidur nyenyak di peraduannya.
Sementara itu, Den Wahyana pelahan berjalan menjauhi kereta. Dia ingin memberikan kesempatan pada Danar untuk melampiaskan dukanya. Di bawah atap sebuah dangau di sawah dia berhenti. Dari sana dia lihat peristiwa yang menggetarkannya.
Danar melangkah keluar dari dalam kereta. Tampak dia membopong tubuh istrinya yang terbalut jarit-jarit kesayangannya. Dia berjalan tertatih-tatih membelah tanah persawahan menuju pohon kantil yang berada di tepi sawah.
Di bawah kerindangan dedaunan, Danar membaringkan tubuh Rara Ireng. Beberapa saat dia berlutut di sampingnya. Kemudian, dia pelahan bangkit dan mulai berjalan mengitari jasadnya.
Den Wahyana terhenyak saat Danar menengadahkan wajahnya, memekik parau, dan meninju udara kosong di atasnya dengan tangannya yang terkepal.
Untuk telinga Den Wahyana, pekikan liar Danar itu tiada beda dengan raungan murka binatang luka.
Awan yang berleret-leret seperti jajaran tombak pelahan menggembung dan mengubah dirinya menjadi gelembung-gelembung raksasa. Bulatan-bulatan yang kemudian berangsur menyatu itu pelahan menutupi birunya langit. Kelabu pun berkuasa. Mendung pun menggelayut, menemaramkan pepohonan dan persawahan.
Lalu hujan pun turun. Gerimis tipis. Kemudian makin lebat. Ada petir menyambar.
Den Wahyana berjalan mendekati pohon kantil berhujan-hujanan. Dia memberanikan diri untuk mendatangi sosok yang sekarang sedang berdiri mematung di bawah pohon kantil dengan tubuh istrinya yang terbujur beku di hadapannya. Pada saat jaraknya sekitar semeter dari Danar, dia dengan lembut mencoba mengajaknya bicara. Bekas panglima perang itu bergidig pada saat Danar menatapnya.
Kenyerian batin yang membayang di mata Danar tampak begitu liar mengerikan.
*****
Cuplikan ini ditampilkan dengan izin khusus dari penulis. Novel karya asli Dasamuka pada saat ini tidak tersedia.