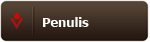Lolong Anjing di Bulan
Arafat Nur lahir di Medan, 22 Desember 1974. Sejak usia SD pindah ke Aceh dan hidup dalam kecamuk perang saudara hingga dia dewasa. Sejumlah peristiwa di Aceh dituliskannya dalam puisi, cerita pendek, dan novel. Di sela-sela kesibukannya sebagai petani dan pekerja serabutan, dia gemar membaca buku-buku sejarah, filsafat, dan sastra.
Lampuki (Serambi, 2009) merupakan novelnya yang memenangkan Sayembara Novel Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) 2010 dan meraih Khatulistiwa Literary Award 2011. Novelnya, Burung Terbang di Kelam Malam (Bentang Pustaka, 2014) telah diterjemahkan ke bahasa Inggris dengan judul A Bird Flies in the Dark of Night. Novel terbarunya Tanah Surga Merah (Gramedia, 2016) kembali memenangkan Sayembara Novel DKJ 2016. Arafat bisa dihubungi di arafatnur@yahoo.com
Hak cipta ©2018 ada pada Arafat Nur. Terbit atas izin dari penulis. Hak cipta terjemahan ©2018 ada pada Maya Denisa Saputra.
Bab 1
Kehadiran Orang-Orang Pejuang
Suatu petang di bulan Juli 1989, kedai kopi Leman di Tamoun tiba-tiba sesak oleh kerumunan manusia. Terdengar keriuhan orang-orang yang bersorak-sorai. Keriuhan itu tiba-tiba senyap ketika Arkam membuka suara. Suaranya yang lantang menembus keluar kedai itu.
Satu dua lelaki dan perempuan, dengan pakaian kerja mereka yang kotor, masih terus berdatangan menghampiri kedai. Sementara matahari sudah condong ke barat. Bentuknya seperti sebuah lingkaran cahaya yang tersangkut di jajaran pucuk pohon kemiri. Setengah sinarnya tercurah terang ke pasar Tamoun membentuk bayangan panjang pada setiap benda dan juga pada satu dua orang yang sedang berlalu di jalan menuju kedai Leman.
Arkam menunjukkan secarik kain merah bergambar bulan bintang yang dikatakannya bendera. Bendera semacam itu tidak pernah dikibarkan di Alue Rambe. Aku dengar bahwa Panglima Perang Wilayah Pereulak, Ishak Daud, adalah orang pertama yang mengibarkan bendera itu di salah satu SMA di Aceh Timur.
Semua orang senyap terdiam. Mereka menatap penuh perhatian ke wajah Arkam yang keras.
Sambil melangkah hilir-mudik di depan orang-orang, Arkam terus berbicara dengan penuh semangat hingga wajahnya menegang. Tonjolan urat-urat pada lengannya tampak ketika jari-jarinya menggenggam kuat membentuk kepalan tinju. Saat berbicara, berkali-kali dia menyentuh topi pet merahnya. Dia seperti ingin membukanya, tetapi selalu batal.
“Kita sudah lama hidup ditekan, ditindas, dan dilalimi. Kita tidak bisa terus-terusan begini. Selamanya kita akan menjadi budak. Kita adalah orang-orang bermartabat. Nenek moyang kita pejuang hebat. Kita tidak boleh takut. Kita harus berani melawan semua kelaliman ini. Apakah kalian semua berani melawan pemerintahan keji ini?” teriaknya mengacungkan tinju ke udara.
“Berani,” sambut orang-orang penuh semangat.
Gelegar suara yang membahana itu memekakkan kupingku.
Arkam terus saja berbicara. Dia mengulang inti tujuan perjuangan yang dibangkitkan Hasan Tiro tiga belas tahun lalu di kaki gunung di Pidie. Namun, perlawanan-perlawanan kecil itu berhasil dipatahkan serdadu pemerintah. Banyak pengikut Hasan Tiro yang mati di ujung bedil lawan. Sebagian yang tersisa terendus oleh mata-mata, dan akhirnya diringkus, diculik, dan dibunuh oleh tentara. Sementara Hasan Tiro dan beberapa pengikutnya sudah terlebih dulu menyingkir ke luar negeri untuk mencari suaka politik dan dukungan dunia internasional.
Selama masa itu, pejuang terus menghimpun kekuatan di luar negeri. Sebagian mengikuti pelatihan rahasia di Libya dan menyelundupkan senjata ke Aceh.
Mereka adalah anak-anak muda yang yakin mampu melawan pemerintahan Jakarta di bawah pimpinan Soeharto yang telah menyengsarakan banyak rakyat. Tidak saja rakyat Aceh tetapi rakyat Indonesia lainnya juga hidup dalam penindasan dan ketidakadilan. Bagaimana mungkin di negeri yang hijau dengan hasil alamnya yang melimpah—belum lagi minyak dan gas bumi—rakyatnya hidup dalam kemiskinan? Begitu sebagian isi ceramah Arkam.
“Sekarang tibalah saatnya kita bangkit untuk berjuang mengambil apa yang menjadi milik dan hak kita. Kita bisa hidup makmur dan lebih bermartabat dengan mengurus tanah kita sendiri. Hidup pejuang,” seru Arkam dengan wajah padam menegang.
“Hidup pejuang,” sambut orang-orang mengacungkan tinjunya ke udara. “Hidup Aceh! Allahu akbar!”
Arkam adalah adik Ibu. Usianya sekitar tiga puluhan waktu itu. Selama enam tahun dia menghilang ke Malaysia. Kemudian dia hengkang ke Libya dan tinggal di sana selama setahun untuk mengikuti pelatihan keprajuritan. Kini dia kembali dengan tubuh lebih tinggi dan wajah terkesan keras dengan tulang pipi menonjol. Kumisnya tetap tipis. Sepertinya kini dia punya kegemaran memakai topi pet merah.
Arkam dan tujuh temannya sering berkeliaran ke kampung-kampung untuk mencari dukungan penduduk dan untuk mendapatkan pengikut baru. Di antara mereka berdelapan, hanya tiga orang yang memiliki senjata, termasuk Arkam. Dua orang memegang radio genggam dan yang tiga lainnya bertangan hampa.
Mereka berkeliaran di kampung-kampung dalam wilayah kekuasaannya sebagai Panglima Sagoe, jabatan prajurit pejuang tingkat kecamatan.
Alue Rambe, kampungku ini, adalah kampung terpencil di pegunungan Aceh Utara sebelah selatan kota Lhokseumawe. Kampung kami termasuk dalam kekuasaan Arkam.
Jalan utama kampung berupa jalan tanah berkerikil. Ketika dilalui sepeda motor atau truk angkutan barang, debu-debu pun terbang berhamburan. Namun, di musim hujan bagian-bagian tertentu badan jalan dipenuhi genangan air yang membuatnya becek dan sangat licin.
Aku berada di dalam kerumunan orang-orang di luar kedai Leman, membaur dengan lelaki, perempuan, dan anak-anak. Aku menyandarkan dada pada dinding papan terbuka sehingga aku bisa leluasa memandang ke dalam kedai.
Para lelaki duduk pada setiap bangku. Yang tak mendapatkan bangku bersandar pada tiang; beberapa lainnya berjongkok di lantai tanah. Di satu-satunya meja yang lapang dijajarkan sepucuk senjata laras panjang dan sepucuk pistol. Senjata-senjata itu seperti sengaja dipamerkan untuk membangkitkan semangat orang-orang dalam berjuang melawan pemerintahan Jakarta yang sudah berlaku tidak adil terhadap Aceh.
Arkam memungut sepucuk AK-47 dan mengacungkannya ke orang-orang. Dia memastikan pada orang-orang bahwa benda itu berbahan logam, bukan kayu ataupun plastik. Temannya yang berwajah angkuh mengacungkan AK-47 menegakkan, lalu melipatnya. Seorang lagi, menimang-nimang sepucuk pistol Baretta buatan Italia, menggenggamnya, kemudian memutar-mutarkan pistol itu dengan jari telunjuk yang dimasukkan dalam lingkaran pelatuk. Pistol itu tidak berputar dengan baik dan hampir saja jatuh, yang membuat Arkam membelalakkan mata ke arahnya. Pemuda itu membuang muka, berpura-pura tidak tahu dan tidak peduli pada mulut Arkam yang menyeringai.
Aku tahu semua jenis senjata itu karena Arkam menjelaskannya berulang-ulang seraya mengacung-acungkannya ke hadapan orang-orang yang mengitarinya. Sementara seorang pemuda yang bertubuh agak kekar berdiri tegap di sisi meja berjaga-jaga. Para pemuda, yang masih tetap bertahan dan belum beranjak dari kerumunan, tak lepas-lepas memandangi tiga pucuk senjata itu dengan takjub, seolah-olah itu adalah benda paling ajaib di dunia. Benda semacam itu memang belum pernah ada di kampung ini.
Yasin, seorang pemuda yang sejak tadi diam, memandangi dengan saksama senjata-senjata itu tanpa mempedulikan penjelasan-penjelasan Arkam. Tiba-tiba dia menyentuh AK-47 yang baru saja diletakkan di meja.
Seketika itu juga Arkam menepis tangannya.
Yasin sangat terkejut.
“Ini senjata berbahaya. Kau tidak boleh menyentuhnya,” hardik Arkam. Kejadian itu membuat tiga temannya menegakkan badan dan menajamkan mata.
Salah satu temannya yang lebih tegap mendorong Yasin agak jauh dari meja. Beberapa pemuda berwajah bengal lainnya bergeser ke belakang.
Arkam melanjutkan hardikannya, “Kalau kau sudah bergabung dengan kami dan sudah memadai latihan menembaknya baru kau boleh memegangnya. Kaukira ini senjata mainan?”
Sejumlah orang tertawa. Mereka mengangguk-anggukkan kepala pertanda dukungan pada ketegasan Arkam.
Wajah Yasin merona, agaknya dia malu telah melakukan kecerobohan.
Arkam pun sesumbar tentang kehebatannya menembak dari jarak jauh. Latihan keprajuritan yang diajarkan oleh para pejuang lebih hebat dibandingkan latihan serdadu pemerintah yang hanya dibekali senjata bekas perang dunia kedua dengan peluru yang sering macet dan bidikan yang tidak tepat.
Leman, sang pemilik kedai kopi, diam saja. Senyumnya tampak dibuat-buat. Kegembiraannya juga seperti dipaksakan. Lebih setengah penduduk kampung datang. Sebagian dari mereka menyesaki kedai kopi, sebagiannya lagi berada di jalan. Aku yakin mereka datang bukan untuk minum kopi, tetapi semata ingin melihat lebih dekat senjata-senjata api mematikan yang dibawa Arkam dan temannya. Sebelumnya keberadaan senjata-senjata itu hanyalah merupakan bualan orang-orang yang bermimpi tentang kekayaan Aceh. Di negeri ini, tidak ada orang sipil yang berani menyentuh barang semacam itu, apalagi sampai menyimpannya di rumah. Hukuman bagi pemilik senjata tidak sah adalah hukuman mati, atau setidaknya akan mendekam belasan tahun dalam penjara.
Sebagian orang di kedai kopi, terutama mereka yang masih muda-muda, tampak begitu berapi-api. Mereka menyambut gerakan “pengusiran hama dan penyakit” ini dengan begitu yakin. Mereka akan melawan ketidakadilan pemerintah Jakarta. Aku menangkap kecemasan di wajah beberapa orang tua di sana. Kecemasan akan bahaya yang sedang mengintai kampung-kampung.
Perang memang seakan tidak pernah berakhir di tanah ini. Perang sudah ada semenjak kehadiran Portugis, Belanda, dan Jepang. Dan perang berlanjut dengan pemberontakan partai komunis dan Darul Islam. Dan sekarang, perjuangan Aceh yang melemah mulai bertunas kembali. Tidak akan ada kata akhir untuk peperangan di tanah ini.
Sementara itu, teman-teman Arkam dan para pemuda bersorak. Bersemburan cercaan dan makian terhadap tentara pemerintah seakan musuh-musuh mereka itu sudah berada di depan mata. Kegilaan anak-anak muda itu membuat sebagian lainnya kesal. Diam-diam mereka menyingkir dari sana mengikuti perempuan-perempuan yang sedari tadi kulihat sudah menyingkir duluan.
“Percayalah,” teriakan Arkam membuat orang-orang di dalam kedai senyap.
Tangan kanan Leman yang sedang menyaring kopi menggantung di udara sambil memegang gayung kaleng kopi, sedangkan tangan satunya lagi memegang saringan. Dia, seperti yang lainnya, diam mendengarkan.
“Percayalah,” ulang Arkam yang tampak begitu percaya diri, “Kita akan sanggup mengusir serdadu-serdadu itu dari sini. Senjata-senjata yang kita miliki lebih hebat daripada senjata mereka. Senjata yang mereka miliki cuma M-16 yang usang, bekas dipakai tentara Amerika di perang Vietnam. Sering macet. Hahaha….” Tawa Arkam disambut anak muda lainnya dengan sorak-sorai. Sepertinya mereka tidak ingin beranjak dari sana.
Tangan Leman bergetaran memegang gayung kopi saat ledakan tawa terjadi. Wajahnya pucat. Sepertinya dia ingin selekasnya mengusir tamu-tamu yang bersikap kurang beradab itu. Mereka menggelar pertunjukan senjata di kedainya tanpa izin.
Aku bersama belasan anak lain menunggu di luar kedai dengan menyandarkan perut di dinding dan dengan leluasa memandang ke dalam. Aku menjadi begitu kesal karena Leman tidak kunjung menyalakan televisinya. Setiap petang, tepatnya sehabis Asr, aku dan anak-anak akan menonton sebentar, sebelum Leman menghardik dan mengusir kami pulang untuk mandi dan pergi mengaji. Menonton televisi saat petang adalah kesenangan tiada tara bagi anak-anak. Mungkin juga kesenangan bagi orang dewasa yang bebas menyaksikannya sampai larut malam.
Televisi 14 inci milik Leman adalah satu-satunya televisi yang ada di kampungku. Kedai ini selalu ramai dikunjungi orang-orang selepas Asr, ketika siaran televisi dimulai.
Petang itu, kami betul-betul kecewa dengan pameran senjata Arkam yang menyebabkan kami tidak bisa menonton televisi. Ada dua puluhan pemuda yang terus mengerumuni meja tempat dipamerkannya tiga pucuk senjata api berserta pelurunya itu. Saat itu Arkam seolah seorang pemimpin perjuangan paling hebat dan paling berkuasa di Aceh.
Tiga pemuda yang bertangan hampa itu adalah pengikut baru Arkam yang katanya kelak juga diberi senjata.
Seorang penduduk bertanya kepada pemuda yang tidak bersenjata itu saat Arkam selesai bicara, “Kenapa kau tidak memiliki senjata?”
Dengan rikuh pemuda ramping itu menjawab, “Sedang dikirim dari luar negeri.”
Untuk meyakinkan penduduk, Arkam yang mendengarkan perkataan itu, mengangguk tanpa senyum. Wajah Arkam tampak lelah, tetapi masih menegang. Dia menyesap kopi yang telah dingin, yang sedari tadi tidak sempat diminumnya. Hanya sekali sesap dan dia segera meminta Leman menyingkirkan dan menggantinya dengan kopi baru yang panas.
Leman cepat-cepat menyeduh kopi dan menghidangkannya. Sementara orang-orang masih memandang Arkam. Hanya sebagian kecil saja yang menyingkir meninggalkan kedai Leman.
“Sekarang pulanglah kalian ke rumah masing-masing!” perintah Arkam kepada orang-orang yang ada di dalam dan luar kedai.
***