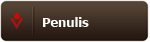Mengenang Padewakkang
Andi Batara Al Isra lahir di Ujung Pandang, 9 Januari 1994. Sedang pusing kuliah antropologi di University of Auckland, Selandia Baru, melalui beasiswa pendidikan Indonesia LPDP. Karyanya berupa cerpen dan puisi telah diterbitkan di berbagai majalah dan surat kabar, juga pernah dimuat dalam beberapa buku antologi bersama. Selain itu, tulisannya pernah menjuarai beberapa lomba penulisan tingkat nasional dan memperoleh penghargaan, seperti cerpennya yang berjudul Keranda Puang mendapatkan penghargaan FLP Awards 2017 sebagai Cerpen Terpuji. Batara juga telah menerbitkan dua buah buku puisi tunggal, yakni Di Seberang Gelombang (2019) dan Gersik dalam Matriks (2020). Cerpen Mengenang Padewakkang yang dimuat pada laman Dalang Publishing ini merupakan karya pertamanya yang diterjemahkan ke dalam bahasa asing. Bergelut di Forum Lingkar Pena, Yayasan Antropos Indonesia, Wijen Projects, dan Perpustakaan Antropologi FISIP Unhas. Batara juga mengelola laman www.bacabata.com, sebuah laman yang terbuka bagi siapa saja untuk mengirimkan dan menerbitkan tulisan. Sila kunjungi akun Facebook Andi Batara Al Isra atau akun Twitter dan Instagram @bataraisra. Bersurat di aali598@aucklanduni.ac.nz.
***
Mengenang Padewakkang
ARNHEM Land, Australia, Desember 1945
Sudah bertahun-tahun Burarrwanga Dayn Gatjing menatap kosong kaki langit. Di tangannya ada pipa tembakau dari kayu yang sejak lama tak pernah lagi mengepul. Dia menunggu kapal-kapal dari Makassar kembali menanam sauh seperti dulu. Setelah angin tenggara yang bertiup antara akhir Maret hingga April, membawa layar padewakkang, kapal dagang milik orang Makassar, ke utara puluhan tahun silam, tak ada lagi yang tersisa selain kenangan. Kepergian mereka seperti kehilangan sebagian dari diri sendiri.
Burarrwanga, lelaki berambut putih dan berkulit gelap itu, adalah pemimpin kelompok suku Yolngu, penduduk pribumi kawasan ini. Meski keriput, meski tubuhnya terlihat rapuh dihantam angin pantai dan gurun, harapannya tidak pernah pupus. Lama sekali, setiap tahun, ketika baarramirri, angin dari arah barat laut, tiba antara Desember dan Januari, sepanjang pantai ini penuh orang dan kapal yang tertambat. Ada yang mengangkat keranjang, ada yang menyelam mencari teripang, dan ada yang mengasapi hasil buruan tersebut. Bayangan tentang masa indah itu tidak pernah hilang dari ingatan Burarrwanga Dayn Gatjing. Dia akan terus menunggu Daeng Gassing bersama para pelaut Makassar lainnya datang dari seberang lautan dengan membawa beras, emas, dan tembakau. Memang sudah sejak ratusan tahun lalu, orang Makassar kerap datang ke Arnhem Land, membangun hubungan baik yang saling menguntungkan dengan penduduk asli di sana, termasuk leluhur Burarrwanga. Hubungan baik tersebut berjalan hingga kini.
“Mungkin mereka ditelan ular petir di tengah lautan,” kata Marika, istri Burarrwanga Dayn Gatjing.
“Jangan bilang sembarangan. Ular petir hanya menyerang orang jahat yang berlayar. Orang baik seperti mereka tidak akan ditenggelamkan.”
“Sudahlah, Burarrwanga, masih ada pohon asam yang dulu mereka tanam. Kau bisa istirahat di bawahnya,” lanjut Marika.
“Sudah lama nama itu tidak kudengar. Terakhir kali kau memanggilku seperti itu saat mereka masih di sini kan?”
“Ya, orang-orang, bahkan para orang kulit putih sekarang lebih mengenalmu dengan Dayn Gatjing ketimbang nama lahirmu.”
Sambil menghela napas, Burarrwanga Dayn Gatjing mengingat kembali apa yang telah dilakukan orang-orang berkulit putih itu pada hidupnya. Kapal-kapal padewakkang milik orang Makassar sudah tiada, diusir oleh Persemakmuran Australia engan alasan-alasan yang tidak masuk akal. Sekarang, yang berseliweran hanyalah kapal-kapal mereka, menguasai lautan dan menguras hasilnya tanpa ampun, terutama teripang. Orang Yolngu tidak mendapatkan apa-apa. Mereka tidak dilibatkan dalam pasar. Persemakmuran Australia mengambil semuanya.
Ingatan Burarrwanga lalu terbang ke masa puluhan tahun silam. Masa ketika pantai-pantai Arnhem Land masih dipenuhi layar padewakkang orang Makassar.
***
Siang yang terik di bulan Januari 1905 seolah matahari berlipat ganda di tanah ini. Meski begitu, beberapa awak kapal serta orang-orang Yolngu bertelanjang dada dan kaki tetap sibuk mengangkat keranjang bambu berisi puluhan teripang yang baru saja ditangkap dari dasar laut. Teripang-teripang tersebut akan dibawa ke sebuah tempat pengasapan di mana Daeng Gassing, seorang pemimpin kapal asal Makassar, duduk mencatat jumlah pikul yang hari ini berhasil dikumpulkan.
Di sebelahnya, Burarrwanga duduk mengawasi anggota kelompoknya yang ikut membantu kegiatan tersebut. Di tangannya terdapat pipa kayu berisi tembakau pemberian bapaknya, yang jauh di masa lalu adalah juga pemberian seorang pelayar asal Makassar. Hampir setiap pria dewasa di kelompoknya memiliki benda ini. Mereka menyebutnya pipa Makassar sebab orang Makassarlah yang membawa benda ini dari seberang lautan.
“Tembakau yang saya simpan sejak setahun lalu kau ke sini sudah habis. Sekarang kau bawa lagi,” ucap Burarrwanga sambil asap keluar dari hidungnya.
“Itu yang leluhur kita selalu lakukan sejak ratusan tahun lalu. Sudah kebiasaan bukan? Setiap tahun, kami, orang-orang Makassar, bawakan kalian barang dan sebagai gantinya, kalian sebagai penduduk asli di sini bantu kami kumpulkan teripang,” kata Daeng Gassing sambil mencatat angka-angka yang kurang dimengerti oleh Burarrwanga. Orang-orang di Arnhem Land tidak begitu mengerti tulisan. Mereka tidak punya aksara. Jika ingin merawat ingatan, mereka menggambar atau mengukir kayu serta batu.
“Kami tidak akan merasa sebaik ini jika di masa lalu, orang-orangmu tidak ke tanah ini mengumpulkan teripang. Kalian bisa ambil itu semua, kami tidak memakannya,” kata Burarrwanga sambil sedikit tertawa.
“Rasanya memang tidak enak. Tidak ada orang Makassar yang makan hewan aneh ini. Kami jual ke Tiongkok. Harganya mahal. Pantaimu menghasilkan banyak sekali teripang dengan mutu bagus,” sambung Daeng Gassing.
“Kau tahu, aku berharap suatu hari aku bisa mengunjungi kampung halamanmu. Pasti tempat itu sangat makmur dan maju. Banyak kapal dan rumah besar, kan?” tanya Burarrwanga.
“Kalau tanah itu sangat makmur, kami tidak mungkin ke sini mencari teripang. Di sana banyak masalah, terutama setelah orang Belanda menguasai Makassar. Namun di sisi lain, kami senang bisa ke sini, leluhur kami pun pasti senang,” jawab Daeng Gassing.
Apa yang lelaki Makassar itu mungkin tidak sadari adalah bahwa selama ratusan tahun, leluhurnya telah membawa perubahan besar bagi kehidupan di Arnhem Land. Mereka memberikan beras, logam, tembakau, minuman keras dan barang-barang lain yang tidak pernah dilihat orang Arnhem Land sebelumnya. Tanah ini sudah seperti bagian dari mereka. Bahkan di masa lalu, desas-desus pernah menyebar bahwa Arnhem Land adalah bagian kekuasaan Kerajaan Gowa. Itu pula alasan mengapa orang Makassar memiliki nama khusus bagi tanah ini. Mereka menyebutnya Maregeq.
Di tengah percakapan itu, Marika yang sedang hamil besar tiba-tiba mendatangi mereka berdua. Dia berlari-lari kecil dengan napas tersengal-sengal.
“Orang Persemakmuran… ada orang Persemakmuran Australia … saya lihat mereka … bawa pistol … senapan … ke sini.”
Mendengar itu, Daeng Gassing dan Burarrwanga langsung meminta orang-orangnya menyiapkan senjata. Orang Makassar menyelipkan badik dan parang di balik sarung, sementara orang Yolngu menyiapkan tombak dan panah. Mereka tidak ingin kekerasan. Hanya saja, karena orang-orang Persemakmuran Australia membawa senjata, segala kemungkinan harus dipersiapkan.
“Anda terlalu jauh dari kampung halaman dan sudah terlalu banyak mengambil teripang di tanah orang. Anggap saja ini peringatan.” Kata seorang polisi Persemakmuran Australia begitu dia berhadapan dengan Daeng Gassing.
“Kapal-kapal saya terdaftar di syahbandar Port Bowen. Apa yang perlu diperingatkan?”
“Lihat,” polisi itu mengeluarkan selembar kertas, “saya ditugaskan mengawasi kalian karena meracuni orang-orang asli sini. Kalian mengajarkan mereka mabuk!”
“Hei, apa urusanmu menganggu kesenangan kami?” Burarrwanga angkat suara. Dia tidak senang melihat orang Persemakmuran Australia mencampuri kehidupan orang-orangnya.
“Itu yang sering dikatakan para penjahat. Dengar, tanpa sadar, kalian dirusak oleh orang-orang ini yang entah datang dari mana,” polisi itu menatap Burarrwanga sambil tangannya menunjuk Daeng Gassing.
“Bukan kau yang memerintah di sini!” Dengan geram, Burarrwanga sekonyong-konyongnya berusaha meninju polisi yang berada di depannya. Sedikit meleset, tetapi polisi itu kehilangan keseimbangan dan jatuh ke belakang.
Begitu tersungkur, polisi itu tiba-tiba melepaskan tembakan peringatan ke angkasa. Orang-orang di sekitarnya menutup telinga. Kini, orang-orang Makassar dan Yolngu menghunus senjata tajam, siap menyerbu pasukan polisi berkulit putih. Namun, Daeng Gassing memberikan isyarat agar menahan serangan.
“Karena ini hanyalah peringatan, kami akan pergi. Kami sebenarnya tidak ingin ada pertumpahan darah. Tapi, sebelum itu, pukulan harus dibalas dengan pukulan…” Debuk! Bogem mentah mendarat di wajah Burarrwanga.
Polisi Australia berambut pirang itu pergi membawa pasukannya begitu saja setelah menghantam tulang pipi Burarrwanga.
Orang-orang kini mengeremuni Burarrwanga. Beberapa yang lain hendak melawan balik dan mengejar polisi Persemakmuran Australia, tetapi Burarrwanga yang setengah sadar memberikan isyarat agar menyudahi persoalan ini. Pukulan polisi itu terlampau keras. Kepala Burarrwanga berkunang-kunang, seperti ada banyak kanguru yang melompat-lompat di sekelilingnya. Pandangannya semakin kabur, dia tidak lagi melihat wajah Daeng Gassing dengan jelas. Semuanya berubah hitam. Dia pingsan.
***
Dua tahun setelah peristiwa peringatan pada 1905, tiba waktu dimana orang Makassar harus benar-benar hengkang dari Arnhem Land sebab Persemakmuran Australia yang telah mengeluarkan larangan pelayaran bagi orang Makassar untuk memasuki wilayah Australia. Berita itu merupakan kabar buruk. Lebih buruk dari badai yang sering menghantam padewakkang saat melintasi lautan. Bagaimana tidak, mencari teripang sampai ke tanah jauh adalah kebiasaan yang sudah dilakukan turun-temurun sejak pertengahan 1600. Leluhur Daeng Gassing yang berlayar lebih dulu ke Arnhem Land ketimbang orang berkulit putih yang datang belakangan bersama ribuan tahanan dan senapan.
Mata Burarrwanga belum lepas dari lidah api unggun yang menjilat sunyi. Menit-menit berlalu, belasan orang yang duduk mengelilingi penerang itu tak mengeluarkan suara sama sekali. Yang terdengar hanya debur ombak menyapu pasir, decit papan kapal yang digoyang arus, dan ranting patah yang dilahap api. Mereka bingung, marah, sekaligus sedih, sebab esok hari, setelah padewakkang pergi, mereka mungkin tidak akan pernah bertemu lagi.
Burarrwanga mengais-ngais api dengan ranting. Dilihatnya sisa bakaran yang telah jadi abu, persis harapan orang-orangnya. Dia menghela napas lalu mengembuskannya kuat-kuat. Dia terlampau pusing. Banyak hal jumpalitan di kepalanya seperti kanguru yang biasa dia buru di padang sabana. Dia memikirkan nasib orang-orang dan keturunannya kelak jika dia bersama istri dan anaknya memutuskan ikut ke Makassar bersama para pelayar yang telah dia kenal bahkan sejak dia mulai bisa mengingat.
Persis di hadapannya, di sebelah kobar api yang menari-nari, dia melihat wajah murung Daeng Gassing. Burarrwanga heran, harusnya lelaki berkumis tebal dan berambut panjang itu tidak perlu terlalu sedih sebab Daeng Gassing akan kembali ke Makassar beserta belasan awak kapal yang rindu melihat nyiur pelepah.
“Kau yakin mau tinggalkan Arnhem Land?” Daeng Gassing memecah sunyi.
“Saya harus. Orang Persemakmuran Australia telah mengambil semuanya, tidak ada lagi yang bisa saya pertahankan. Kami tidak bisa hidup tanpa kalian,” jawab Burarrwanga sambil tangannya melempar ranting ke dalam api.
“Tapi orang-orangmu? Kau mau biarkan mereka?”
“Para tetua akan memilih pemimpin suku yang baru setelah saya pergi. Ini kesempatan terakhir saya seberangi gelombang dan melihat ada apa di balik kaki langit. Aku ingin kehidupan yang lebih baik bagi istri dan anakku.
Mereka bersitatap. Bara seolah berpindah dari arang ke mata dua orang yang sudah seperti saudara itu. Daeng Gassing tidak ingin Burarrwanga meninggalkan orang-orangnya begitu saja. Namun dia bisa apa. Dia tidak berhak menghalangi mimpi seseorang.
“Kemarin saya bertemu seorang ibu, dia menangis sambil terduduk dan memukul-mukul pasir begitu tahu kita akan pergi,” kata Marika.
Daeng Gassing masih tertunduk. Tangannya memegang sejenis gelas dari bambu berisi ballo, minuman keras khas Makassar yang terbuat dari nira enau atau kelapa, yang jauh-jauh dia bawa dari Makassar. Tak lama berselang, dia bangkit lalu menyerahkan gelas itu pada Burarrwanga. “Ini malam terakhir kita bersenang-senang. Di sana masih banyak, habiskan saja,” tawar Daeng Gassing yang disambut oleh Burarrwanga dengan senang hati.
“Saya, sebenarnya, tidak mau pergi. Bagaimana pun, di sini saya lahir. Di sini pula saya harus mati,” Marika kembali bersuara dengan sirih pinang di mulutnya. Pernyataannya membuat orang-orang di sekeliling api unggun itu kaget.
“Hanya kau dan anak kita yang tidak bisa saya tinggalkan. Saya rela melepaskan apa pun, tapi kalian? Saya tidak bisa.” Burarrwanga sambil menggelengkan kepala.
Malam masih pekat. Orang-orang mulai beradu mulut. Setelah Marika mengeluarkan pendapat, anggota kelompok lain mulai ikut bicara. Sebagian besar mereka tidak sepakat jika Burarrwanga pergi. Kepergian orang Makassar sudah cukup menyakitkan. Jika pemimpin kelompok yang beberapa tahun lalu berjasa atas keberaniannya terhadap pasukan Persemakmuran Australia juga pergi, mereka betul-betul kehilangan harapan.
Adu mulut tersebut berakhir dengan ketidak sepakatan antara Burarrwanga dengan orang-orangnya, termasuk Marika. Burarrwanga masih keras kepala. Dia masih ngotot akan membawa Marika ke Makassar meski Marika sendiri tidak ingin ikut dan anggota kelompok lain sudah mencegahnya. Burarrwanga lalu sekonyong-konyongnya meninggalkan api unggun dan menuju gubuknya untuk tidur. Dia sudah sangat mengantuk.
***
Dalam mimpinya, Burarrwanga bangkit dan menoleh ke sana kemari. Jantungnya berdebar. Dia mencari Daeng Gassing dan orang-orang Makassar yang lain. Burarrwanga tak melihat satu pun dari mereka. Dia gugup. Harusnya hari ini, dia, Marika, dan anak semata wayangnya ikut ke Makassar.
Hari mulai sedikit terang. Dari kejauhan, matahari mulai menyingsing sedikit demi sedikit meski bintang kejora seperti enggan pergi. Jangan-jangan, padewakkang telah berlayar meninggalkannya? Pikir Burarrwanga. Dia curiga sebab semalam, dalam ingatannya, Daeng Gassing dan beberapa orang Yolngu tidak sepakat jika dia harus ikut ke Makassar. Burarrwanga lantas mencari orang-orangnya. Dia kesal. Dia merasa dikhianati.
Burarrwanga mulai heran. Dia belum mendapat satu pun anggota kelompoknya bahkan di gubuk-gubuk yang mereka dirikan. Ke mana mereka? Diculik orang Persemakmuran Australia? Batin Burarrwanga.
“Tidak, mereka tidak diculik,” teriak seseorang dari kejauhan.
Mendengar suara itu, Burarrwanga membalikkan badan. Namun tak ada siapa-siapa. Seseorang jelas-jelas bersuara dan mendengar suara batinnya. Dia menoleh ke sekitar, hanya seekor kanguru yang menatapnya dari atas bukit karang.
“Kau tersesat?”
Burarrwanga kembali menoleh ke depan dan didapatnya seekor kanguru tepat di hadapan wajahnya. Dia berteriak lalu tersungkur. Burarrwanga menoleh ke arah bukit tempat kanguru itu awalnya terlihat, tetapi ia sudah tak ada. Entah bagaimana kanguru itu berpindah secepat kilat ke hadapannya. Yang lebih aneh lagi, kanguru itu bisa bicara. Burarrwanga mulai bertanya-tanya, apakah semua ini nyata atau hanya sekadar mimpi belaka sebab tidak mungkin ada kanguru yang bisa bicara.
“Burarrwanga Dayn Gatjing, kau mau tinggalkan orang-orangmu begitu saja?”
“Dari mana kau tahu nama saya? Dayn Gatjing? Nama saya hanya Burarrwanga!”
“Oh, kau akan tahu nanti. Tidak lama lagi.”
Kanguru itu lantas mengubah wujudnya dengan cara yang sukar dipercaya. Ia menjadi seorang wanita berkulit kuning. Mirip seperti kulit orang-orang Makassar yang lebih terang dari kulit orang-orang Yolngu. Wanita itu melayang. Lalu dengan sekali lambaian, bukit-bukit rata dengan tanah. Sungai mengalir ke angkasa lalu jatuh sebagai hujan yang lembut. Matahari yang sudah setengah naik tiba-tiba tenggelam lagi. Malam datang dan bintang-bintang muncul kembali. Di langit, mereka berputar mengelilingi Burarrwanga. Benda-benda indah lainnya muncul seperti lukisan. Warna malam tidak hanya hitam, paduan kabut merah, hijau, biru, kuning, dan warna-warna lain yang belum pernah Burarrwanga lihat sebelumnya seolah ditumpahkan begitu saja. Burarrwanga takjub melihat pemandangan itu.
“Kau… kau Baiyini, leluhur pertama orang Yolngu?”
“Aku adalah apa yang kau pikirkan, Dayn Gatjing. Aku melukis semua ini, lalu mengirimnya ke alam tempat kalian hidup.”
“Kau … Mimi, roh pelukis? Bukan, kau… Barnumbirr, roh penciptaan!” Burarrwanga hendak sujud tetapi sosok gaib itu menyuruhnya untuk bangun.
“Tegarlah, dan kembalilah ke orang-orangmu. Kau hanya tersesat. Kau takut tanah ini mengecewakanmu lebih jauh. Tapi apa kau lupa? Orang-orang sebelummu bertahan sejak ribuan tahun, bahkan sebelum padewakkang orang Makassar datang dan sebelum para orang kulit putih menembakkan senapan kali pertama. Kalian akan baik-baik saja puluhan hingga ratusan tahun ke depan. Tinggallah di tanah ini, kenanglah yang pergi.”
Burarrwanga terbangun menangis masih mendengar petuah sosok itu. Kini dia mengerti. Dia tadi berada di wongar, alam mimpi. Alam tempat roh leluhur hidup dan menciptakan dunia. Tidak sembarang orang bisa ke sana. Menurut cerita para tetua, hanya mereka yang terpilih oleh roh leluhur saja yang bisa mendapat petunjuk melalui mimpi dan membuka gerbang ke wongar untuk melihat wujud asli para pencipta. Dia mendapat penglihatan dan telah diberkati.
***
Abu dan sisa-sisa unggun semalam masih teronggok di pesisir. Air telah pasang. Orang-orang sibuk mengangkat barang dan keranjang terakhir berisi teripang kering ke atas padewakkang. Angin tenggara sudah bertiup kencang. Para awak kapal mulai menyiapkan layar. Sauh akan dilepas, tetapi Daeng Gassing masih berdiri di tepian.
“Tiba-tiba sekali kau putuskan tidak pergi. Kau dapat mimpi?”
“Ya, aku berada di wongar dan bertemu kanguru. Sulit kujelaskan, tapi leluhur menyuruhku tetap di sini.”
Hal itu memang sangat sulit dimengerti oleh Daeng Gassing. Seseorang yang semalam sangat bersikeras untuk pergi dari tanah ini dan ikut berlayar, kini berubah pikiran hanya dengan alasan diberi petunjuk oleh seekor kanguru dalam mimpi.
Namun itu kepercayaan Burarrwanga. Entah dia bertemu leluhur atau apa di alam sana, Daeng Gassing tidak mau memikirkannya lebih jauh. Dia lega Burarrwanga batal meninggalkan kampung dan orang-orangnya. Yang Daeng Gassing yakini, Burarrwanga harus terus berjuang merebut kembali hak-hak atas tanah leluhurnya dari orang-orang Persemakmuran Australia.
“Oh iya, bisakah saya mengambil namamu? Akan saya taruh di belakang nama saya. Burarrwanga Daeng Gassing, atau dengan penyebutan orang Yolngu, Dayn Gatjing. Ya, Burarrwanga Dayn Gatjing!”
“Tanda persaudaraan?”
“Saya akan mewariskan nama-nama Makassar dan menceritakan kisah kalian kepada anak saya, kepada cucu saya, kepada cucu dari cucu saya. Panggil saya Burarrwanga Dayn Gatjing!”
“Tentu. Kita mungkin akan bertemu kembali suatu hari ketika musim baarra tiba dan angin … mamirri bertiup,” Daeng Gassing kurang yakin dengan istilah Yolngu yang dia pakai.
“Hahaha, baarramirri, musim ketika angin bertiup dari arah barat laut.” Burarrwanga melambaikan tangan terakhir kali, diikuti oleh orang-orang Yolngu. Mata mereka terpaku pada layar padewakkang hingga tidak terlihat lagi di kaki langit.
*****