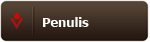Para Penjual Rumah Ustazah Nung
Ben Sohib menulis cerita pendek, esai, novel, dan skenario film. Dwilogi novelnya, The Da Peci Code (Rahat Books, 2006) dan Rosid & Delia (Bentang, 2008) diangkat ke layar lebar dengan judul 3 Hati 2 Dunia 1 Cinta dan menjadi film terbaik pada Festival Film Indonesia (FFI) 2010. Ben juga diunggulkan sebagai penulis skenario terbaik pada FFI 2017 untuk film Bid’ah Cinta.
Kumpulan cerita pendeknya Haji Syiah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh George Fowler berjudul Haji Syiah & Other Stories. Cerpen ini juga diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman berjudul, Hadschi Schia oleh Jorn Holger Sprode. Kedua terjemahan itu bersama dengan karya aslinya diterbitkan dalam satu buku (Lontar 2015)
Ben bisa dihubungi di bensohib2@yahoo.co.id
Terbit bulan Agustus 2019. Hak cipta ©2019 ada pada Ben Sohib. Terbit atas izin dari penulis. Hak cipta terjemahan ©2019 ada pada Oni Suryaman.
Para Penjual Rumah Ustazah Nung
Kau harus melihat sendiri bagaimana si bungsu itu memainkan drama di hadapan ibunya. Dia tahu ibunya selalu merasa iba kepadanya dan lekas terharu pada apa pun yang dikeluhkannya. Lelaki itu memang bebal dalam banyak hal, tapi tidak untuk urusan yang satu ini. Ketiga kakaknya, dua perempuan dan satu laki-laki, dibuat tak berkutik dan hanya bisa pasrah saat sang ibu akhirnya menuruti keinginannya: menjual rumah pusaka.
“Dulah tsudah tak tahan hidup tsendiri. Dulah ingin menikah lagi tsecepatnya,” itu yang dia katakan sambil tangannya mengusap sepasang pipi tembam yang basah oleh air mata.
Lihat, dia selalu berbicara dengan memanggil namanya sendiri, menegaskan bahwa dia memang anak bontot yang manja. Memang benar dia anak bungsu dari empat bersaudara. Tapi usianya 38 tahun, berperut buncit, berkepala botak, dan tak fasih melafalkan “s” karena dua gigi depannya sudah rompal (soal kenapa dua gigi depannya rompal akan kuceritakan nanti).
Aku tak tahu apa yang ada di pikiranmu jika kau berada di sana menyaksikan rapat keluarga sore itu, melihat seorang lelaki dewasa berbicara dengan memanggil namanya sendiri, sesuatu yang hanya pantas dilakukan anak balita atau paling tidak gadis remaja. Mungkin kau ingin menamparnya. Ketiga kakaknya ingin sekali membunuhnya.
“Kau tak memikirkan Umi?” tanya salah seorang kakak perempuanya.
“Umi bitsa membeli rumah kecil di kampung dekat-dekat tsini. Buat apa rumah tsebesar ini jika penghuninya cuma Umi dan Dulah? Lagipula, kalau nanti menikah Dulah kan juga ingin punya rumah tsendiri, punya mobil, punya utsaha, tseperti kalian semua!”
Namanya memang Abdulah, dan dia memang dipanggil Dulah, tapi percayalah, kau akan merasa jengah melihat seorang lelaki dewasa, dengan potongan seperti yang sudah kugambarkan tadi, berbicara dengan gaya memangggil namanya sendiri. Dan kejengahanmu akan menjadi-jadi setiap kali ada kata yang mengandung huruf “s” di tengah-tengah pembicaraannya.
“Tapi Umi belum tentu betah di rumah baru,” sergah kakak perempuan yang lainnya.
“Betul, selain banyak kenangan dengan almarhum Abah, Umi kan ada majelis taklim di rumah ini. Itu hiburan tersendiri buat masa tua Umi,” kali ini kakak laki-lakinya yang angkat bicara.
Si bungsu berdiri. “Hiburan? Hiburan buat kalian karena kalian tsudah punya tsegalanya! Kalian egoits! Kalian….” Dia tak mampu melanjutkan kalimatnya. Dia kembali duduk dan menutup wajah dengan kedua telapak tangannya. Sekarang dia tersedu. Kakak-kakaknya yang duduk di depannya terdiam, sementara sang ibu yang duduk di sampingnya tampak seperti orang linglung. Mungkin dia bingung menghadapi suasana seperti ini, apalagi pikirannya masih terganggu dengan kata-kata Abdulah seminggu yang lalu. Saat menyampaikan niatnya hendak menikah lagi setelah delapan tahun menduda, anak bungsunya itu mengawali dengan keluh-kesah bahwa dia tak pernah merasa bahagia sepanjang hidupnya, dan bahwa sekarang dia ingin menikmati hidup selagi usianya belum terlanjur tua. Pikiran Ustazah Nung—demikian perempuan itu dipanggil oleh warga kampung—makin ruwet ketika dia tahu dengan siapa sang anak hendak menikah (soal dengan siapa Abdulah hendak menikah juga akan kuceritakan nanti).
Setelah tangisnya mereda, si bungsu melanjutkan bicaranya, “Kalian tak pernah memikirkan hidup Dulah yang hancur, yang ketsepian, yang tak punya rumah tangga, yang tak punya apa-apa!”
“Kami semua memikirkan hidupmu, dan kau bebas mengawini setan mana pun yang kau suka, tapi jelas kami tak setuju dengan usulmu menjual rumah ini, kita juga harus memikirkan kehidupan Umi!“ kata kakak perempuannya yang pertama.
“Umi akan baik-baik tsaja, kalian berlebihan! Ini mumpung tsekarang harga tsedang tinggi, mau menunggu apa lagi? Kalian tega melihat Dulah hidup merana tseperti ini bertahun-tahun? Kalau begini tserus, Dulah bitsa-bitsa duduk dan jalan-jalan telanjang di depan rumah!”
“Akan kujual rumah ini, dan kubagikan uangnya sesuai hak waris masing-masing!” akhirnya Ustazah Nung ambil keputusan. Perempuan tua itu berbicara tegas dan lantang, dengan suara bergetar.
***
Kini tiba saatnya aku bercerita tentang bagaimana dua gigi depan Abdulah rompal, dan beberapa hal lainnya. Giginya masih utuh seandainya dia tak berbuat bodoh. Bahkan rumah tangganya mustinya juga masih utuh. Tapi dia terlalu bodoh untuk mempertahankan keutuhan gigi depan maupun rumah-tangganya.
Itu bermula dari petualangannya dengan seorang perempuan bernama Lola. Saat itu Abdulah sudah beristri. Tapi, dua tahun usia pernikahan tampaknya masih terlalu singkat untuk bisa memadamkan api cinta pertamanya kepada Lola. Dia memang sudah tergila-gila kepada perempuan itu sejak dia masih murid SLTA. Mereka belajar di sekolah yang sama. Abdulah murid kelas 3, Lola duduk di bangku kelas 1. Tapi mereka lulus dalam waktu yang bersamaan lantaran dua kali Abdulah tak naik kelas (Abdulah juga pernah tak naik kelas sebelumnya, dua kali saat di SD, sekali di SLTP).
Selama tiga tahun menjadi teman satu sekolahan, Abdulah tak berhasil menjadikan Lola sebagai pacarnya, tapi dia cukup senang telah berhasil membuat Lola bersedia menerima apa saja yang dia berikan, baik berupa barang maupun uang. Tak sekali pun pemberiannya pernah ditolak Lola. Rasa bahagia Abdulah berlipat-ganda saat Lola mulai berani meminta uang jajan seminggu sekali, yang langsung dia terjemahkan sebagai kesediaan gadis itu untuk menjadi istrinya.
“Lola memang cantik, tapi sepertinya dia bukan gadis baik-baik, aku sering melihat dia merokok di warung Bu Mameh,” kata Ustazah Nung saat Abdulah memintanya untuk meminang Lola, enam bulan setelah mereka berdua lulus SLTA.
“Lola cinta pertama Dulah, tak ada yang bisa menggantikannya,” jawab Abdulah.
Dengan berat hati Ustazah Nung akhirnya melangkah ke rumah Lola menemui ibunya, menyampaikan niat Abdullah. Dan dia pulang dengan membawa kabar buruk untuk anak laki-laki terkasihnya. : Lola “sudah ada yang punya,” seorang pengusaha biro perjalanan. Mereka akan menikah tahun depan.
Sejak saat itu Abdullah menjadi pemurung dan sering melamun. Keadaan yang membuat Ustazah Nung risau ini berlangsung selama hampir dua tahun, sampai salah seorang kakak perempuannya datang bersama seorang perempuan bernama Hilda.
“Ini adik temanku. Dia dari Tasikmalaya, ke Jakarta mau mencari pekerjaan,” katanya saat memperkenalkan kepada Abdulah.
Mereka menikah enam bulan kemudian. Ustazah Nung menjual sebidang tanah di Kebon Baru untuk biaya perkawinan, dan sebagian sisanya diberikan kepada Abdulah untuk modal usaha membuka warung sate kambing di Jalan Otista.
Di luar dugaan banyak orang yang mengenalnya, Abdulah berhasil mengelola warung itu dengan baik. Kian hari Warung Sate Kambing “Bang Dulah” kian banyak mendapatkan pelanggan. Dalam waktu dua tahun, Abdulah sudah berani mengambil kredit mobil. Saat itulah Lola kembali muncul dalam kehidupannya. Lola yang tak kunjung menikah, baik dengan pengusaha biro perjalanan atau biro apa pun juga, datang ke warung itu.
“Satemu enak,” katanya saat akan membayar di meja kasir.
“Kau tak perlu membayar,” jawab Abdulah dengan gemetar.
Lola mengulurkan dua lembar kertas, selembar uang kertas pecahan lima puluh ribu dan selembar lainnya kertas putih bertuliskan nomer telepon genggamnya. Abdulah menerimanya dengan tangan bergetar seperti orang sakit buyutan. Dan Lola sengaja menyentuhkan jemari tangannya ke telapak tangan Abdulah yang berkeringat dingin. Abdullah buru-buru memasukkan kedua lembar kertas itu ke laci, dan lupa memberikan uang kembalian.
Tak sampai dua minggu setelah kunjungan itu, kabar bahwa Abdulah sering pergi berdua dengan Lola sudah santer terdengar di seantero kampung. Menurut sas-sus yang beredar di antara warga, Abdulah memberi Lola uang bulanan. Sepeda motor bebek baru yang dikendarai Lola konon juga merupakan pemberian Abdulah. Kabar-kabar burung itu akhirnya hinggap di telinga Hilda. Saat Abdulah ke dapur hendak mengambil segelas air pada satu sore di hari Minggu, Hilda yang sedang mencuci wajan bertanya, “Benarkah semua yang aku dengar dari orang tentang hubunganmu dengan Lola?”
Entah apa yang saat itu ada di benak Abdulah. Awalnya dia diam saja, matanya sebentar memandang Hilda, sebentar memandang ke jendela. Lalu mendadak dia lancar berbicara setelah si istri berkata, “Ceritakan saja yang sebenarnya, aku lebih senang mendengar dari mulutmu sendiri.”
Abdulah membenarkan semua yang diceritakan orang dan didengar istrinya. Dia menutup pengakuannya dengan “Mungkin Dulah masih mencintai Lola” yang dia ucapkan sambil tersenyum.
Hantaman punggung wajan di mulutnya itu begitu keras, dua gigi depannya langsung rompal. Mendengar suara ribut-ribut, Ustazah Nung yang sedang rebahan di kamar bergegas menghampiri sumber suara. Dia menjerit melihat mulut Abdulah penuh darah. Malam itu juga Hilda pulang ke Tasikmalaya dan tak pernah kembali ke Jakarta. Sementara Lola memilih hengkang dari kampungnya. Dia tinggal bersama salah seorang sepupunya di daerah Kota. Konon di sana dia bekerja di sebuah restoran yang juga menyediakan karaoke. Sebulan sekali dia pulang ke rumahnya.
***
Abdulah kembali menjadi pemurung dan sering melamun. Entah karena sebab yang mana. Warung satenya dibiarkan tak terurus dan tutup tiga bulan kemudian, mobilnya dibawa pergi oleh dua orang debt collector yang datang ke rumahnya tak lama setelah itu. Pada tahun pertama setelah kejadian itu, juga pada tahun-tahun selanjutnya, Abdulah lebih banyak menghabiskan waktunya dengan duduk sambil merokok, berpindah- pindah dari satu kursi di ruang tamu, ke kursi lainnya di teras belakang atau teras depan. Setiap kali ibunya menganjurkan menikah lagi, selalu dia tanggapi dengan gelengan kepala.
Hingga pada satu malam di tahun yang kedelapan, setelah beberapa minggu sebelumnya sering terlihat berdiri di depan cermin memegang sisir, berusaha sedemikian rupa menyisir ke kanan sejumput rambut panjang yang tumbuh di sisi kiri kepalanya agar bagian atas kepalanya yang botak licin itu tampak seolah-olah masih ditumbuhi rambut tipis, Abdulah tiba-tiba menghampiri ibunya dan mengatakan hendak menikah dengan Lola.
Abdulah bercerita bahwa Lola sudah beberapa kali menemuinya dalam sebulan terakhir ini. Dia berkata bahwa Lola yang sekarang berstatus janda itu mencinta dirinya, bahwa Lola ingin dia menjadi ayah baru yang bertanggungjawab bagi anak satu-satunya. Mata Abdullah berkaca-kaca saat menceritakan bagaimana anak lelaki berusia tiga tahun itu, dalam waktu demikian singkat sudah terbiasa memanggilnya “Papa.”
***
“Tak ada cacatnya” adalah istilah yang digunakan para calo tanah dan rumah yang banyak berkeliaran di daerah ini ketika mereka mengomentari rumah Ustazah Nung. Ukurannya pas, surat-suratnya “bersih”. Rumah tua itu berada tepat di pinggir Jalan Raya Kampung Melayu Besar. Lebar depannya 30 meter, sementara panjangnya mencapai 50 meter, sangat bagus untuk gedung berlantai empat. Di kanan dan kiri rumah Ustazah Nung itu memang sudah banyak berdiri gedung berlantai empat.
Bukan sekali dua kali para pengembang menanyakan rumah Ustazah Nung kepada Bang Sanip, makelar bangkotan yang menguasi seluk beluk pertanahan di daerah ini. Bang Sanip hapal hampir seluruh riwayat rumah dan tanah di wilayah yang—sejak dibangunnya jalan layang ke pusat kota—menjadi incaran para pengembang itu.
Sejak jalan layang mulai dibangun sekitar tiga tahun lalu, harga rumah dan tanah yang terletak di pinggir jalan raya itu melambung. Kebanyakan warga memilih menjual rumahnya dan pindah ke daerah pinggiran yang harga tanahnya jauh lebih murah. Hanya tersisa beberapa gelintir warga yang memilih mempertahankan rumah dan tanah warisan leluhurnya, dan Ustazah Nung termasuk salah seorang dari mereka.
“Ini kesempatan emas, harganya bagus. Ustazah bisa membeli rumah baru, naik haji lagi atau umroh. Sisa uang Ustazah bisa disimpan di bank syariah, tujuh turunan tidak bakal habis,” bujuk Bang Sanip pada suatu sore. Sudah tiga kali dia bersama dua temannya datang menemui Ustazah Nung dalam setahun ini.
“Aku masih betah di sini,” jawab Ustazah Nung.
Bang Sanip dan kedua rekannya meninggalkan Ustazah Nung setelah menenggak habis air putih yang disuguhkan, tapi tenggorokannya masih terasa kering. Air liurnya nyaris habis setelah hampir satu jam dia merayu Ustazah Nung dengan berbagai jurus agar mau melepas rumahnya. Tapi perempuan berkerudung itu seperti tidak mengenal kalimat lain kecuali, “Aku masih betah di sini”.
Entah sudah berapa kali Ustazah Nung mengucapkan kata-kata ini. Dan setiap kali kalimat itu terucap, Bang Sanip dan kedua temannya merasa seperti dicekik.
Jawaban singkat yang diberikan Ustazah Nung setiap kali Bang Sanip menyelesaikan kalimatnya yang panjang lebar, benar-benar membuat pemimpin makelar itu putus asa. Kedua temannya yang bertugas membenarkan semua yang diucapkan Bang Sanip ikut putus asa. Mereka merasa kalimat-kalimat pendek seperti “itu benar,” “tepat sekali,” dan “betul sekali,” yang mereka sisipkan di tengah-tengah pembicaraan Bang Sanip, terbukti tak berpengaruh apa-apa.
Begitu sampai di luar pagar rumah Ustazah Nung, sebelum melanjutkan langkahnya, Bang Sanip menoleh dan menatap rumah tua itu beberapa waktu. Aih, rumah yang sangat cantik seandainya si pemilik tak suka mengulang-ngulang kalimat, “Aku masih betah di sini.”
Saat itulah Bang Sanip melihat Abdulah muncul dari dalam rumah, berjalan sambil membetulkan gulungan sarungnya menuju sofa tua yang diletakkan di pojok teras. Abdulah duduk mengangkat kedua kakinya sebelum menyalakan rokok. Wajahnya kusut seperti orang yang tak tidur berhari-hari.
Tiba-tiba Bang Sanip mengusap mulut, menyembunyikan senyumnya. Lalu dia berjalan dengan cepat, bergegas menyusul kedua temannya. Benaknya dipenuhi wajah Lola. Ingatannya dengan cepat menyusun kembali riwayat percintaan dan perselingkuhan yang melibatkan Abdulah dan Lola. Bang Sanip tahu di mana Lola bisa ditemui, dan dia juga tahu apa yang sedang dibutuhkan perempuan itu saat ini.
Malamnya, para makelar itu menggelar rapat hingga menjelang dinihari.
***