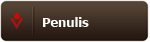Horas, Ibu!
Reni Renatawati adalah seorang mahasiswi sastra Inggris dari Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Lahir pada 6 Januari 2001 di Pasar Rebo, Jakarta, Reni adalah keturunan dari dua suku yang berbeda; Batak dan Jawa. Sebagai seseorang yang senang mendengarkan lagu, menggambar, dan membaca buku karya penulis Indonesia maupun luar negeri, Reni memiliki impian untuk menjadi seorang penulis profesional yang membahas dan menguak tentang kebudayaan, dan permasalahan sosial yang terjadi di Indonesia melalui karya sastra rekaan yang berdasarkan atas penelitian. Tujuan utama dari impian yang diutarakan adalah agar membuka mata rakyat Indonesia mengenai kebudayaan, termasuk juga dengan permasalahan yang ada di kemasyarakatan Indonesia.
Reni dapat dihubungi di renirenataharianja16@gmail.com
Horas, Ibu!
Hembusan semilir angin senja memainkan rambut Jakob yang mulai memutih. Kedua netranya menatap nanar tanah merah tempat ibunya dikubur. Sudah lewat duabelas tahun, sejak kematian ibunya, dan limabelas tahun tanpa kehadiran kedua saudaranya yang lenyap di tanah orang karena beralasan mau mengadu untung dan nasib. Kedua saudaranya yang pergi ke tanah Jawa dan menghilang dari Siborong-borong, kampungnya di Sumatera Utara, kini berdiri di samping Jakob, menatap kubur ibu mereka dengan khidmat sembari membiarkan para tukang gali kubur membongkar kubur dan peti mati ibunya.
Di tanah batak, adalah hal wajar untuk keluarga melakukan upacara kematian bagi para leluhur, termasuk kepada orang tua yang telah lama meninggal dengan memindahkan tulang belulang mereka ke tempat yang lebih baik dari sebelumnya. Maksud dari adat ini adalah untuk menghormati mereka. Saat itu pula, seluruh sanak saudara haruslah kembali dari perantauan ke kampung halaman untuk mempersiapkan upacara, seperti yang sedang terjadi pada keluarga Jakob dan kedua abangnya.
***
Dua bulan yang lalu, saat Jakob dan istrinya hendak berjualan di pasar, kedua abangnya tiba-tiba muncul di halaman rumahnya. Walau waktu itu matahari belum tampak, tetapi Jakob bisa melihat wajah kedua abangnya yang secerah mentari. Ketika istri Jakob menyambut mereka ramah, Jakob membeku di ambang pintu. Dia baru tersadar ketika istrinya menggoyangkan bahunya dan memintanya untuk segera memotong babi peliharaan mereka untuk dijadikan jamuan. Meskipun Jakob melakukan apa yang diminta istrinya dan menerima kedua abang beserta keluarga mereka masuk, hatinya meneriakkan kata tidak suka dengan kedatangan mereka.
Ketidaksukaan Jakob pada abang-abangnya itu bukan tanpa alasan. Saat kedua abangnya memutuskan untuk pergi hampir dua dasawarsa yang lalu, ibu sedang sekarat dimakan penyakit. Dan seakan mengejek harapannya, ibunya yang mati-matian bertahan hidup akhirnya pergi tanpa pamit dalam tidur. Tidak memiliki uang yang cukup, Jakob menguburkan ibunya di belakang rumah dengan acara sederhana, tanpa kehadiran kedua abangnya.
Tiga hari setelah kedatangan dua abangnya, saat matahari telah lama terbenam dan seluruh keluarga mereka sudah tertelan mimpi, tiga pria masih terjaga dibawah rona lampu teplok. Tidak ada sepatah katapun yang keluar dari bibir mereka sampai akhirnya abang tertua, amang Lamsihar menghembuskan napas panjang sambil menatap Jakob lekat-lekat. “Kami sudah mendengar soal ibu,” katanya pelan, “Dia dikubur dimana, Jakob?”
Jakob tidak segera menjawab. Buta karena amarah dan kesedihan, dia kembali menatap kedua abangnya dan menarik napas dalam-dalam, seakan enggan untuk memberitahukan keberadaan ibunya. Tapi dalam hatinya, Jakob sadar kalau kedua abangnya juga berhak untuk mengetahui keberadaan ibu mereka. Mau bagaimanapun keadaan mereka dan dirinya, mereka adalah keluarga. Pada akhirnya, Jakob menghembuskan napas perlahan, dan memberitahu mereka bahwa dia di kubur di belakang rumah.
“Kenapa ibu dikuburkan di sana?” tanya amang Ruhut, “Bukankah dulu ibu pernah bilang kalau dia ingin dikuburkan di antara leluhur kita?”
Mendengar perkataan amang Ruhut, hati Jakob serasa diiris pisau tumpul. Dia berusaha mengatupkan bibirnya serapat mungkin. Jakob mulai tertawa lirih, tetapi masih cukup terdengar oleh kedua abangnya yang menatapnya bingung. Dalam hati kecilnya, Jakob berharap kalau abangnya mengerti kesusahan dan sakit hati yang dicicipinya saat pemakaman ibunya terjadi.
“Hatiku sakit melihat kalian berdua,” tutur Jakob sambil mengepalkan kedua tangannya, berusaha mengendalikan rasa perih di hatinya yang kembali muncul, tetapi gagal ketika dia kembali menatap kedua abangnya dengan netranya yang memerah dan berkaca-kaca. “Abang bisa saja makmur di tanah Jawa. Punya uang, punya jabatan, punya keluarga yang sejahtera, tapi rasanya sekarang semuanya percuma saja.”
“Apa maksudmu, Jakob?” tanya amang Lamsihar dengan suara bergetar.
“Buat apa uang sebanyak pasir lautan, jabatan setinggi awan kalau kalian tidak pernah mendengar ratapan ibu?” Sambarnya pedas, “Jujur saja aku heran dengan ibu yang menangisi dua orang yang melupakan keluarganya di kampung.”
Jakob melihat air muka amang Ruhut yang mengeras, sementara amang Lamsihar hanya terdiam dengan lekukan memilukan menghiasi wajahnya yang keriput. Tidak ingin menuang minyak ke dalam api, Jakob berdiri tanpa mengatakan apapun dan meninggalkan kedua abangnya dalam kesunyian.
Sesampainya di kamar tidur, istri Jakob yang mengetahui sikap Jakob terhadap kedua abangnya berusaha menenangkan suaminya. Dia mengatakan bahwa ibu mertuanya tak akan senang dengan sikap Jakob yang terkesan kekanak-kanakan, dan tidak mau mendengarkan kedua abangnya yang sudah datang jauh-jauh demi melihat ibu mereka yang sudah tiada. “Adalah salah kalau kau mengusir mereka, Pak,” katanya selembut kain satin, “Jangan lupa, kalau kalian itu saudara satu darah dan ibu.”
“Lantas kenapa?” tanya Jakob sembari menggelengkan kepalanya, “Aku bukan marah karena mereka pergi ke Jawa demi memperbaiki keuangan mereka. Aku marah karena tidak sekalipun mereka pulang untuk menjenguk ibu. Dan sekarang, setelah ibu sudah mati selama dua belas tahun, mereka baru datang? Sudah tidak ada gunanya lagi keberadaan mereka disini.”
Tak mengatakan apapun, istrinya duduk di samping suaminya dan mengelus-elus pundaknya.
“Pak,” sanggah istrinya, “sadarkah kamu kalau apa yang baru saja kau katakan itu jahat? Janganlah hatimu jadi gelap karena ketidaktahuanmu itu.”
Jakob diam seribu bahasa sementara istrinya melanjutkan, “Bukalah hatimu, Pak. Beri mereka kesempatan dan waktu, itu saja.” Ujar istrinya meyakinkan.
***
Paginya, Jakob tengah bersiap untuk memberi makan ternak ketika tanpa sengaja dia melihat kedua abangnya yang tengah mengisap tembakau di depan rumah sambil menyesap kopi hitam yang masih mengepul. Sayup-sayup, Jakob dapat mendengar apa yang tengah mereka bicarakan. Dia tidak dapat mempercayai telinganya ketika amang Ruhut mengangkat suaranya, menyatakan penyesalannya karena tidak pulang kampung lebih cepat.
“Aku hanya bisa berandai, Bang,” ucapnya lesu, “seandainya aku pulang lebih cepat, mungkin aku masih bisa bertemu ibu. Dan mungkin saja Jakob tidak semarah ini.”
Jakob termenung. Ucapan amang Ruhut terus menerus berputar dalam kepalanya tanpa henti. Namun Jakob menggelengkan kepalanya dan pergi dari tempatnya berdiri tanpa memiliki niat untuk membuka hati. Rasa sakit hatinya sudah terlalu dalam menguasai dirinya.
Selepas memberi makan babi dan ayam peliharaannya, Jakob berjalan sembari mengenang ibunya. Pikirannya sekalut hatinya.
Saat Jakob melihat sekitarnya, dia sudah berdiri di samping kuburan ibunya dibelakang rumahnya. Jakob menatap kuburan ibunya sambil menghela napas panjang sebelum tersenyum kecil. Dia merasa kalau ibunyalah yang membawa dia kemari.
“Bu, ini anakmu, Jakob,” sapanya dalam hening, “Maaf kalau beberapa hari ini aku tidak bisa datang menjenguk.”
Jakob menceritakan kepada ibunya yang berada di langit bahwa kedua abangnya sudah kembali dari tanah Jawa setelah lama menghilang ditelan waktu dan bumi. Dia juga menceritakan keluh kesah yang tersembunyi dalam hatinya yang tidak memiliki kesempatan untuk berbicara.
“Entahlah Bu,” desahnya lirih, “Rasanya sudah tidak ada lagi yang benar dalam diriku ini,” katanya sambil menatap langit biru. “Aku merasa… apa yang aku lakukan ini tidaklah benar.”
Tidak ada yang menjawab selain suara tawa keponakannya dari dalam rumah. Jakob mengerjapkan kedua matanya beberapa kali sebelum menghela napas panjang sembari mengusap wajahnya yang sekasar pasir dengan gusar. Batinnya lelah. Sungguh, dia berharap ibunya dapat berbicara kepadanya sekarang dan memberikan sebuah petunjuk atau apapun. Namun kenyataan bahwa ibunya tidak lagi akan bisa membantu, menamparnya keras. Pada akhirnya, Jakob memutuskan untuk kembali masuk ke rumah tanpa mendapatkan jawaban dari siapapun.
***
Malamnya, Jakob terbangun dari tidurnya dan tidak bisa mempercayai matanya. Dia yakin sekali kalau semalam dia jatuh tertidur di dalam kamarnya dan bukannya di alam terbuka. Terlebih, yang membuat Jakob bergegas bangkit berdiri dari pembaringan adalah keberadaan ibunya yang tengah duduk bersila di sampingnya. Seakan mengajaknya untuk menari, rumput dihadapannya bergoyang dengan gemulai. Rambut ibunya yang digelung rapi dan mulai berwarna seputih tulang tersisir oleh angin. Ibunya menatap Jakob hangat dan tidak mengatakan apapun sambil menepuk tanah di sampingnya, meminta Jakob untuk duduk. Ragu-ragu, Jakob duduk di sebelah ibunya dengan kaku.
Tak ada yang berbicara di antara mereka untuk waktu yang cukup lama. Jakob sibuk dengan pikirannya yang mulai meracau. Dia sama sekali tidak tahu apakah ini tanda petaka, atau petunjuk dari Tuhan.
“Jakob,” panggil ibunya, “Bagaimana kabarmu?”
Jakob terdiam. Belum pernah dia mendengar suara ibunya yang sehalus sutera, bahkan ketika ibunya masih hidup. Mati-matian Jakob berusaha menahan tangis dengan mengangguk-anggukan kepalanya.
Ibunya mengelus pucuk kepala anaknya. Terlihat jelas guratan kebahagiaan terpancar dari wajahnya. “Bagus, bagus,” ibunya terus mengatakan hal yang sama sembari membiarkan Jakob tidur bertumpu pada pangkuannya, “Ibu lihat, kedua abang mu sudah pulang, ya.”
Jakob mengangguk dalam diam dan menutup kedua matanya, menikmati sentuhan kasih ibunya yang sudah lama tiada.
“Ibu senang sekali saat akangmu pulang setelah sekian lama tinggal di tanah Jawa,” ucapnya bahagia sebelum menatap netra Jakob dengan matanya yang bersinar, “Ibu lihat anak-anakmu dan anak kedua akangmu baik-baik.”
Jakob hanya mengangguk.
“Jakob, anakku,” lanjutnya, “Kenapa dengan hatimu, Nak?”
Jakob tercengang mendengar ibunya. Dia benar-benar tidak menyangka kalau ibunya mendengar perkataannya pagi tadi. Ingin rasanya dirinya bangkit dan membela dirinya, tapi bagai tersihir, tubuhnya tidak menuruti kemauannya.
“Mendengar perkataanmu pagi tadi, aku jadi teringat saat kamu berusaha membela keluarga kita empatbelas tahun lalu,” katanya sambil tertawa renyah.
Perkataan ibunya membuat Jakob teringat saat dirinya melemparkan tinju ke wajah salah satu pedagang yang dikenalnya di pasar. Sesungguhnya, Jakob tidak ingin menimbulkan kekacauan, tapi cibiran pedagang itu pada keluarganya membuat dirinya lepas kendali.
“Mana ada keluarga yang lupa akan kedudukannya!” serunya pada Jakob, “Tak pernahkah ibumu mengajari soal itu? Atau memang benar kalau sudah tak ada adat di keluargamu dengan mengizinkan akangmu pergi merantau dan membiarkan mereka melupakan dari mana mereka berasal?”
Hari itu pula, ibunya berkali-kali berlutut meminta maaf kepada seluruh orang di pasar karena keributan yang berkesan kekanakan yang dilakukan Jakob.
“Apa yang kau lakukan ke pedagang itu sama dengan apa yang kau lakukan pada kedua akangmu,” tuturnya, “Kau tidak mau mendengarkan kedua akangmu dan terlalu berpaku pada sakit hatimu.”
“Lalu aku harus apa?” tanya Jakob lemas, “Bukannya sudah terlambat buat mereka untuk melihat ibu?”
“Mereka kemari bukan tanpa alasan,” jawab ibunya sabar, “Ingat apa yang pernah istrimu katakan beberapa malam lalu?”
“Ya. Dia memintaku untuk membuka hatiku,” jawab Jakob sambil menahan tangis.
“Kalau begitu, lakukanlah,” kata ibunya sambil mengusap rambut Jakob yang seputih tulang, “Ibu yakin, mereka datang untuk kebaikan kalian bertiga.”
Jakob mengangguk lemah. Rasa berat di hatinya kini sirna terbawa angin saat air mata mengalir deras dari kedua matanya dan membasahi pakaian ibunya yang tertawa sambil menepuk-nepuk bahu Jakob.
“Janganlah menangisi aku, Nak,” hiburnya, “Tangisilah hatimu, dan ingat kalau tidak ada kata terlambat untuk meminta maaf.” Ibunya kini bangkit berdiri dan mulai berjalan menjauhi Jakob yang termenung menatap punggung ringkih ibunya yang semakin menjauh dan menghilang terbawa angin.
Jakob menutup kedua matanya, membiarkan air mata yang menggenangi kedua pelupuk matanya mengalir melintasi pipinya yang tirus sebelum terbangun dari tidurnya.
Istrinya yang tidur di sebelahnya terbangun. Dia mendapati suaminya yang duduk di ranjang, gemetaran dengan wajah seputih kertas. “Ada apa, Pak?” tanya istrinya sambil mengusap pelan pungung Jakob yang berkeringat.
“Aku tidak apa,” jawab Jakob dengan suara bergetar, “Hanya, mendapat sebuah pencerahan.”
***
Lepas beberapa hari, seluruh keluarga dari Jakob dan kedua abangnya berkumpul di ruang tengah. Jakob sendiri duduk diam sambil sesekali menghisap tembakau saat abangnya membenarkan tempat duduknya dan mulai berbicara mengenai alasan mereka pulang kampung. “Abang sudah membicarakan ini dengan amang Ruhut jauh sebelum kami sekeluarga berencana untuk datang, dan Ruhut beserta keluarga bersedia ikut serta,” ujar amang Lamsihar, “Akan tetapi Jakob, adat ini tidak akan bisa dilakukan tanpa restu darimu juga.”
Jakob menatap lurus amang Lamsihar. Meskipun dia paham akan adat yang dimaksud oleh kedua abangnya, rasa penasarannya memadamkan bara amarah yang tersisa dalam hatinya. “Apa maksud abang berdua?” tanyanya sebelum dia bisa menguasai bibirnya.
“Kami mau minta keikutsertaan dari keluargamu untuk memindahkan tulang belulang ibu ke tempat yang lebih baik.” balas amang Lamsihar, “Itulah alasan kami datang di saat yang bersamaan.”
“Kami tahu mungkin sudah terlambat bagi kami untuk bisa melihat ibu,” sambung amang Ruhut sambil tersenyum sendu, “Tapi hanya inilah yang bisa kami lakukan, setidaknya agar beliau bisa memiliki tempat peristirahatan yang lebih layak.”
Isak tangis terdengar dari bibir Jakob, diiringi dengan air mata yang mengalir semakin deras. Kedua abangnya terkejut melihat tangisan Jakob dan menanyakan ada apa gerangan. Jakob mengutarakan segala yang ada di dalam hatinya selama ini, terutama amarah yang menguasai dirinya. Berkali-kali Jakob membungkukan badan hingga kepalanya nyaris menyentuh lantai, memohon pengampunan dari kedua abang dan keluarganya.
“Jakob, janganlah membungkuk,” sambar amang Ruhut, “Kami juga sama bersalahnya dengan dirimu. Biarlah kita memperbaiki apa yang rusak, diawali dengan memindahkan ibu ke tempat yang lebih baik.”
Pagi itu, kabut yang seakan menutupi rumah kini lenyap, diganti dengan rona hangat matahari.
***
“Horas! Horas! Horas!” seru para penggali kubur, menandakan tulang ibu si empunya acara telah ditemukan. Jakob bersama abang-abangnya segera membalas seruan yang bermakna doa ucapan syukur itu. Mereka sudah siap dengan kain putih di tangan masing-masing untuk menerima tulang ibu mereka. Mereka membawa tumpukan tulang ibunya ke tempat yang telah disediakan untuk dibersihkan dengan air campuran kunyit dan jeruk nipis.
Saat Jakob membersihkan tulang ibunya, perkataan ibunya menghampiri pikirannya. Terngiang di telinganya suara ibunya yang lembut, yang menyibakkan tabir amarah yang menyelubungi mata hatinya. Satu-satunya suara yang membimbing hati Jakob keluar dari ketersesatan di kekelaman. Air mata kelegaan meleleh dari pelupuk mata Jakob.
*****