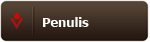Rumah Kawin
Zen Hae menulis puisi, cerita, dan kritik sastra. Telah menghasilkan dua buku: kumpulan cerita pendek Rumah Kawin (KataKita, 2004) dan buku puisi Paus Merah Jambu (Akar Indonesia, 2007) – yang terakhir ini masuk lima besar Khatulistiwa Literary Award 2008 dan mendapatkan predikat “Karya Sastra Terbaik 2007” dari majalah Tempo. Menamatkan pendidikan di Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia IKIP Jakarta (kini Universitas Negeri Jakarta) pada 1994. Pernah menjadi wartawan, pekerja LSM, penulis naskah infotainmen dan dosen paruh waktu. Anggota Komite Sastra Dewan Kesenian Jakarta (2006-2012) dan Ketua Komite Sastra DKJ (2006-2009) dan Ketua Bidang Kajian dan Kritik DKJ (2011-2012). Sejak Februari 2012 ia adalah Manajer Penerbitan di Komunitas Salihara.
“Rumah Kawin” terbit pertama kali di Kompas (4 Juni 2003). Edisi perubahan Hak Cipta © 2014 oleh Zen Hae. Terbit atas ijin dari penulis. Hak Cipta terjemahan © 2014 oleh Indah Lestari.
***
Rumah Kawin
Lagu “Malam Terakhir” baru saja berakhir dari mulut Gwat Nio dan Karna Suling. Para wayang cokek sudah mengosongkan kalangan, bersiap-siap untuk pulang. Para panjak membereskan alat musik mereka. Tetapi Mamat Jago masih saja berdiri sambil memeluk Sarti di tengah kalangan.Tangannya terus meremasi pantat Sarti dan menyorongkan mulutnya ke mulut wayang bermata burung hantu itu.
Bau anggur kolesom kembali menerpa hidung Sarti. Ia melengos dan berusaha mendorong tubuh Mamat Jago sekuat tenaga, tetapi dengan cepat Mamat Jago meraih tangan Sarti dan melipatkannya ke pinggangnya.
Kali ini Mamat Jago menggoyang-goyangkan pinggangnya sambil terus menekan pantat Sarti. Batang zakar Mamat Jago terasa seperti ikan gabus, menekan selangkangan Sarti.
Wayang cokek itu meringis, mencoba menggeser pantatnya.
“Aih jangan tinggalkan Abang, Manis. Jangan biarkan pancuran ini ngucur sendirian. Aaaghh.”
“Heh, Minan, gesekin gua lagu ‘Ayam Jago’. Gua mau ngibing lagi,” teriak Mamat Jago, tiba-tiba.
Minan Balok, si tukang teh yan, celingukan. Balo si tukang gambang menggelengkan kepalanya. Pemain musik lainnya menangguk. Tak mungkin lagi mereka main. Ini sudah pukul dua pagi. Sudah waktunya rombongan Gambang Kromong Mustika Tanjung pimpinan Tan Eng Djin dari Teluk Naga berhenti main.
Sahibul hajat, keluarga Lie Ban Hoa dari Salembaran dan keluarga Fai Koen Atmadja dari Kapuk, sudah meminta mereka berhenti sejak setengah jam lalu. Sebab izin keramaian yang mereka dapatkan dari aparat keamanan setempat hanya sampai pukul satu.
“Heh, budek lu. Gua masih banyak duit. Kalo perlu pala lu semua gua beli. Gua mau nyawer lagi. Ayo,” teriak Mamat Jago sambil menuding-nuding para panjak yang masih bersambut pandang.
Sarti kembali mengibaskan tangannya. Menarik tubuhnya dari pelukan Mamat Jago yang kian sempoyongan. Terlepas.
Sebagai gantinya satu tamparan tangan kanan Mamat Jago mendarat di pipinya. “Sundel lu!” maki Mamat Jago sambil melempar cukin merah hati ke wajah Sarti.
Sarti meringis dan memegangi pipinya, berlari ke arah wayang lain yang sejak tadi hanya bisa memandanginya dengan cemas.
Ini sudah kelewatan, pikir Eng Djin. Anak buahnya memang boleh dipeluk, dicium, atau dibawa ke mana saja, tetapi pantang disakiti. Ia pun keluar dari sela-sela gong dan menghampiri pengibing mabuk itu. Merendengnya. “Maaf, kita harus berhenti, Bang. Kalau tidak cokek kita bakal ditubruk polisi.”
“Jangan takut, Koh. Mereka semua teman saya. Ayo, main lagi.
Bang Minan mulai menggesek teh yan-nya, tetapi segera Eng Djin menggoyang-goyangkan tangan kirinya. “Mendingan Abang pulang saja. Nanti kita-kita juga yang repot.”
“Sial dangkalan lu,” maki Mamat Jago. Dengan sisa tenaganya disodoknya perut Eng Djin, tetapi ia menepiskan tangan itu. Mamat Jago balas menyerang dengan pukulan siku yang diruncingkan—gentus tubruk.
Eng Djin jatuh terduduk.
“Engkoh jangan bikin saya malu ya. Saya jawara kampung. Jago berantem. Semua orang bisa saya bikin jatoh deprok.”
Eng Djin bangkit dan mundur selangkah. Bersandar pada tiang. Dipandanginya kepalan tangan Mamat Jago yang padat berisi. Empat belas jurus ilmu pukul memang masih dikuasainya, tetapi ia sadar, tidak mungkin menandingi kemahiran pukulan jawara kampung Bulak Petir ini. Namun, ia akan melawan sebisanya kalau Mamat Jago menyerang lagi. Itulah cara ia mempertahankan harga dirinya di depan anak buahnya.
Ternyata, tidak. Mamat Jago hanya memasang jurus. Kuda-kudanya kelihatan goyah. Tubuhnya goyang seperti orang-orangan sawah.
Tiba-tiba, dua orang berjaket kulit hitam, si Gondrong dan si Cepak, masuk ke kalangan. Eiiitt, Mamat Jago mengalihkan kuda-kudanya ke arah dua orang asing itu. Mencoba lebih awas, ia kibas-kibaskan kepalanya.
Si Gondrong lantas mencabut revolver dari balik jaketnya dan mengacungkannya ke udara.
Orang-orang terkesiap. Ada juga yang menjerit.
“Bapak-ibu saya minta berhenti. Bubar!” Si Gondrong memerintah.
Dengan sigap Si Cepak mencekal tangan Mamat Jago, memitingnya, memborgolnya, dan menyeretnya seperti sekarung tahi ayam.
***
Entah sudah berapa lebaran lewat setelah penangkapan itu. Mamat Jago tersenyum. “Sudah lama sekali,” gumamnya. Saat itu dengan mudah ia masuk-keluar sel. Ditangkap malam, keluar pagi; dibekuk pagi, dilepas sore; masuk sore, keluar malam. Anak-anak buahnya akan mengantarkan uang tebusan, tak lama setelah ia digelandang polisi. “Polisi teman Abang,” katanya berkali-kali kepada anak buahnya. Setelah itu ia akan dengan leluasa datang lagi ke rumah kawin, ngibing dan minum, membuat keributan bila perlu.
Tetapi, itu dulu. Ketika kekayaan dan kehormatan didekapnya dengan dua tangan. Ketika jual-beli tanah kebun dan sawah di kampungnya sedang ramai-ramainya. Setiap saat orang datang dan pergi dari rumahnya. Membawa dan mengambil uang. Pekerjaannya sebagai calo tanah sangat sibuk kala itu. Pernah suatu ketika anak buahnya harus memanggul berkarung-karung uang ke rumahnya untuk membebaskan berhektar-hektar sawah yang kini menjadi bandar udara itu. Orang-orang kampungnya pernah berkata, ia tidur bukan di atas kasur kapuk, tetapi di atas kasur uang.
Sekarang ini semuanya sudah lain. Kekayaan dan kehormatannya rontok sudah, seperti pohon kelapa disambar petir. Meranggas dan mati. Tanahnya yang dulu hektaran kini hanya tinggal sepekarangan saja, menciut bagai kelaras terbakar. Di atasnya berdiri rumah yang dulu pernah menjadi rumah termegah dan termahal di kampungnya—kini sudah menjadi sarang kumbang, ngengat, dan laba-laba. Kosong, kusam, sepi. Mobil dan motornya entah di tangan siapa.
Puluhan kerbaunya tak berjejak lagi. Kambing dan ayam hanya tinggal sekandang. Anak buahnya yang berjumlah puluhan sudah pergi meninggalkannya, mencari majikan baru begitu ia bangkrut.
Masroh, istri yang tak pernah lagi disentuhnya sejak diserang TBC, wafat dua tahun lalu. Tiga anak perempuannya sudah dibawa suami mereka ke kota lain. Menjadi orang rantau. Satu anak lelakinya menjadi pengojek untuk menghidupi istri dan empat anaknya. Hanya ia dan si bungsu yang tinggal di situ.
Ah, betapa perihnya kehilangan ini. Mamat Jago batuk satu-dua. “Apa ada obatnya?” ia bergumam.
Pekerjaan sebagai calo tanah sudah tidak dilakoninya lagi. Tidak ada lagi orang yang mau menjual kebun dan sawahnya. Tanah warisan mereka sudah habis terjual, tinggal yang kini mereka tempati. Dan itu tak mungkin mereka jual, kecuali kalau mereka mau menjadi gelandangan di kampung sendiri. Lahan-lahan yang tadinya menjadi sumber penghidupan mereka kini sudah berubah kegunaannya.
Ratusan hektar sawah itu sudah dibikin rata tanpa pematang dan diberi pagar besi setinggi dua meter di tepinya. Di tengahnya membujur dua jalur landasan beton, dari barat ke timur. Ia dan orang kampungnya hanya bisa memandangi pesawat terbang yang lepas landas dan mendarat. Hanya mereka yang pernah naik haji mampu menaikinya. Di malam hari pesawat-pesawat itu berubah menjadi kunang-kunang raksasa yang tubuhnya tetap berkelap-kelip meski melayang di batas langit terjauh.
Pabrik-pabrik juga sudah berjalan siang dan malam. Siapa pun orang terkaya di kampungnya tidak mungkin membangun dan memiliki pabrik-pabrik itu. Mereka hanya petani penggarap dan pedagang kecil, tidak mungkin menguasai modal dan teknologi perpabrikan secanggih itu. Tapi, anak-anak mereka, lelaki dan perempuan, si bungsu juga, senantiasa berbondong-bondong, keluar masuk pabrik, dengan seragam. Mereka sudah menjadi manusia pabrik yang mau tidak mau dibayar murah oleh tauke-tauke dari Korea, Jepang, dan Taiwan.
Rumah-rumah mewah juga sudah dibangun dan ditempati orang-orang yang tidak pernah mereka kenal sebelumnya. Orang-orang kampung memang tidak mampu membeli dan menempati rumah mahal itu, tetapi mereka masih bisa menjadi pengojek di perumahan itu dengan motor yang dibeli dari hasil menjual tanah warisan mereka. Mereka masih bisa menikmati jalan-jalan aspal yang lurus-menyiku, sungai kecil yang jernih dan dibeton tepinya, taman yang indah, sambil memandangi rumah-rumah besar dengan pintu dan jendela yang melengkung. Rumah-rumah yang dahulu mereka saksikan di layar-layar lenong. Di tambah gonggongan anjing, tentu saja.
Mamat Jago menarik napas dalam-dalam sebagaimana ia menarik kenangan-kenangan yang terkubur dalam liang gelap masa lalunya. “Aku butuh obat,” ia bergumam sembari menelan ludah.
Aroma tanah basah dibawa angin selatan melintasi padang ilalang setinggi pinggang. Hujan akan segera turun. Musim penghujan sudah tiba dan akan makin tinggi curahnya menjelang Lebaran Cina atau Tahun Baru Imlek. Musim kawin akan tiba juga. Rumah-rumah kawin di Kampung Melayu, Kosambi, Salembaran, dan Sewan akan ramai lagi. Ia rindukan semua itu.
***
Dalam mimpinya sore itu, Mamat Jago mendatangi lagi rumah kawin Teratai Putih. Orang-orang menyingkir begitu ia memasuki pintu utamanya. Ia memasang langkah tegap seorang jawara kampung. Hanya di sinilah aku bisa menikmati lagi seluruh kesenangan dan kehormatan hidupku, pikirnya sembari tersenyum. Bukankah sudah bertahun-tahun belakangan ini ia tidak menikmati dua hal itu lagi. Ya, di sinilah orang akan memuji kelihaiannya ngibing yang dipadu dengan keindahan jurus-jurus pukulnya, kekuatannya menenggak berbotol-botol bir bercampur anggur kolesom, keroyalannya nyawer. Dan tubuh wayang yang panas dan memabukkan! Liukan dan goyangan yang membangkitkan syahwat! Aih, lelaki mana yang bisa tahan.
Nyai Sirah, si tukang cuking, menyambut Mamat Jago dengan selendang merah hati, seperti dulu. Perempuan bersusur sebesar telur puyuh itu kemudian mengalungkan selendang itu di leher Mamat Jago, tanda ia harus turun ke kalangan, memilih wayang mana yang ia suka.
Tapi hanya Sarti yang ia tuju. Ditatapnya Sarti yang duduk di pojok, bersebelahan dengan Minan Balok. Kali ini Sarti memakai kaus hijau daun pisang bergambar naga merah jambu yang melintas dari bawah ke atas dan celana capri krem. Dengan pakaian itu ia tampak lebih muda dari usianya yang sebenarnya. Sedikit gemuk membuat lekukan-lekukan tubuhnya tampak nyata dibalut pakaian yang serba ketat itu.
Darahnya berdesir. Ditariknya tangan wayang cokek kecintaannya itu. Sarti tersenyum dan mengikuti Mamat Jago dengan langkah merpati. Pengibing dan wayang lain sengaja mengosongkan kalangan, memberi penghormatan atas kembalinya si raja ngibing dari Bulak Petir itu.
Dengan dagu yang sedikit mendongak Mamat Jago menebar pandangan ke seluruh ruang. Tak lupa ia mengangkat kedua tangan yang dikepalkan, tanda hormat kepada sahibul hajat, kedua mempelai, dan Tan Eng Djin.
Bang Minan menjawab salam Mamat Jago dengan menggesek teh yan-nya.
“Ayo, Minan, gesekin gua lagu ‘Ayam Jago’. Gua mau ngibing lagi.”
Teh yan digesek, disusul gambang, kecrek, gong, suling, dan kempul. Susul-menyusul. Jalin-menjalin. Gwat Nio sudah melantunkan suaranya yang garing-melengking seperti suara burung titutit.
“Ayam jago jangan diadu, kalau diadu jenggernya merah.
Ayam jago jangan diadu, kalau diadu jenggernya merah.
Baju ijo jangan diganggu, kalau diganggu yang punya marah.
Baju ijo jangan diganggu, kalau diganggung yang punya marah.”
Tapi Sarti tidak juga menggoyangkan tubuhnya. Tangannya dibiarkan terkulai.
Mamat Jago meraihnya, melipatkannya ke pinggangnya, merapatkan pelukannya. Tubuh perempuan itu terasa dingin, seperti daun dadap pengusir demam anak-anak. Ia menatap paras Sarti; bibirnya terkatup, matanya terpejam. “Ayo, Sarti, jangan kau goda Abang seperti malam-malam dulu!” kata Mamat Jago sambil menggoyang-goyangkannya tubuh Sarti. Ditepuk-tepuknya pipinya, tak ada gerakan sedikit pun. Dipandanginya para panjak. Semuanya berhenti main. Tak ada yang bergerak. Semua dingin dan biru. Seperti keramik Cina.
Mamat Jago membopong Sarti keluar. Penonton yang semulai menyesaki kalangan dan halaman rumah kawin sudah tak ada lagi. Dengan was-was ia menjejaki halaman, menerobos hujan senja yang turun bagaikan lapis-lapis kelambu. Sepanjang jalan pohon-pohon meliuk-mabuk, rumah-rumah bisu-merunduk. Nyala lampu listrik dan patromaks tampak setengah hidup setengah mati. Ia susuri jalan aspal, memotong sungai, membelah padang ilalang.
“Kau tidak boleh mati, Sayang. Hiduplah bersama Abang. Di rumahku kau akan hangat.” Dikecupnya bibir Sarti. Air liur nya yang bercampur air hujan masuk ke mulut Sarti.
Si mata burung hantu itu tersedak. Tubuhnya menggeliat. Tangannya meraih leher Mamat Jago.
Ia tersenyum dan mempercepat langkahnya.
Malam dan hujan pertama benar-benar telah mengepung kampung Bulak Petir. Dari kejauhan rumah Mamat Jago yang terletak di tepi sawah bera dengan jalan yang lurus memotong pematang tampak bagaikan lukisan luntur. Satu-dua lampunya menyala.
Ah, anak yang baik, pikir Mamat Jago. Pasti Si Bungsu menyalakan lampu-lampu itu sebelum berangkat ke pabrik untuk kerja malam.
Cahaya lampu-lampu itu senantiasa membangkitkan keriangan masa mudanya. Bukankah dulu ketika masih berpacaran, bahkan setelah menikah dan anak-anaknya belum lahir dan menyesaki rumah, ia dan Masroh selalu berlarian di atas pematang sawah begitu hujan pertama turun. Setelah basah kuyup oleh air hujan barulah mereka mandi di sumur senggot yang airnya terasa lebih hangat daripada air hujan. Buatnya, laku itu semacam perayaan untuk datangnya musim hujan.
Pintu rumahnya tidak terkunci. Dasar anak ceroboh, maki Mamat dalam hati, pasti Si Bungsu lupa menguncinya. Ia mendorong pintu dengan punggungnya dan langsung menuju kamar tidur. Ia membaringkan Sarti di ranjang. Di situlah dulu Masroh mengembuskan napas terakhirnya dengan tubuh kurus kering dan sepasang payudara yang serupa jeruk busuk.
Mamat melucuti seluruh pakaian basah dari tubuh Sarti dan menyelimuti tubuh itu dengan kain batik yang dulu pernah dipakai untuk menyelimuti mayat istrinya. Ia pandangi wajah Sarti yang tertidur pulas. Dalam keremangan wajah itu berganti-ganti dengan wajah istrinya.
“Pacarku, biniku.”
Mamat Jago mengecup bibir Sarti. Bibir itu terasa bergerak. Balas melumat.
Tangan Sarti perlahan mendekap Mamat Jago. Ia mulai bernapas satu-dua. Hangat, panas, gemuruh.
Mamat Jago balas mendekapnya lebih erat lagi. Kini kehangatan menjalari tubuh mereka berdua.
Sarti mengerang sambil mencengkeram punggung Mamat Jago. Dalam sekejap mereka telah bergumul di atas kasur ringsek. Mereka saling memagut-mematuk-mengecup-merenggut- mencakar-mengular, terbakar.
Tiba-tiba, brak! Mamat Jago kaget dan melepaskan pelukannya.
Eng Djin, si Gondrong, dan si Cepak sudah berdiri di pelangkahan pintu. Buru-buru Mamat Jago meraih dan mengenakan celana kolornya.
“Sadarlah, Bang. Sarti sudah mati,” kata Eng Djin.
Mamat Jago menoleh.
Sarti terbaring telanjang kaku dengan sisa-sisa keringat yang meleleh di sela-sela payudaranya.
Tak percaya Mamat Jago menepuk-nepuk pipi Sarti. “Ayo, manis, bangun. Ada Koh Eng Djin dan teman Abang datang,” bisiknya ke telinga Sarti.
“Relakan kepergiannya, Bang. Nyebut, Bang.”
Mamat Jago masih tak percaya. Ia mengguncang-guncangkan tubuh Sarti. Kaku, dingin, biru. Tangisan pilu kemudian meledak dari mulutnya. Tangis yang sudah lama sekali baru terdengar lagi. Ketika Masroh mati pun ia tidak terbujuk untuk menangis.
Eng Djin hanya menarik napas menyaksikan lelaki malang itu. Tanpa aba-aba Si Gondrong dan Si Cepak langsung membekuk Mamat Jago. Mereka menggelandang Mamat Jago dan memasukkannya ke mobil jip.
Sepanjang jalan kedua polisi yang diakui sebagai temannya itu tidak mengajak Mamat Jago bicara. Si Cepak sibuk menyetir, Si Gondrong asyik merokok.
Mamat Jago mengamati borgol di tangannya yang kadang berkilatan oleh cahaya yang menembus kaca mobil. Baja antikarat ini benar-benar membuatnya tidak berkutik.
Terutama ketika mobil terguncang-guncang di jalan berlubang, tubuhnya terpental dan membentur pintu belakang mobil. Ia mengaduh dan Si Gondrong hanya menoleh dengan rokok yang tetap terjepit di bibirnya.
Akhirnya Mamat Jago menyandarkan tubuhnya ke jok dan membuang pandangannya ke kaca pintu belakang. Ia menyaksikan cahaya lampu-lampu rumah yang meleleh dan membentuk garis panjang bergelombang. Tapi ia juga melihat tubuh Sarti yang telanjang berkeringat mengikuti mobil yang entah menuju ke mana. Tubuh Sarti melayang seperti ikan terbang. Benarkah Sarti sudah mati? Mungkinkah aku menyenggamai mayat, Mamat Jago membatin. Bukankah di atas ranjang Sarti balas membalas kecupan dan pelukannya dan mereka bergumul hebat seperti di malam-malam dulu.
Tiba-tiba mobil berhenti. Pintu belakangnya dibuka paksa. “Keluar lu!” Bentakan Si Gondrong membuatnya ternganga. Mamat Jago tak punya lagi kuasa untuk menolak. Ia melompat. Telapak kakinya amblas di hamparan pasir.
Si Gondrong dan Si Cepak menggiringnya ke sebuah tempat gelap. Ada debur ombak. Kersik daun. Serbuk garam yang menempeli bibirnya. Ia menduga-duga pantai apa ini. Mungkin Tanjung Kait, Rawa Saban, Kamal, atau pantai yang belum pernah ia kunjungi. Dorongan keras membuatnya tersandung karang dan tersungkur. Butiran pasir asin memenuhi mulutnya.
“Kami tidak pernah benar-benar berteman denganmu. Kami berteman untuk bisa membekuk bajingan macam kau. Malam ini hidupmu tamat,” suara Si Cepak mengalahkan deru ombak.
Dor! Dor! Dor!
Darah meleleh dari tiga lubang di pelipis dan dahi Mamat Jago. Diserap pasir, dijilat ombak, larut di air.
***
Dor! Dor! Dor!
Mamat Jago terjaga. Ia bangkit, seperti ada yang mengusap wajahnya. “Sarti!” ia memanggil. Tak ada jawaban. Ia kemudian mengusap dahi dan pelipisnya. Tak ada darah. Hanya air hujan dari genting bocor! “Mimpi apa lagi ini?” katanya, heran. Ia duduk di tepi ranjang. Ditajamkan pendengarannya, rentetan tembakan itu masih terdengar. Aih, ia tersenyum, rupanya hanya suara petasan dari rumah kawin! Ia berjalan menuju jendela dan menguakkannya. Hujan sudah berhenti, tetapi air masih menggenang di pelataran rumahnya. Begitu juga kenangannya pada Sarti, Eng Djin, Si Cepak, dan Si Gondrong. Dan Sarti! Mengapa kau muncul dalam mimpiku dengan cara seaneh itu, ia membatin lagi.
Tanpa membuang waktu ia membuka lemari dan mengambil pakaian terbaiknya. Baju safari dan celana panjang krem, topi laken coklat tua, sandal kulit hitam, tongkat kayu dengan gagang berukir kepala naga membuat ia merasa gagah kembali. Tapi cermin buram di depannya tak bisa menyembunyikan pipinya yang mulai keriput dan kantung matanya yang bergantung. Lama ia tatap wajah tuanya sehingga ia terbatuk. Tubuhnya terguncang-guncang, bayangnya terkekeh-kekeh. “Dasar bini sialan!”
“Aku harus kembali ke rumah kawin itu.” Mamat Jago mengetuk-ngetukkan ujung tongkatnya ke lantai teraso. Tiga kali. Hatinya mantap.
Rumah kawin Teratai Putih masih seperti dulu. Orang-orang masih menyingkir begitu Mamat Jago masuk kalangan. Ia kembali memberi hormat kepada sahibul hajat, kedua mempelai, Tan Eng Djin, panjak, dan wayang cokek yang secara bergantian membalas salamnya.
Tapi Sarti hanya memonyongkan mulutnya dan mengembuskan asap rokoknya ke arah Mamat Jago.
Si Tua itu hanya tersenyum dan membalas Sarti dengan lagak serupa.
Sarti langsung menggilas puntung rokok dengan kelom geulisnya. “Sudah lama Abang gak ke sini. Sarti kangen,” kata Sarti sambil mengalungkan cukin merah hati ke leher Mamat Jago.
“Abang banyak urusan, Neng,” kata Mamat Jago sambil mendekap pinggang Sarti.
Tanpa diminta, Minan menggesek teh yan-nya.
Bunyinya yang lirih membuat Mamat Jago mendekap Sarti lebih mesra lagi. Seperti ada lubang hitam di dada Mamat Jago yang hanya bisa tertutup jika ia mendekap wayang cokek kecintaannya itu. Bait pertama lagu “Stambul Siliwangi” kemudian mengalun dari mulut Gwat Nio.
“Ya jika begini, kalo begini, Karna, nagalah ya naganya.
Aih, kayulah ya biduk, kayulah biduk ya dimakan api.
Ya kalo begini, kalo begini, Sayang, apa rasanya.
Aih, badanlah hidup, ya badan hidup, ya rasanya mati.”
Karna menyusul dengan suara bergelombang. Sesekali Mamat Jago mengikuti,
“Ya bunga mawar, Manis, bunga mawar, Jiwa Manis, dari Kahyangan.
Ya indung-indung, ya jeruk purut, Nona.
Ya jeruk purut, Jiwa Manis, harum baunya.
Ya belajar kenal, Nio, belajar kenal, Jiwa Manis, tidak halangan.
Aih. . .indung-indung, ya cuma awan.
Ya cuma awan, Jiwa Manis, ada yang punya.”
Para pengibing dan pasangannya turut melingkari Mamat Jago dan Sarti. Tapi tak ada yang sanggup menari. Semuanya hanya berdekapan. Tiba-tiba Mamat Jago terbatuk. Suaranya kisut, napasnya turun naik.
Sarti mengusap-usap punggung Mamat Jago. “Abang sakit.”
“Abang sakit cinta.”
“Berobat dong.”
“Enggak ah. Abang kepingin ke rumah kawin aja. Ke dokter Sarti.” “Ah, Sarti banyak pasen.”
“Rawatlah Abang, Bu Dokter. Jadiin saya satu-satunya pasen.”
“Tong ah.”
“Tadi Abang mimpiin Sarti dan semua orang di rumah kawin ini.”
“Masak? Apa ceritanya.”
“Ah, malu nyeritainnya.”
“Apaan?” Sarti mencubit paha Mamat Jago.
“Kita main dokter-dokteran.”
“Ih, jorok.” Sarti meremas selangkangan Mamat Jago.
Mamat Jago mengerang dan menekan pantat Sarti.
Kali ini Sarti membiarkan Mamat Jago meremas dan menekan pantatnya. Ada api yang meletup dari bekas lubang hitam itu. Suhu badan Mamat Jago merambat hangat dan menjalar ke tubuh Sarti.
Api menjalar ke tubuh pengibing dan wayang cokek lainnya. Semuanya terbakar.
Para penonton menelan ludah. Seorang anak kecil, sembari berjongkok, meremas selangkangannya.
“Pulang yuk sama Abang.”
“Pulang ke mana.”
“Pulang.”
Batuk Mamat Jago meletus lagi, bertanding dengan suara gambang. Napasnya seperti bunyi perahu ngadat. Hingga pada satu pukulan gong, napasnya mereda.
Sarti menjerit.
Orang-orang menoleh.
Tubuh Mamat Jago bertumpu di tubuh Sarti.
“Terus main. Gua bakal mati kalo gambang berhenti,” kata Mamat Jago dalam dua kali jeda. Setengah berbisik, setengah menjerit.
Para panjak tetap diam. Pelan-pelan tubuh Mamat Jago merosot ke lantai.
Sarti meletakkan kepala Mamat Jago di pangkuannya. Ia tersenyum, hanya bisa tersenyum, sambil mengusap-usap wajah Mamat Jago.
Dalam hitungan detik Mamat Jago masih bisa menyaksikan wajah Sarti berubah menjadi wajah seorang perempuan muda. Itulah perempuan yang pernah mengajak Mamat Jago tamasya ke sebuah pulau kecil di pantai utara. Saat itu Mamat Jago baru khatam membaca Quran. Sebagai hadiah perempuan itu mengajaknya tamasya. Mereka berdua saja ke pulau penuh pohon kelingkit, elang bondol, burung camar, ganggang, rajungan itu. Masa tamasya paling indah itu mungkin hanya beberapa menit, satu dua jam, seharian, berkali bulan. Mamat Jago tak bisa mengingatnya lagi. Tapi ia hafal betul senyum perempuan itu. Dan ia merasa bahagia.
***