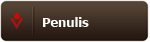Semayamkan Mamak
Lintang Amartya Padmarini adalah perempuan kelahiran 2002 yang dibesarkan di Sleman, Yogyakarta. Sehari-harinya, Lintang adalah mahasiswa Studi Perdamaian dan Konflik di S1 Hubungan Internasional UGM. Dia turut berkecimpung di Girl Up UGM, perkumpulan yang menyuarakan kesetaraan antara lelaki dan perempuan di kampusnya. Perjalanannya menempuh pendidikan di jenjang perguruan tinggi mengenalkannya pada banyak peminatan baru, termasuk di antaranya pemberdayaan perempuan, menentang kekerasan, dan mendukung perdamaian. Walau demikian, Lintang tetap menggemari kesusastraan Indonesia, khususnya buku-buku Ahmad Tohari. Judul novelnya Lintang Kemukus Dini Hari mengilhami nama Lintang.
Lintang dapat dihubungi melalui surel: lintangamartya02@gmail.com
Semayamkan Mamak
Tidak bosan-bosannya aku mengenang kisah hidup Mamak yang dia ceritakan sendiri selama hidupnya. Menurut cerita tersebut, aku terlahir sebagai anak haram. Mamakku wanita Jawa baik-baik, dilahirkan oleh keluarga terhormat yang bermukim di Semarang, sebuah kota pelabuhan di Pulau Jawa, jauh dari Pulau Buru ini. Dia mengungkapkan bahwa dirinya dan serombongan gadis seumurannya diboyong paksa ke Pulau Buru untuk dijadikan wanita penghibur oleh tentara Dai Nippon. Mamak berkata merekalah yang menduduki tanah air kita selama Perang Dunia II berlangsung di Indopasifik dari 1942 hingga 1944.
Mamak mengutuk para serdadu keparat yang setelah menghamili gadis-gadis itu, langsung pergi meninggalkan mereka begitu Jepang dikabarkan kalah. Miris hatiku mendengar penggambaran Mamak akan betapa kejamnya perilaku serdadu Jepang tersebut.
Tidak hanya sampai di situ, Mamak turut mengenang bagaimana dia dan sekumpulan gadis-gadis lainnya tidak punya perlindungan di tengah-tengah pulau terpencil yang langka penghuni. Mereka terancam kelaparan, melahirkan tidak selamat, dan terjangkit penyakit malaria. Satu per satu tumbang. Hanya Mamak dan seorang temannya yang selamat. Keduanya akhirnya menikah dengan laki-laki penduduk suku Alfuru, seorang di antaranya adalah bapak tiriku. Berdasarkan kisahnya, Mamak dan bapak tiriku menikah hanya karena dengan itulah, Mamak dapat bertahan hidup, sedangkan Bapak menikahi Mamak karena kecantikannya.
Lahirlah aku di tengah-tengah suku Alfuru, suku pedalaman di Pulau Buru, pulau terpencil yang adalah bagian dari kepulauan Maluku. Akulah satu-satunya kulit kuning di antara kulit kehitaman khas penduduk asli pulau itu. Satu-satunya sipit di antara wajah-wajah bermata bulat di pulau itu. Rasanya seperti diriku ini memang ditakdirkan untuk diasingkan. Tidak ada yang mau berteman denganku, apalagi mengajak berburu. Temanku hanya Mamak, orang pertama yang mengajariku bahasa Indonesia. Setiap kali waktuku tidak kuhabiskan untuk berburu, pastilah aku bercengkerama dengan Mamak menggunakan bahasa Indonesia. Mamak adalah wanita cerdas yang dapat dengan mudahnya mengenalkanku ke bahasa ibunya itu, sehingga jadilah bahasa itu bahasa rahasia kami berdua di Pulau Buru.
Karena Mamak dan bapak tiriku tidak menikah atas dasar cinta, begitupun hubunganku dengan bapak tiriku itu. Dia tidak punya pilihan lain selain menerima keberadaanku karena dengan demikian, Mamak mau mempertahankan pernikahan mereka. Mustahil menghadirkan adik sambung yang dapat memperbaiki hubungan kami karena setelah melahirkanku dengan susah payah, rahim Mamak tidak kuat menaungi jabang bayi lagi. Hubungan kami tetap dingin, hampir-hampir disisipi benci. Setiap kali bapak tiriku mulai mencak-mencak karena gagal menangkap hewan buruan, Mamak selalu berbisik kepadaku dalam bahasa Indonesia, “Lari! Lari sebelum kamu kena pukul.”
***
Di tahun 1969, beberapa bulan setelah Mamak meninggal ketika umurku 25, Pulau Buru kedatangan penghuni baru. Mereka orang-orang dari Jawa, kebanyakan lelaki. Semuanya bisa bicara bahasa Indonesia. Perawakan sebagian besar diantaranya mirip Mamak, bahkan ketika kutemui lebih dekat, cara bicara mereka juga mirip. Kagum betul aku. Walau ternyata mereka lebih kagum — dan juga kaget — ketika melihat lelaki sipit kuning berpakaian bawahan kolor khas Alfuru tapi mirip Asia Timur. Para penghuni baru ini lebih kaget lagi ketika mengetahui aku mampu berbahasa Indonesia, walau jauh dari kata mahir.
Diketahuilah bahwa orang-orang itu adalah tahanan. Aku melihat bagaimana mereka ditertibkan dengan kekerasan, sebagaimana yang dilakukan bapak tiriku kepadaku. Pada waktu itu memang kemampuan bahasaku sangat payah, tapi manusia tetap bisa mencium amarah dan penindasan, dalam keterbatasan berbahasa sekalipun. Terenyuhlah aku melihat mereka, mengingat kami sama-sama korban amarah dan penindasan.
Ada seorang di antara mereka yang sangat membekas. Karman namanya. Lelaki yang gagah, tegap, seumur bapak tiriku. Bedanya dengan bapak tiriku, Karman tidak pernah memarahi, apalagi memukulku. Kami berteman baik sejak dia mendapati kehadiranku yang malu-malu mengintip dari balik pagar penjara. Dia menyapaku dan menggaetku dalam perbincangan mendalam. Kami sama-sama diselimuti rasa ingin tahu yang sama kuatnya. Dia yang menganggap kehadiran laki-laki kulit kuning di Buru ini janggal, dan aku yang baru sekali ini melihat orang Jawa selain Mamak. Aku serbu dia dengan pertanyaan tentang Jawa. Kuceritakan pula tentang Mamak yang katanya lahir di Jawa, tetapi telah berpulang beberapa bulan lalu, dan pada saat-saat terakhirnya mengharap dikuburkan di sana.
Karman tertawa kecil ketika kutanyai. Matanya menerawang, sepertinya dia tidak sabar ingin pulang. “Jawa itu pulau besar, tak seperti Buru ini,” katanya.
Aku manggut-manggut. Seperti apa, sih, pulau yang besar itu? Kupikir pulauku ini sudah cukup besar, ternyata masih ada yang lebih besar lagi. Aku memikirkan Mamak yang minta dikebumikan di Jawa. Pasti menyenangkan jika bisa bersatu dengan tanah yang luar biasa luasnya.
“Bagaimana dengan Semarang? Mamak lahir dan ingin dimakamkan di sana. Apakah kotanya cukup luas?” tanyaku. Karman membalasnya dengan anggukan.
“Kalau kau ingin memenuhi kemauan mamakmu, pergilah ke Jawa naik perahu,” ujar Karman sambil berlari mundur ketika ada seruan meneriaki namanya. Itu seruan sipir penjara, memanggil nama tahanan yang masih keluyuran meski sudah waktunya bagi mereka untuk kembali melakukan kerja paksa. Karman menambahkan di sela-sela napasnya yang terengah, “Semarang itu kota pelabuhan yang ramai.”
Begitu lama aku berpikir, hingga tak sadar Karman lenyap dari mata. Rupanya dia sudah kembali ke dalam bangunan penjara. Belum juga sempat aku melambaikan kepergiannya.
Untung kami bertemu lagi. Aku dan Karman mulai lebih akrab. Seiring dengan semakin banyaknya jumlah pertemuan rahasia kami, begitupun kemampuan berbahasa Indonesiaku semakin membaik. Sebetulnya, mustahil juga pertemuan ini disebut rahasia.
Kami bukan pasangan muda dimabuk cinta yang sembunyi-sembunyi bertemu di semak-semak. Siapapun yang berdiri cukup dekat dengan kami akan dengan mudahnya mendapati bahwa kami duduk saling membelakangi, dibatasi oleh pagar hunian tahanan di Pulau Buru, supaya kalau kami ketahuan, aku tinggal lari.
Baru juga kuketahui di kemudian hari bahwa Karman dan kawan-kawannya ini bukan tahanan biasa, mereka adalah tahanan politik. Di mataku yang saat itu masih awam dengan kemutlakan kuasa negara, sulit untuk membayangkan bagaimana seseorang bisa ditahan hanya karena berpolitik. Karman dipenjara karena ikut andil dalam PKI yang dituduh menyulut pemberontakan yang menghabisi nyawa 7 petinggi militer, walau sebetulnya dia tidak tahu-menahu tentang pemberontakan itu. Maklum, tahu apa seorang juru tulis pemula tentang pembunuhan pembesar militer? Yang Karman lakukan hanya menulis persuratan sesuai perintah, tahu-tahu saja dia ditangkap.
Mungkin karena itulah Karman tidak pandai berburu. Dia bukan pembunuh ulung. Dia tidak ditahan karena menghilangkan nyawa seseorang, tetapi karena menulis. Badannya tegap tapi tidak berguna, dia terlampau kikuk untuk membidik ayam hutan. Jemarinya yang panjang lebih sering dipakai untuk diam-diam berguru menulis pada Pak Pram, salah seorang tahanan yang lebih mahir dalam kepenulisan, dan bukannya untuk melepaskan anak panah. Walau ini bukan masalah besar baginya. Dia tetap bisa menyantap rangsum untuk makanan sehari-hari. Namun, bagiku, tanpa tangkapan unggas atau ikan harian, aku tidak akan bisa makan. Alhasil, pada hari kami berjanji untuk bertemu, tangan kami berdua selalu penuh oleh hasil buruanku. Satu dua kubawa pulang untuk dimakan bersama bapak tiriku yang sudah jompo, sisanya diperdagangkan ke kepala sipir dengan Karman sebagai perantara. Bukan apa-apa, aku hanya menjual hasil buruanku untuk mendapatkan uang. Karman memberitahuku bahwa orang tidak lagi mempertukarkan barang dan jasa dengan hasil buruan, tetapi menggunakan uang. Karenanya, aku gigih mengumpulkan uang tersebut untuk membiayai perjalananku ke Jawa demi memakamkan Mamak, meskipun Karman sempat tergelak melihatnya. Agaknya butuh ribuan hari jika hasil buruanmu hanya sebatas unggas, begitu katanya.
“Lain kali, cobalah berburu celeng. Kurasa harganya lebih mahal,” Karman terkekeh melihatku menyodorkan bangkai ayam hutan lewat celah pagar.
“Kau pikir mudah menangkap celeng seorang diri?” dengusku.
“Memang tidak. Kenapa tak minta bantuan orang lain?”
Aku terhenyak. Sudah seumur hidup dikucilkan, kukira aku sudah kebal. Rupanya aku tetap tertohok ketika tersadarkan bahwa aku memang terasingkan. Untungnya, Karman tidak menunggu jawaban, buru-buru dia memilah hasil buruanku hari ini. Iseng saja aku menyeletuk, “Karman, menurutmu mengapa Mamakku minta dimakamkan di Jawa?”
“Entahlah. Mungkin Buru bukan tempat pulang bagi beliau,” Karman mengedikkan bahu.
“Bahkan meskipun anak semata wayangnya ada di sini?” kepalaku tertunduk, tungkaiku lunglai. Aku memalingkan wajahku, takut-takut mendengar jawaban dari Karman, apapun itu.
Karman mendongak cepat ketika mendengar pertanyaanku. “Yang benar saja? Aku yakin bukan itu maksud beliau.”
Aku mengangguk lesu. Tidak dapat kumungkiri bahwa kerisauan ini sudah lama bercokol di ujung pikiranku, “Aku juga berharap demikian.”
“Jawab jujur. Memangnya kau sendiri merasa nyaman berada di Buru? Jangan menyamakan rasa nyaman dengan kebiasaan, kau juga tahu bahwa keduanya berbeda.
Siapa tahu tempatmu bukan di sini, siapa tahu mamakmu ingin mencarikanmu kenyamanan yang selama ini tak kau dapatkan. Tidak ada salahnya mencoba melancong ke Jawa, kalau memang itu yang kau hendaki.”
Aku merengut mendengar jawaban Karman. Harga diriku mencoba berontak biarpun kalah ketika pikiranku mengiyakan Karman. Alhasil, kami kembali terjebak dalam diam.
“Ngomong-ngomong, kalau nanti aku mati, apakah kau keberatan menguburkanku di Buru ini?”
Aku sudah menduga Karman akan buka suara duluan, hanya tidak menyangka dia akan menanyakan itu. Sejenak teringat tatapan mengawang Karman ketika belum lama aku menghujaninya dengan pertanyaan seputar Jawa. Sepertinya aku salah duga, barangkali tatapan itu bukan tatapan mendamba ingin pulang, justru tatapan pedih karena tak merasa rindu dengan tanah sendiri. Ibu Pertiwi pasti bercanda, bagaimana bisa ada sekian banyak anak manusia yang tercerai berai dari rumahnya?
***
Tahun ini 1972, tiga tahun berselang setelah meninggalnya Mamak. Jumlah manusia di bumi Indonesia ini sudah semakin banyak, tetapi baru sekali ini dalam 28 tahun aku hidup kulihat kerumunan manusia sebanyak ini. Kudapati diriku terkungkung di tengah lautan manusia khas kerumunan di kota pelabuhan, Semarang. Memang benar, semasa hidupnya, Mamak sering bercerita tentang betapa sibuknya Semarang. Walau ternyata, bagi seseorang yang dibesarkan di pedalaman Pulau Buru sepertiku, tempat ini masih jauh lebih bising daripada apa yang aku bayangkan. Tidak habis-habisnya aku tercengang ketika mendapati bahwa tanpa bergerak pun, bahuku tetap bersenggolan dengan bahu manusia-manusia lain yang lalu-lalang di pelabuhan. Sudah seramai ini, padahal matahari masih menyebul malu-malu di ufuk timur.
Kakiku terus melangkah hingga akhirnya menjauh dari tepi pelabuhan. Tujuanku hadir di kota ini hanya satu, yaitu mencari adik Mamak, bernama Sumarni yang lebih akrab dipanggil Marni. Menurut cerita Mamak, beliau tinggal di Kelurahan Tanjung Mas, tidak jauh dari pelabuhan. Atau semisal aku gagal menemukan beliau, paling tidak aku harus mendapati keturunan R. Projowinoto, yang menurut catatan yang diberikan Mamak, kakekku sendiri, mantan polisi pelabuhan di Semarang.
“Permisi,” ujarku seraya menghampiri sekumpulan bapak-bapak yang tengah bersenda gurau di warung kopi Pelabuhan Tanjung Mas. “Bisakah saya ditunjukkan kediaman Bapak R. Projowinoto? Beliau mantan polisi yang pernah ditempatkan di pelabuhan ini.”
Bapak-bapak tersebut mengernyitkan kening. Salah seorang di antara mereka bertanya,
“Anda siapanya? Bapak R. Projowinoto sudah meninggal sejak lama.”
Aku manggut-manggut. Masuk akal bahwa kakekku sudah meninggal karena anak sulungnya saja juga sudah. Akan tetapi, sepertinya sulit dipercaya kalau aku bilang akulah cucunya. Kujawab saja sekenanya, “Hanya kerabat.”
Mereka terlihat lebih bingung lagi. Tentunya bingung mendapati lelaki muda sepertiku, bermata sipit, berkulit kuning, tetapi mengaku berkerabat dengan R. Projowinoto, yang kuduga terlihat seperti lelaki Jawa pada umumnya.
“Kerabat?” tanya seorang dari bapak-bapak tersebut. Pandangannya tidak bersahabat.
Aku menelan ludah lalu menjawab, “Saya cucunya.”
Sontak bapak-bapak itu tak kuasa menahan raut terkejut. Seorang di antara mereka bertanya dengan salah satu alis terangkat, “Betul kamu cucunya? Siapa ibumu? Lahir dari putri yang mana kamu?”
“Mamak saya Sumaryati, Pak.” jawabku dengan sedikit terganggu.
Lebih terkejut lagi raut bapak-bapak itu. Seorang lain menanggapi, “Ya Gusti, Sumaryati yang itu? Yang sudah lama hilang itu?”
Mendengar tanggapan tersebut, sepertinya Mamak dianggap hilang oleh orang-orang di kampungnya.
“Sek digowo karo Jepang kuwi? Yang dibawa oleh Jepang itu?” Bapak-bapak itu saling bertanya dalam bahasa daerah yang tidak dapat kupahami.
Salah seorang turut menimpali. “Maryati adalah temanku di Sekolah Rakyat.”
Seorang bapak kemudian melihat ke arahku dan bertanya, “Ada bukti apa yang bisa menunjukkan kalau kamu benar anak Maryati?”
Tanganku merogoh bungkusan sederhana yang aku bawa dari Pulau Buru. Kusodorkan foto Mamak semasa gadis. Foto itu disimpan Mamak baik-baik, sebelum akhirnya diwariskan ke aku. Sambil memperhatikan bapak-bapak itu mencermati foto Mamak, aku diam-diam tersenyum. Foto itu mengingatkanku pada cerita Mamak. Kata beliau, waktu kecil, aku begitu heran melihat Mamak ada di kertas.
“Betul, ini memang Maryati,” ujar seseorang, ditanggapi dengan anggukan oleh lainnya yang ikut mencermati foto Mamak.
“Karena Bapak R. Projowinoto sudah berpulang, bisakah saya diantar ke rumah Ibu Marni?” aku menyela. Beliaulah adik kesayangan Mamak yang namanya kerap muncul dalam igauan dan yang agaknya Mamak rindukan di alam bawah sadarnya. Di saat nyawanya digerogoti malaria sekalipun, hanya Marnilah nama yang Mamak serukan.
Bapak-bapak tersebut mengangguk. Beriring-iringanlah kami menyusuri tepi jalan raya menuju kediaman Marni.
Ke rumah kayu yang kokoh itulah aku diantarkan oleh bapak-bapak warung kopi. Kulihat lalu-lalang manusia yang sibuk menjemur dan mencelup kain di halamannya. Kain panjang bercorak berukuran besar-besar digantung di tali-tali yang melintang disangga tongkat, warna dan coraknya yang beragam mengingatkanku pada cerita Mamak akan indahnya kain yang bernama batik. Para wanita di sini terlihat masih menggunakannya, walau tidak sedikit juga yang tidak.
Aku menunggu di ambang gerbang sementara para bapak memasuki halaman rumah dan menemui seorang perempuan tak jauh dari pintu utama. Mereka berbincang, samar-samar kudengar mereka menyebut nama Mamak dan Marni. Salah satu bapak berseru menyuruhku mendekat, mengenalkanku kepada perempuan berkebaya dan berkain batik yang sedari tadi mereka ajak bicara. “Marni, ini dia. Anak muda yang mengaku putranya Maryati.”
Pandanganku bertumpu ke sepasang mata milik Marni, bibiku. Marni mirip sekali dengan Mamak, walau Mamak lebih kurus dan kumal sedangkan Bibi Marni nampak molek. Awalnya aku tangkap raut curiga ketika dia melihat ke arahku dengan raut tidak percaya, keningnya mengernyit dan mulutnya sedikit terbuka. Lalu kutangkap pula raut haru ketika lamat-lamat dia melihatku. Dihampirinya aku, dilihatinya aku dan semakin kentara raut harunya melihatku.
“Siapa namamu, Nak?” tanya Marni.
“Man Beta, Bibi.”
Marni, yang tampak terhenyak, mengatupkan tangannya di mulut. Sebelum bertanya lebih lanjut, tak lupa dia mengucap terima kasih kepada para bapak yang mengantarkanku.
“Matur nuwun, terima kasih,” begitu ucapnya, lantas dibalas oleh bungkuk hormat dari para bapak yang izin pamit.
Sepeninggal para bapak, Marni mengajakku untuk masuk dan duduk berhadapan di meja ruang tamu. Dia memperhatikan garis wajahku lebih seksama sambil bergumam, “Walau sipit begini, begitu mirip kamu dengan Mbakyuku, Maryati.” Senyum tipis merekah di bibirnya, air mukanya penuh haru. “Bagaimana kabarnya sekarang? Apakah dia baik-baik saja? Bisakah aku bertemu dengannya?”
Aku menggeleng, “Mamak sudah meninggal sejak lama. Sakit malaria, tak tertolong.”
Marni terkejut, lalu menengadahkan kepala. “Gusti, belum juga aku sempat bertemu lagi dengan Mamakmu. Rupanya dia sudah tenang di atas sana, cepat sekali dia berpulang.”
Sorot mata Marni meredup, bahunya terkulai lemas.
Aku tersenyum getir, menunjukkan belas kasihku.
Suasana hening sejenak, Marni masih berusaha melumat kabar duka. Sementara, aku tidak enak mengusiknya. Tidak terbayang seperti apa rasanya dipisahkan berpuluh tahun hanya untuk mendengar kabar bahwa yang tercinta sudah tiada.
“Jadi, selama ini dimana kau tinggal? Di mana Mbakyuku tinggal?” tanya Marni.
“Di Pulau Buru, Bibi. Pulau kecil di timur sana, jauh dari Jawa.”
“Astaga, jadi para Jepang itu membawa Mbakyu jauh ke sana? Ke pulau terpencil?
Bahkan aku tak tahu ada pulau bernama itu di timur.” Marni menghela napas untuk kesekian kalinya, tatapannya merana seakan penuh penyesalan karena tidak dapat mengelakkan takdir yang tidak mengenakkan.
“Ya, Bibi,” jawabku dengan sendu.
“Jangan bilang, kau anak dari Jepang itu?”
“Benar, Bibi.”
Marni mengusap wajahnya gusar. “Astaga, tak kusangka. Ternyata Mbakyuku sendiri yang jadi korban tentara Jepang. Sungguh kasihan, padahal Bapak bilang Mbakyu akan disekolahkan.” Tatapannya yang tadinya merana kini berkilat-kilat penuh kebencian, agaknya Marni tersakiti karena dikhianati.
“Betul, Bibi.”
“Ada maksud apa kau kemari?” Kata-katanya lugas, tetapi memancarkan kehangatan.
Aku mengeluarkan kantong istimewa dari dalam buntel kadutku. “Aku hendak menguburkan Mamak.”
Gemeletak bunyinya ketika kantong tersebut kuletakkan di atas meja. Rasanya seakan tapak kaki Mamak kembali mengetuk bumi ini.
***
Tidak butuh waktu lama bagi Marni untuk segera menghubungi adik laki-lakinya dan memanggil pemuka agama setempat ke rumahnya. Langsung dipastikan bahwa Mamak akan dimakamkan sekarang ini juga di pemakaman keluarga. Kantong berisi Mamak sudah diambil alih oleh Marni dan adiknya, aku hanya terbengong-bengong hingga Marni menyerukan namaku untuk ikut bergegas. Di tengah huru-hara pemakaman sekalipun, masih kudapati adik Marni mendelik ke arahku sembari bertanya ke kakaknya, “Berarti, sekarang tanah warisan Bapak akan dibagi tiga?” Marni hanya mendesis menyuruh adiknya diam.
Perjalanan dari rumah Marni menuju tempat kuburan terasa begitu panjang. Kakiku berat melangkah, walau pikiranku berulang kali meyakinkan diri bahwa inilah yang Mamak mau.
Aku tidak kuasa menahan nuraniku untuk tidak mengenang Mamak. Berkali-kali ku camkan bahwa kepulangannya tidak sama dengan kehilangannya, bahwa dia tetap bersamaku.
Mamakku, Mamakku yang manis. Yang kini tinggal belulang.
Mamakku yang ku pertanyakan. Mamakku yang entah dimana, tapi orang bilang dia sudah tenang di atas sana. Di atas yang mana?
Mamakku yang kupertanyakan. Katanya harus dimandikan, biarpun hanya tinggal belulang. Padahal di Buru sana, aku yang mengais kuburannya dengan hati-hati, mengelapi sisa-sisanya tiap hari menjelang keberangkatanku ke Jawa. Apakah masih tidak cukup bersih?
Mamakku yang kupertanyakan. Kata pemuka agama harus didoakan dengan salat, padahal aku tak tahu Mamak punya agama. Padahal aku sendiri pun tak punya.
Mamakku, Mamakku.
Yang dikebumikan dengan tata aturan yang bahkan aku tidak mengerti. Dibungkus kain, didoakan dengan rapalan doa yang berbeda dengan yang dibacakan tetua adat di Pulau Buru. Liang lahatnya digali dengan pacul, berlainan dengan kuburnya di Pulau Buru dulu yang hanya boleh digali dengan kayu. Salah satu kebaya kesayangannya tidak boleh ikut dikuburkan, bertolak belakang dengan di Pulau Buru. Tidak mengapa.
Yang dikuburkan diiringi dengan pertengkaran adik-adiknya mengenai warisan kakek, soal apakah aku yang anak orang asing ini patut mendapatkannya atau tidak. Soal adik Marni yang tidak terima ketika kakaknya berniat menyisakan warisan untukku, walaupun aku sendiri tidak menginginkannya. “Untuk apa memberikan warisan kepada seseorang yang tidak mengharapkannya? Tidak ada guna!” begitu seru adik Marni ketika menentang kakaknya. Tidak mengapa.
Yang disemayamkan tanpa aku ikut serta di dalamnya.
Ketika liang lahat sudah digali, tanah merah sudah menganga, wajah-wajah asing mengelilingi liang. Tukang kubur sudah membawa seonggok kain putih berisi Mamak, walau sudah bukan Mamak yang kubungkus dengan kantong anyaman. Saat itulah aku menjerit.
Susah payah aku katakan pada tukang kubur untuk serahkan Mamak padaku. Tak ada yang mengerti raunganku meminta Mamak. Wajah-wajah itu menatapku keheranan. Tidak sedikit pula yang risih melihat lelaki dewasa menangis meraung di pekuburan.
Barulah ketika Marni menyerahkan Mamak kepadaku, aku terdiam.
Wajah-wajah itu seakan diberi jawaban atas keheranannya.
Angin bertiup hening, kicau burung terdengar samar di kejauhan.
Selamat berpulang, Mamak. Setelah penantian panjang, berlabuhlah engkau dalam kedamaian tiada ujung. Putramu ini telah semayamkan engkau.
Mengapa.
*****