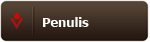Senja Di Batavia
Batavia, 12 Oktober 1740.
Dari jendela kamarnya, Sari melihat burung-burung bangau melayang berputar tinggi di angkasa. Lengkingan mereka mengiringi nyaringnya pekik-pekik ketakutan di bawahnya. Hamburan warna merah bersemu jingga di langit seakan menggambarkan api yang tidak berhenti berkobar.
Lima hari setelah Nyonya Carolien, majikannya, menitahkannya untuk pulang ke rumah sampai waktu yang tidak ditentukan, Sari melewatkan waktunya berdiam diri di rumah berkawan dengan kebisingan-kebisingan yang mulai memekakkan telinganya.
Teriakan amarah yang dilontarkan dalam bahasa Melayu dan bahasa Belanda, serta teriakan ketakutan yang dilontarkan dalam bahasa Cina saling bersahutan memenuhi udara. Suara pedang yang mengayun membelah angin serta suara bubuk mesiu yang melontarkan peluru tidak henti-hentinya mengalun bersama teriakan-teriakan itu.
Seperti kata Nyonya Carolien, orang Cina sedang dibantai habis-habisan di luar sana. Dia juga menceritakan kalau mereka membuat rusuh dengan membunuh lima puluh orang Belanda.
Sekarang pikiran Sari melayang pada Xiao Li, sahabat baiknya. “Ah, Xiao Li. Di mana kamu sekarang?” gumamnya.
***
Sari baru beberapa minggu bekerja untuk Nyonya Carolien saat dia bertemu dengan Xiao Li tahun lalu. Gadis limabelas tahun seperti Sari seharusnya sudah dipinang. Tapi, tidak ada yang mau dengan seorang gadis berbibir sumbing. Dia pun tidak bisa mendapatkan pekerjaan sampai pada suatu hari tetangganya, yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di tangsi Belanda, menawarinya pekerjaan di rumah Tuan Willem, seorang perwira tinggi militer Belanda, untuk melayani Nyonya Carolien, istrinya.
Nyonya Carolien suka mengumpulkan kain-kain sutera. Menurutnya, kain-kain sutera membuat kecantikannya makin menonjol.
Setiap hari Sabtu, setelah Nyonya Carolien menghabiskan sarapan paginya, Sari menemani Nyonya Carolien ke Pasar Tanah Abang.
Toko kain yang dimiliki keluarga Xiao Li terletak di bagian timur pasar, dekat toko-toko kelontong. Tokonya agak sepi hari itu. Selain Sari, hanya ada seorang perempuan Cina bertubuh tambun, dan Nyonya Carolien bersama temannya.
Sari melihat-lihat potongan sisa kain di sebelah pintu masuk dekat tempat membayar, sambil menunggu majikan dan temannya berbelanja. Pemilik toko sedang mengembalikan uang kepada seorang perempuan Cina yang menggendong anak bayi. Dilihatnya juga seorang anak laki-laki yang dengan sigapnya mengangkat segulung kain yang dibeli perempuan itu ke kereta kuda yang menunggu di depan toko.
Mereka sedang berjalan menuju pintu toko saat Sari mendengar suara ‘tuk’ pelan. Dilihatnya satu mata uang perak menggelinding di ubin keramik yang mengkilap. Jika uang itu tidak berada di dalam dompet yang punya, siapa pun dapat memungutnya, bukan? begitu pikir Sari. Maka dia beranjak untuk mengambil uang itu sembari berpikir akan ditukarkan dengan barang apa nantinya.
Baru saja dia mendekatinya, anak laki-laki yang mengangkut kain tadi sudah memungut uang perak yang tak bertuan itu. Namun, anak itu tidak memasukkan uang logam itu ke dalam saku celana pendek putihnya. Dari ambang pintu Sari melihat dia berlari kecil menuju dan memberikannya kepada perempuan itu.
Sari kembali masuk ke dalam toko. Dia bersandar pada salah satu lemari kaca di bagian belakang toko dan memperhatikan anak itu kembali berjalan masuk lalu duduk di atas kursi tinggi dekat tempat membayar. Anak laki-laki itu mengusap peluh yang mengalir dari dahinya dengan selembar handuk yang dikalungkan di lehernya. Pipinya merah seperti buah tomat yang diiris-iris Sari saat membuat roti berlapis untuk Nyonya Carolien.
Sari mengalihkan pandangannya dengan cepat pada kain merah di depannya saat mata sipit anak laki-laki itu bertemu matanya. Hawa panas menjalar ke sekujur tubuhnya ketika dari sudut matanya dia melihat anak itu turun dari kursi tinggi dan berjalan mendekatinya.
“Hai,” ujar anak laki-laki itu.
Sari mengerjapkan matanya dan memandang anak itu dengan aneh dan takjub. Tidak banyak orang yang mau berbicara dengannya. Sari tahu ada orang yang percaya bahwa wajahnya yang cacat bisa mendatangkan petaka kalau dipandang terlalu lama. Anak laki-laki Cina itu adalah lelaki pertama di luar keluarganya yang mengajaknya bicara.
“Xiao Li,” ujarnya lagi, memperkenalkan diri. Lalu melanjutkan, “Namamu siapa?”
“Sari,” jawabnya dengan malu-malu.
“Sali,” katanya sambil menganggukkan kepalanya.
Sari tersenyum. Orang Cina memang tidak bisa mengucapkan ‘r’.
***
Setelah hari perkenalan itu, Sari dan Xiao Li sering menghabiskan waktu bersama. Sore hari saat Nyonya Carolien menghabiskan waktunya untuk minum teh bersama dengan teman-temannya dan saat Xiao Li bebas dari tugas membantu ayahnya, Sari dan Xiao Li berjalan bersama ke tepi Kali Besar untuk melihat senja.
Xiao Li bercerita bahwa orang Cina di Batavia tidak enak-enak amat hidupnya. Ada pemberlakuan wajib lapor bagi setiap orang Cina yang berdiam di Batavia. Orang Cina yang banyak uang sering diperas oleh orang Belanda. Beberapa teman Xiao Li yang hanya memiliki dua potong baju, hitam dan biru, dipindah paksa ke Ceylon. Apakah mereka selamat tiba di Ceylon tidak ada yang tahu. Ada desas-desus mereka dibuang ke laut.
Kata Xiao Li, banyak orang Cina yang tidak mampu dan masih tinggal di Batavia sekarang menjadi buruh di pabrik gula Belanda. Namun, belakangan ini banyak dari mereka yang diberhentikan secara paksa karena harga gula yang terus turun. Nampaknya banyak orang Cina yang geram dengan sikap semena-mena orang Belanda dan berniat memberontak.
Sari teringat bahwa pada pertemuan terakhir mereka, Xiao Li bercerita kalau orang Cina akan menyerang orang Belanda dalam waktu dekat. Dia mencuri dengar dari teman ayahnya yang datang malam-malam untuk mengajaknya ikut serta. Ayahnya tentu menolak mentah-mentah ajakan itu karena dia tidak memiliki masalah dengan orang Belanda. Sejak saat itu Xiao Li tahu bahwa Batavia mulai tidak aman.
Pada penghujung hari itu, Xiao Li mengambil selembar kain sutra merah dari saku celananya. Kain tipis dan licin itu dengan lembut dibalutkannya melingkari bahu Sari. “Simpanlah kain ini sebagai cendera mata persahabatan kita. Sebagai tanda perasaanku padamu.” Kecupannya, yang ringan dan cepat, ditempatkan di dahi Sari. Lalu dia melangkah pergi, menjauh. Hilang.
***
Kenangan Sari buyar saat Emak memanggilnya untuk membantu menyeduh kopi buat Bapak dan Mas Ario, kakaknya. Di ruang tamu, Bapak dan Mas Ario sedang menggerutu. Mereka tidak mendapat upah karena pengawas ladang gula melarang mereka menggarap ladang dalam beberapa hari ini.
“Kawan-kawanku pergi ke kota untuk mengambil harta orang-orang Cina serakah itu. Aku mau ikut besok daripada berdiam di rumah,” ujar Mas Ario.
“Ah, kaki Bapak sakit. Kamu saja yang pergi. Bawa pulang barang yang banyak. Katanya mereka punya guci bagus. Semoga tidak rusak kena tembakan meriam, agar kita bisa jual lagi. Enak saja mereka bisa kaya sementara kita terus-terusan miskin,” omel Bapak.
“Ambil yang banyak ya, Nak,” sambung Emak. “Emak dengar kemarin kalau orang-orang Cina mau menjadikan kita budak. Kalau tidak mau, kita yang akan dibunuh seperti yang mereka alami sekarang. Nah, tahu rasa mereka kini yang dibantai.”
Sari mengantarkan kopi ke ruang tamu dan meletakkannya di atas meja. Dengan takut-takut dia duduk di sebelah Emak sembari memandang Bapak dan Mas Ario yang menyeruput kopi. Dengan suara gemetar Sari berkata, “Kenapa kalian begitu benci dengan orang Cina?” Bukankah mereka tidak pernah bikin ribut dengan kita?” Tiga pasang mata seketika melihat ke arah Sari, mata-mata yang menghakimi.
“Kamu ini perempuan tahu apa,” bentak Bapak. “Mereka menguasai pusat kota. Merampas milik kita. Kamu lupa dulu kita pengusaha pabrik gula? Meskipun kecil, itu milik kita. Mereka punya banyak uang, melibas kita hingga tertinggal di pinggiran. Kurang serakah apa mereka?”
“Tapi kan—”
“Hus. Kamu sekarang berani membantah bapakmu?” potong Emak, nadanya meninggi.
Sari tidak ada maksud untuk membantah Bapak. Dia memahami perasaan ayahnya yang terluka karena perusahaannya dicaplok orang Cina sehingga dia bersama Mas Ario sekarang terpaksa menjadi buruh di lahan tebu. Sari hanya ingin bilang bahwa orang Cina itu juga ada yang baik dan tidak bisa semuanya disalahkan sebagai penyebab keadaan keluarga mereka sekarang ini. Belum sempat dia kembali berusaha menyampaikan maksudnya, pintu rumah diketuk.
Emak bergegas membuka pintu dan mendapati pengawas kebun tebu dan dua tentara Belanda berdiri di depan rumah.
“Selamat sore, Bapak-Ibu sekalian,” ujar pengawas kebun tebu berbasa-basi. “Saya membawa pengumuman bahwa Belanda menawarkan dua dukat untuk setiap kepala orang Cina.”
Bapak dan Mas Ario segera bangkit dari tempat duduk untuk mendengarkan lebih lanjut pengumuman itu.
Sari terdiam mendengar pengumuman itu.
“Ini tidak benar,” gumam Sari dengan kesal setelah pengawas kebun tebu dan dua tentara Belanda itu pergi. Belum pernah dia melihat mata Bapak, Emak, dan Mas Ario begitu berbinar-binar.
Bapak mengambil golok sedangkan Mas Ario membawa cangkul.
Sari mencengkeram tangan Mas Ario dan berusaha menahannya keluar dari rumah.
Emak menariknya.
“Kamu ini perempuan banyak tingkah. Duduk diam sana,” bentak Bapak.
Emak memaksa Sari duduk di kursi walaupun dia terus meronta.
Malam itu Bapak dan Mas Ario tidak pulang.
***
Setiap langkah kaki Sari lengket berkecipak karena genangan-genangan darah yang membasahi tanah. Warnanya lebih merah dari senja. Merah pekat. Lebih pekat dari dinding merah di rumah Nyonya Carolien. Kali Besar yang mengalir di antara jalan setapak dan sawah berubah warna – memerah. Tubuh Sari bergetar hebat sembari melangkahi mayat orang-orang itu. Air matanya mengalir semakin deras ketika dia melihat bayi yang sudah tidak bernapas dalam dekapan mayat emaknya.
Serdadu-serdadu Belanda menusukkan bayonet pada siapa pun yang tergeletak di tanah. Tidak ada erangan. Tidak ada jerit kesakitan. Anak-anak kecil itu bukannya terbunuh, namun sengaja dibunuh. Membayangkan anak-anak itu berlarian ke tengah jalan kemudian ditembak dikepalanya dan mereka yang ditemukan bersembunyi di dekat semak-semak dan ditusuk tepat di jantungnya, membuat Sari mual. Dia membungkuk dan muntah.
Langit menyisakan sedikit sinar terangnya. Di perkampungan seberang, tempat Xiao Li dan keluarganya tinggal, lebih banyak lagi orang-orang Cina yang bergelimpangan di tanah tanpa nyawa. Beberapa orang setempat, kenalan Bapak dan Mas Ario, serta serdadu-serdadu Belanda memandang Sari dengan tatapan penuh selidik. Sebagian dari mereka keluar-masuk rumah membawa barang-barang yang ada di rumah itu. Sebagian lagi membakar rumah dan yang lainnya menusuki setiap orang yang tergeletak di tanah.
“Heh! Sedang apa kamu di sini?”
Sari terkejut mendengar suara Mas Ario memanggilnya di depan teras rumah seseorang sembari membawa piring keramik dan sendok perak. Baju dan tubuhnya dipenuhi bercak darah.
“A… aku mencarimu dan Bapak. Kami di rumah khawatir,” sahut Sari agak gemetar. Dia berharap kebohongannya tidak diketahui kakaknya.
Mas Ario memandang adiknya dengan sorot mata marah. Dia kembali masuk ke dalam rumah itu lalu keluar dengan mengusung barang-barang lainnya.
Petang itu, pada saat Sari kembali ke rumah bersama Bapak dan Mas Ario yang membawa barang-barang untuk Emak, perkampungan itu telah hangus tidak berbekas oleh lautan api.
Sembari mengekor Bapak dan Mas Ario, Sari akhirnya tak tahan dan berteriak, “Mengapa semuanya harus dibunuh, Mas? Mengapa?” Air mata mengalir membasahi pipinya
“Mereka punya salah apa sama Mas? Kenapa anak-anak juga dibunuh? Anak-anak, Mas. Anak-anak,” Sari tersedu.
“Membersihkan hama akan lebih bagus bila hingga akar-akarnya karena mereka tidak akan pernah tumbuh lagi. Biarkan ini menjadi pelajaran bagi mereka agar tidak lagi macam-macam sama kita,” bentak Ario tanpa menoleh. Dia mempercepat langkahnya dan meninggalkan Sari di tengah-tengah segala kekacauan itu.
Pada malam itu, Sari sama sekali tidak bisa memejamkan mata.
***
Pada Sabtu, 22 Oktober 1740, Gubernur Jendral Belanda Adriaan Valckenier mengeluarkan perintah untuk menghentikan pembunuhan terhadap orang Cina.
Seminggu setelahnya, seorang tentara Belanda mengetuk pintu rumah Sari. Katanya, dia diutus Nyonya Carolien menjemput Sari untuk kembali bekerja.
Dengan baju yang dibungkus selembar sarung, Sari berjalan di belakang tentara itu menuju rumah Nyonya Carolien.
Bau tajam besi di udara telah hilang. Tanah tidak lagi basah oleh darah. Tidak ada lagi mayat bergelimpangan di jalan.
Nyonya Carolien menyapa Sari dengan ramah. Dengan lembut dia meminta Sari mengerjakan tugas sehari-harinya namun dia tidak pernah lagi mengajak Sari belanja di Pasar Tanah Abang.
Pada sore hari, di waktu istirahat sebelum dia harus menyajikan makan malam untuk Tuan Willem dan Nyonya Carolien, Sari pergi menatap senja di bawah pohon waru di tepi Kali Besar. Di situ dia biasanya menatap senja bersama Xiao Li. Sari memejamkan mata menahan perih. Merahnya matahari yang sedang terbenam itu mengingatkannya pada api yang berkobar, darah yang mengalir, teriakan-teriakan ketakutan, dan Xiao Li. Sejak Minggu, 9 Oktober 1740 itu, waktu kejadian Geger Pecinan dimulai, sejak dia kehilangan Xiao Li, senja tidak lagi sama. Senja hanya suatu luka yang menghampakan jiwa.
Sari bersandar di batang pohon waru. Dia mengeluarkan kain sutra merah dari balik angkinnya. Pelan-pelan kain itu dia balutkan di bahunya. Xiao Li. Sari mengusap bahu dan lengannya. Dia yakin, suatu hari nanti, entah kapan, dia akan berada kembali dekat di samping Xiao Li.
*****