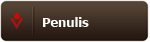Topeng Nalar
Dewi Ria Utari lahir di Jepara, 15 Agustus 1977. Mulai menulis cerita pendek sejak tahun 2003. Karyanya telah diterbitkan di Djakarta, A+, Spice, Media Indonesia, Koran Tempo, dan Kompas selain juga dalam kumpulan cerpen seperti Ripin: Cerpen Pilihan Kompas 2005-2006, Pena Kencana Literary Award 2008, and Cinta di atas Perahu Cadik: Cerpen Pilihan Kompas 2007. Novelnya, Rumah Hujan diterbitkan oleh Gramedia tahun 2016. Dewi tinggal di Jakarta dan sekarang bekerja sebagai Penyunting Utama di Majalah Seni dan Gaya Hidup Sarasvati. Dewi bisa dihubungi di dewiriautari@gmail.com.
Hak cipta ©2017 ada pada Dewi Ria Utari. Terbit atas izin dari penulis. Hak cipta terjemahan ©2017 ada pada Femmy Syahrani.
Topeng Nalar
Sudah tiga hari Nalar demam. Biasanya demamnya cepat hilang begitu dikompres air atau keningnya ditempeli irisan bawang merah. Kemarin neneknya sudah membawa dia ke Mak Moyong—dukun anak. Kata si dukun kena sawan. Tapi demamnya tak juga turun ketika ia dipaksa neneknya minum jamu dari Mak Moyong.
Kalau sore ini aku dapat gaji mingguan, Nalar akan langsung kubawa ke Dokter Kiki. Puskesmas sudah tutup saat aku bubaran pabrik. Tidak tega aku jika menunggu sampai besok. Demam Nalar begitu tinggi. Lagi pula penyebabnya aku sendiri. Sebagai ibu dan penyebab sakitnya, aku harus bertanggung jawab. Apalagi sudah setahun ini hubunganku dan Nalar tak begitu hangat.
Penyebabnya, ketika setahun lalu, ia melihat aku nopeng dengan Ibu di kampung, Nalar memaksaku untuk mengajarinya nopeng. Aku menolak. Sudah cukup rasanya garis keturunan penari topeng berhenti di tubuhku. Lagi pula tanggapan nopeng sudah tidak sebanyak dulu saat aku remaja. Sejak tak banyak tawaran nari, aku memutuskan jadi buruh rokok. Pemasukan sehari-hari meski sedikit ternyata lebih mampu menyambung hidup kami berempat: aku, ibu, Danu dan Nalar.
Selain soal penghasilan, aku tidak tega jika membiarkan Nalar melalui sejumlah persyaratan yang harus kujalani dulu. Puasa mutih, yang hanya makan nasi putih, dan ngrowot, yang hanya makan umbi-umbian, Senin-Kamis, belum lagi dalam waktu-waktu tertentu harus tidur di lantai tanpa alas, hingga tapa kungkum, bersemedi dengan berendam. Aku menjalaninya karena tidak ada pilihan lain. Bukannya aku tidak suka menari. Namun, aku harus tau diri. Rumah ini sudah kehilangan para lelakinya. Baik ayahku maupun suamiku. Mereka ditakdirkan meninggal mendahului para istrinya. Sungguh tak mungkin jika menjadikan ibuku di usia larutnya harus ikut mencari uang. Cukuplah aku.
Melihat keadaan ini, wajar rasanya jika aku tak menginginkan Nalar menjadi penari topeng. Seperti anak-anak lainnya, aku ingin ia sekolah sampai semampuku membiayainya. Setelah lulus, ia bisa kerja di pabrik, penjaga toko, atau penjual barang.
Harapanku pupus ketika tiga bulan lalu, Nalar diajak ibu mengunjungi makam Mbah Buyut di Desa Gabusan. Dua jam perjalanan naik bus. Sepulang dari sana, Nalar langsung ke kamar penyimpanan topeng dan mengobrak-abrik topeng-topeng yang sudah kusimpan rapi. Di depanku, ia langsung memasang sampur yang dibelitkan di pinggang dan memasang topeng di wajahnya dengan cara digigit. Saat kutanya, ibuku membantah telah mengajarinya menari. Nalar sendiri tak mengatakan apa pun. Ia hanya menari menandak-nandak dan baru terdiam saat kucopot paksa topeng di wajahnya.
Bukannya meredam keinginan Nalar, ibuku malah semakin bersemangat mengajari Nalar menari. Dengan sisa gamelan di rumah, Ibu mengiringi Nalar menari. Bocah itu paling suka gerakan lerep, gerakan mengelus dua jumbai di kiri dan kanan topeng, sambil mengentakkan kaki ke tanah. Jika hanya menari, sebenarnya aku tak terlalu kesal. Aku hanya tak suka ketika Ibu mulai mengajari berbagai tirakat yang pernah diajarkannya kepadaku saat seusia Nalar. Anak itu sudah terlalu kurus untuk ikut-ikutan puasa dan sejenisnya. Sebagai ibunya, aku malu jika Nalar dianggap kurang gizi. Ditaruh ke mana mukaku. Seolah aku tidak cukup memberinya makan.
Inilah kenapa aku tak suka berharap. Berkali-kali aku dikhianati harapan. Aku berharap Nalar bisa kerja di pabrik, penjaga toko, atau penjual barang. Setidaknya dengan tetap menjadi buruh nglinting rokok, aku bisa membiayainya sampai SMA. Memang ia baru tujuh tahun. Masih bisa ia berubah mengikuti harapanku. Tapi sekali lagi, aku benci berharap. Sangat membencinya ketika ayahku meninggal karena malaria, dan suamiku tak pernah pulang sejak pamit melaut tiga tahun silam.
Hanya tersisa satu lelaki di keluarga kami. Danu, kakak Nalar yang sekarang sudah kelas enam SD. Seharusnya aku seperti kebanyakan keluarga lainnya di kampungku, yang menaruh harapan ke anak lelakinya. Tapi bagiku, Danu tidak bisa diharapkan. Aku tidak bisa memercayai anak yang kulahirkan tanpa kutahu siapa ayahnya.
Mungkin karena aku tak menerima kehadirannya, Danu juga tak memedulikan kehadiranku. Ia lebih peduli pada Nalar. Baginya, Nalar lebih dari sekadar adik seibu. Nalar seolah dolanan yang tak pernah kubelikan sejak ia bisa merengek. Dolanan yang bisa membalas setiap sentuhan dan perhatiannya.
Sejak Nalar belajar menari, Danu tak lagi sering menghabiskan waktu dengan bocah-bocah lelaki yang kerap nongkrong di warung kopi Pak Gatot. Dulu, ia kupergoki terbatuk-batuk saat mengisap rokok pemberian anak-anak itu. Begitu aku lewat di depan warung, ia langsung klepas klepus berlebihan sambil duduk menekuk salah satu kakinya seperti gaya sopir truk yang suka mangkal di warung itu.
Belakangan ini, Danu lebih suka menunggui Nalar belajar joget. Ia menonton sambil menatah kayu randu untuk membuat topeng. Aku tak tahu dari siapa ia belajar. Pasti hanya coba-coba. Dari yang semula hasilnya topeng peyot Danu mulai bisa menatahnya seukuran wajah Nalar.
Sebenarnya aku senang, Danu jadi tak banyak nongkrong di warung. Tapi tetap saja aku memiliki banyak celah untuk memarahinya. Apalagi jika aku pulang dari pabrik dalam keadaan lelah teramat sangat. Teras rumah penuh serpihan kayu, menjadi benda yang cocok sekali untuk kuraup dan kulemparkan ke wajahnya. Sambil kelilipan, biasanya Danu hanya menyimpan marah dan mengambil sapu lidi. Nalar hanya bisa menangis.
Kemarahanku pada Danu semakin memuncak dengan sakitnya Nalar. Gara-garanya empat hari lalu ketika aku mendapat tanggapan nari di kampung sebelah. Juragan beras desa sebelah menang jadi lurah. Aku diminta nari tayub dengan Yu Wasis. Ibu sebenarnya sudah tidak setuju aku tayuban. Lebih baik nopeng saja. Katanya, nopeng lebih terhormat ketimbang nayub. Aku sudah persetan dengan alasan itu. Yang penting ada uang beli beras.
Ternyata Nalar mencariku. Rupanya ia dengar dari Danu bahwa aku dapat tanggapan nari dan ia merajuk ingin menonton. Kemudian Danu berhasil meyakinkan mbahnya jika ia bisa menjaga Nalar. Akhirnya mereka menyusulku.
Tiba-tiba aku melihat mereka diantara penonton. Namun perhatianku lebih tersita ke berapa banyak lelaki berwajah berahi yang bisa kukalungi sampur. Mereka jelas-jelas lebih royal menyisipkan uang kertas ke dalam kembenku. Semakin malam, aku tak cukup puas dengan puluhan tangan yang merogoh dadaku. Juragan beras yang punya gawe konon penggemar rahasiaku. Dia pasti bakal nyangoni aku duit berlembar-lembar jika bisa mengajaknya tidur. Sayangnya, niatku gagal ketika menjelang tengah malam, kulihat Nalar dan Danu berdiri termangu di deretan belakang penonton. Aku baru menyadari kehadiran mereka ketika hanya tinggal puluhan lelaki dewasa. Garis genit di bibirku mendadak wagu begitu melihat wajah pasi Nalar. Ia terlihat mimbik-mimbik tepat saat Kang Jono menyusup belahan dadaku. Aku langsung berlari turun dari panggung. Kuseret kedua anakku menjauh dari tempat itu. Biarlah malam itu menjadi rezeki Yu Wasis.
Sepanjang jalan pulang, kugelandang kedua anakku dengan perasaan kisruh. Di gendonganku, Nalar terus membenamkan wajahnya di cerukan dua buah dadaku. Sementara Danu tak mengeluarkan suara apa pun. Hanya bunyi srak-sruk kedua kaki telanjangnya yang bergegas mengikuti langkah kakiku.
Begitu sampai rumah, aku langsung masuk kamar dan membaringkan Nalar yang ternyata sudah tertidur. Setelah itu, aku keluar dan menarik tangan Danu yang sedari tadi berdiri mematung di ruang tengah. Tak kupedulikan teriakan ibuku yang sibuk bertanya, “Ono opo tho iki,” sambil membenahi rambutnya yang acak-acakan selepas tidur. Aku menuju kamar penyimpanan topeng. Setengah kudorong Danu ke dalamnya. Tak kupedulikan tangisnya. Tanpa mengeluarkan sepatah kata pun, aku mengunci pintu. Masih sempat kudengar isak Danu dari dalam.
Paginya, aku terbangun oleh igauan Nalar dan panas keningnya yang menyengat ketiakku. ”Mas Danu. Mas Danu,” igaunya sambil merem. Lirih suaranya memanggil kakaknya membuatku beranjak dari kasur. Niatku untuk terus mengurung Danu kubatalkan. Setidaknya, jika merasakan kehadiran Danu, Nalar agak tenang.
Tak kutemukan Danu di kamar hukuman. Kudapati selot pintu pengunci tak lagi terpasang. Ibu pasti melepaskannya tadi pagi. Tapi saat kutanya, ia menyanggah. ”Tadi pagi saat bangun, pintunya sudah seperti itu,” ujar Ibu sambil memarut kelapa. Sejak saat itu, tak lagi kudapati Danu pulang.
Suhu badan Nalar sering naik turun sejak kepergian Danu. Sudah beberapa kali kubawa ke puskesmas dan dokter yang harganya lebih mahal, mereka tidak menemukan penyebab pastinya. Bermacam obat, baik yang resmi maupun jejamuan, telah dicoba. Namun, hasilnya tetap sama saja. Nalar hanya terlihat anteng dan membaik keadaannya setiap kali menggenggam topeng yang dibuatkan Danu untuknya.
Sejak Nalar sakit-sakitan, keuanganku makin memprihatinkan. Apalagi pabrik tutup untuk sementara. Beberapa teman mengabarkan perusahaan rokok keluarga yang sudah berdiri sejak 50 tahun ini akan dijual. Tanggapan tayub pun mulai berkurang. Untunglah Pak Saidi, penabuh gamelan yang sering mengiringi aku nari, mengabarkan ada acara pengumpulan rakyat yang menginginkan tari topeng.
”Kok bukan tayub Pak?” tanyaku.
”Tayub memang lebih ramai. Tapi pemimpinnya ini katanya pengen pengisi acaranya sopan. Terus karena acaranya soal apa sih itu namanya, kepedulian pada seni bangsa sendiri, makanya mereka ngumpulin beberapa kelompok seni di daerah ini,” kata Pak Saidi.
”Tapi yang dipilih yang sopan. Itu namanya enggak adil,” sanggahku.
”Ndak ngerti lah aku. Manut aja. Terus mereka minta topengnya dicat ijo semua, biar katanya peduli lingkungan.”
”Piye tho, katanya tadi peduli kesenian. Terus sekarang peduli lingkungan.”
“Yah, namanya juga ngumpulin orang biar kepilih. Apa saja biar ketok apik tho,” tukas Pak Saidi.
Tak kupedulikan tangisan Nalar yang tidak mau topeng-topeng di rumah menjadi hijau. Hanya satu topeng yang tak kuganti warnanya. Topeng seukuran wajahnya yang dibuatkan Danu untuknya. Aku tak mau nantinya panasnya naik lagi di saat aku menari. Setidaknya setelah aku mendapat uang bayaran pentas, ia bisa kubawa ke dokter di kota.
Sore itu kuwanti-wanti ibu untuk menjaga Nalar di rumah. Sejak demam, aku memang tak pernah berani meninggalkannya cukup lama. Nalar masih ngambek saat aku pamitan. Ia menolak kucium pipinya. Bahkan, Nalar tak mau melihatku. Diselusupkan kepalanya di antara kaki mbahnya.
Setelah pimpinan partai yang mengadakan acara itu memberikan kata sambutan, kelompok musik angklung yang menjadi hiburan pertama. Aku mendapat giliran kedua. Meski bukan acara resmi, pesta rakyat yang diadakan sebuah partai itu dipadati warga desa yang haus akan hiburan. Apalagi sebelum acara dimulai dibagi sembako secara cuma-cuma.
Dengan takzim kupasang topeng di wajahku. Perlahan aku beranjak dari duduk bersilaku. Dari membelakangi penonton, aku memutar badanku setelah yakin topeng tak goyah. Saat itulah, ketika kuedarkan pandangan dari lubang di bagian mata topengku, aku melihat Nalar dan Danu berdiri di antara para penonton di bagian belakang. Mereka bergandengan tangan. Tarianku terhenti. Tubuhku beku. Di balik topengku, kulihat Nalar tersenyum. Sebelah tangannya menggenggam topeng kesayangannya. Perlahan ia memasang topeng itu di wajahnya. Sambil tetap bergandengan, kedua anakku berbalik. Melangkah menjauh entah ke mana. Itulah kali terakhir kulihat mereka berdua.
***