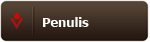Jejak
Wina Bojonegoro, penerima Anugerah Sabda Budaya Sastra 2018 dari Universitas Brawijaya, Penghargaan Beritajaim.com 2021. Menulis cerpen sejak 1988 ditayangkan di berbagai media nasional.
Karyanya juga terbit di puluhan buku antologi. Pada bulan Maret 2021, dia mendirikan Perempuan Penulis Padma untuk menampung para penulis lulusan sekolah menulis Padmedia, dan penulis perempuan lainnya. Lembaga itu telah berbadan hukum dan saat ini memiliki 83 anggota. Wina tinggal di Omah Padma – di Pasuruan. Dia dapat dihubungi melalui surel : wina.bojonegoro@gmail.com dan tentang dia dapat disimak di www.winabojonegoro.com
Jejak
Lelaki yang rambutnya memutih itu duduk di teras samping rumahnya, menatap pohon mangga lalijiwo yang tengah menunggu musim panen tiba. Seharusnya Wibowo bahagia, seperti musim-musim sebelumnya. Tetapi kali ini, ada sesuatu yang meruyak pikirannya.
“Aku telah gagal,” gumamnya seraya menghela napas panjang seolah dia hendak membuang segenap benih kekacauan.
“Kita tidak gagal.” Suara istrinya menelikung dari arah samping, melalui kembara hening yang menggenggam sore itu. “Dia berhasil menyelesaikan pendidikan strata dua di Jerman dengan beasiswa. Sekarang telah bekerja sebagai peneliti pada lembaga besar dengan gaji yang bagus. Kita tidak sia-sia mendidiknya.”
Wibowo menoleh ke samping. Di kursi yang sejajar dengan dirinya duduk Respati Rahayu, yang telah dinikahi lebih dari tiga puluh lima tahun. Selama ini perempuan itulah yang mendukungnya untuk menentukan apapun. Pilihan hidup, membangun rumah, bahkan memilih calon menantu di antara sekian lelaki yang disodorkan anak semata wayang mereka.
“Kurasa kita selama ini sepakat, bahwa keberhasilan orang tua dalam mendidik anak bukan sekedar ditandai pada pendidikan tinggi.” Wibowo ingin berpidato panjang lebar, tetapi melihat isterinya menyuguhkan teh serai kesukaannya, dia menelan ludah, lalu membuang nafas lagi. Direguknya teh serai wangi yang selalu menjadi teman mereka berbincang di sore hari. Irisan jahe dalam campuran serai menerbitkan pedas hangat di tenggorokannya. Kosarasa yang selalu dikenang saat mereka berjauhan, teh serai dengan irisan jahe buatan Respati Rahayu.
“Sementara orang lain tidak tahu harus bagaimana menangani pendidikan anaknya, kita berhasil menanamkan nilai, bahwa sekolah dengan beasiswa itu sebuah kehormatan.” Sang istri memulai lagi. “Kita tak perlu menyuap agar anak kita mendapatkan pendidikan baik. Mulai SD sampai S2 dia selalu masuk sekolah terbaik. Palupi tumbuh menjadi anak mandiri, tanpa merepotkan kita. Ini pencapaian kita sebagai orang tua.”
“Keberhasilan orang tua, yang paling penting adalah menanamkan nilai-nilai kebangsaan,” ujar Wibowo sembari menggenggamkan tangan. “Pendidikan memang sangat penting; tetapi menanamkan nilai kebangsaan, itulah dasar dari semua sikap dan perilaku.”
Respati Rahayu menoleh kepada suaminya dengan mata memicing. “Jadi anak kita tidak punya wawasan kebangsaan?” Suaranya meninggi. “Kurang apa? Dia hapal pancasila. Punya bendera di lemari yang siap dikibarkan kapan saja, hapal lagu Indonesia Raya.” Mata Respati yang biasanya lembut, kali ini terlihat nyalang. “Malah kita punya seperangkat gamelan yang masih dimainkan. Kita menggunakan bahasa Jawa dan bahasa negara dalam perbincangan sehari-hari. Anak kita juga….”
“Bagaimana bisa kamu bilang anakmu itu berkebangsaan?” Wibowo menyela. “Mencari nama buat calon anaknya saja impor. Apa tidak ada nama Indonesia atau Jawa yang indah dan gagah?” wajah Wibowo yang sudah tegang sejak semula, menjadi kian kencang. Lelaki Jawa yang bersikeras membangun joglo di bagian depan rumah induk itu terlihat sangat masgul.
Nama Wibowo Besari yang disandangnya adalah pesan leluhur yang berarti: lelaki berwibawa, digdaya tanpa menyakiti, besar tetapi tidak jumawa, mengayomi tanpa merendahkan. Nama itu serupa titah sang romo yang pernah menjabat sebagai camat di kawasan Tejowangi ini.
“Wong Jowo ojo nganti ilang Jawane. Jadi orang Jawa jangan sampai hilang jati dirinya.” Ucapan ayah Wibowo Besari itu, dijadikan pegangan dalam menjalani hidup. Sebab demikianlah takdir telah disematkan atas dirinya sebagai wong Jowo, maka dibuatlah rumah joglo, pendopo seni, sebagai ciri kejawaan dan membeli seperangkat gamelan slendro dan pelog. Lalu, dia mengajak para tetangga memainkannya. Sesekali jika rejeki membaik, keluarga ini mengundang tetangga untuk kenduri di rumah joglo itu. Nasi tumpeng dengan ayam ingkung, ayam panggang dalam keseluruhannya, menjadi hidangan wajib yang disuguhkan.
***
Terngiang di kotak ingatan Respati perselisihan lama antara dirinya dan sang suami. “Palupi Retnaningrum Hapsari itu kepanjangan. Cukup dua nama seperti kita. Wibowo Besari. Respati Rahayu.” Keluh Respati sembari mengelus perutnya yang membuncit.
“Diajeng tahu artinya tiga nama itu?” Tanya Wibowo muda dengan senyum menggoda.
“Ya tahulah. ‘Palupi’ artinya teladan. ‘Hapsari’ artinya permata yang bersinar. Sek sek… ‘Retnaningrum’ artinya apa ya Mas?”
“Retnaningrum artinya kepribadian yang luwes dan welas asih. Jadi harapanku anak ini kelak menjadi pribadi yang welas asih, berhati mulia, menjadi teladan bagi orang-orang di sekelilingnya.” Sepasang mata Wibowo muda berkilau.
“Itu kalau anak kita perempuan. Lha, kalau lelaki?” Respati melirik tajam ke arah suaminya.
“Dia akan kuberi nama Jagad Reksaning Bawono. Tetapi kata bu bidan, anak kita perempuan.” Wibowo tersenyum lebar, tanda kemenangan.
Saat itulah Respati paham bahwa nama dalam tatanan kemasyarakatan Jawa memiliki aturan tak tertulis. Satu nama menandakan keluarga itu dari golongan petani atau pekerja tingkat bawah. Dua nama biasa digunakan dalam keluarga pegawai pemerintahan, guru atau pedagang. Tiga nama lazim digunakan keluarga ningrat atau pejabat tinggi. Namun, saat ini penggolongan itu tidak lagi menjadi pakem. Meski begitu, Wibowo memiliki pendirian: menggunakan nama Jawa pada anak cucunya adalah wajib, agar darah yang mengalir di tubuh mereka terpantulkan dari nama yang disematkan.
***
Kabar saat Palupi mengandung anak pertama, tentu menjadi sebuah cahaya bagi pasangan yang terlambat memiliki cucu. Hasil pemeriksaan USG mengabarkan anak dalam kandungan Palupi adalah perempuan. Wibowo mulai menderas nama berminggu-minggu, hingga suatu hari dia tampak tersenyum simpul di rumah joglo.
“Aku telah menemukan nama yang tepat buat cucu kita,” katanya pada Respati yang menyusul duduk di kursi rotan jengki. “Maharani Mahisa Suramardini.” Dengan pengucapan patah-patah dan suara didengung-dengungkan, Wibowo mengucapkan nama itu disertai wajah puas.
Respati mendelik.
“Kenapa? Hebat kan?” tanya sang suami.
Respati menggeleng. “Orang Jawa kalau keberatan nama bisa sakit-sakitan.”
“Tunggu dulu.” Wibowo melanjutkan dengan mata berbinar-binar, “Maharani Mahisa Suramardini adalah gelar Ratu Sima, raja Kalingga yang masyhur. Dia bukan saja ratu yang adil dan bisa menerima perbedaan agama, namun juga cantik jelita. Budi pekertinya luhur, sehingga dicintai kaum jelata, disegani golongan kelas atas.”
“Tapi kita ini bukan golongan atasan, Pak. Apalagi trah raja atau ratu. Kita cuma pensiunan pegawai negeri. Kebetulan saja mertuaku pensiunan camat. Masa iya memberi nama cucu seberat itu?” tangkis Respati dengan pikiran ruwet. Setelah diam sejenak, dia berkata, “Mengeja namanya saja susah. Bagiku nama Ningsih, Endang, Wati, itu jauh lebih mudah dan indah.”
Wibowo tersenyum lebar, “Sudah kurenungkan berminggu-minggu. Kucarikan padanan dan perbandingan, lihat itu di buku catatanku. Ada berapa ratus nama dengan artinya?” Wibowo meraih buku catatan bersampul biru di atas meja kecil, mengacungkannya pada Respati sambil berkata, “Ini perjuangan tak mudah untuk menemukan nama yang tepat buat cucu pertama kita. Sebagai kakek, aku ingin turut andil dalam melestarikan nama, tanda kecintaan kita pada leluhur.”
Respati hanya bisa mengangkat pundak. Darahnya pun Jawa tulen, seluruh urutan garis leluhurnya adalah Jawa. Namun dalam melakoninya sehari-hari, suaminya jauh lebih Jawa dari dirinya.
Wibowo memegang teguh falsafah Memayu Hayuning Bawana yang memiliki makna menjunjung tinggi kemanfaatan diri bagi dunia dan isinya. Barang siapa berbuat kebaikan, dia akan selamat dunia akhirat. Salah satu wujudnya adalah, menolak pagar beton atau besi. Dia menggantinya dengan pagar pohon beluntas, yang ditanam rapat mengelilingi batas halaman sebagai kesadaran hidup bertetangga yang saling menghidupi. Beluntas itu menjadi sayuran yang boleh diambil siapa saja sebagai bahan urap-urap atau pecel.
Merasa telah menemukan wangsit nan jitu, Wibowo menelpon Palupi dengan gegap gempita. “Maharani Mahisa Suramardini. Ini nama yang luar biasa, Ndhuk. Jejak kita sebagai wong Jowo akan terekam dalam nama anakmu. Kelak ketika dia dewasa, orang-orang luar sana akan mengenal anakmu sebagai orang Jawa. Jangan lupa, jika ada yang bertanya, kakeknya yang memberi nama!” calon kakek itu tertawa riang.
“Romo…,” suara Palupi mengandung keengganan, dari nadanya dia terdengar ingin melawan.
“Bagaimana? Bagus kan nama pilihan Romo?” Nada bangga Wibowo masih tergambar.
“Tapi Romo, maaf, kami telah menemukan nama buat bayi kami.”
Jawaban Palupi itu seketika mencegah Wibowo untuk berkata selanjutnya. Raut wajahnya mendadak kaku dan pasi. Dia menatap istrinya, yang juga tengah menatapnya.
Kekecewaan mewarnai mata sang calon kakek.
“Lalu siapa nama yang akan kau berikan pada anakmu?” Respati tampak mencoba mencairkan ketegangan yang mendadak hadir di antara dua pihak.
“Alexa Caroline Andromeda,” jawab Palupi kembali riang, seakan dia telah menemukan gugusan bintang di langit yang mudah diraih dengan kedua lengannya.
“Artinya?” tanya sang ibu lagi.
“Alexa itu bahasa Yunani, artinya perempuan pembela manusia. Caroline artinya tangguh dan mengagumkan. Andromeda adalah nama gugusan bintang di alam semesta yang sangat luas, jauh lebih besar dari Bimasakti.”
“Kenapa harus pakai bahasa Yunani? Tidak adakah nama asli Indonesia atau Jawa yang cukup memadai sebagai pengganti anak perempuan hebat?” Sesungguhnya ini kalimat Wibowo. Respati mencoba mengutipnya.
“Anu Bu, sudah terlanjur.” Suara Palupi terdengar gamang.
“Terlanjur bagaimana? Wong anak belum lahir kok.” Sekarang Respati yang mulai merasa masgul. Dia tak ingin anaknya salah menyikapi bayinya, sesuatu yang sangat dilarang dalam budaya Jawa.
“Sudah memesan pakaian bayi, keranjang tidur, dan lukisan dinding kamar tidur dengan nama itu.” Nada suaranya menurun, seakan menyesal telah menyampaikan.
“Kamu kok lancang tho, Nduk?” Wibowo menyela. “Kamu jangan nggege mongso – mendahului kehendak Tuhan. Jangan membeli perlengkapan bayi sebelum upacara tingkeban yang diadakan saat kandungan berusia tujuh bulan agar kamu dan bayimu sehat dan persalinannya lancar. Keheningan hadir setelah kalimat itu terlontar.
“Palupi, kamu tahu kenapa huruf ha na ca ra ka itu nyaris lenyap?” tiba-tiba sang ayah mendesak.
Palupi terdiam.
Respati membasuh wajah dengan kedua tangan, menyadari kegentingan akan panjang.
“Sepertinya anak-anak muda sudah tidak ngajeni leluhurnya.” Wibowo berhenti sejenak, kemudian melanjutkan dengan suara meninggi, “Kenapa nama saja harus impor? Nama seharusnya digunakan untuk menjaga nilai kedirian, agar anak-anak muda tak lupa akar leluhurnya.” Wibowo menunggu tanggapan Palupi. Ketika tidak juga muncul, dia menyerang, “Mestinya kalian malu sama orang Jepang. Mereka maju. Mengikuti jaman, tetapi perilakunya tetap Jepang. Budaya mereka abadi. Hurup kanji dipakai sampai sekarang.” Wibowo berhenti terengah-engah sebelum menyambung dengan tegas, “Nama mereka pun tetap Jepang.”
Palupi tetap membeku.
Dengan berusaha menerobos keheningan, Wibowo mengakhiri dengan berteriak, “Kamu apa? Jawa? Indonesia? Bule bangsa apa?”
***
Sejak hari itu, Wibowo enggan berbicara dengan Palupi, anak perempuan yang dulu sangat dipujanya. Dia lupa, Palupi pernah menjadi bahan pembicaraan di pertemuan apapun, dengan siapapun.
Respati, sebagaimana seorang ibu, selalu berusaha menjadi jembatan dalam hubungan antara ayah dan anak yang membeku sejak persoalan nama itu mencuat.
“Ndhuk, apakah kamu tak ingin menyapa romomu lebih dulu?” Sang calon nenek menelpon tanpa sepengetahuan suaminya.
Palupi mendesah.
Embusan napasnya terdengar oleh Respati yang meneruskan dengan desakan, “Apa sulitnya menerima usulan nama romo?” Pertanyaannya hanya disambut dengan jeda panjang.
Kemudian Palupi berkata, “Bu, Palupi memang orang Jawa. Itu darah yang mengalir di tubuh saya tak dapat disangkal. Namun, sebagai seseorang, saya berhak memberi nama anak saya sesuai dengan selera. Seperti Romo dulu juga memberi nama Palupi sesuai dengan keinginan Romo dan Ibu.”
“Boleh. Tetapi yang tidak disukai romo adalah nama impor itu. Gunakan nama Jawa atau Indonesia yang mampu menjadi jati diri leluhurmu.” Dada Respati penuh, tetapi ditahannya kuat-kuat. Sebagai ibu, dia tidak pernah mengalami perselisihan seruncing ini dengan anaknya. “Seandainya kamu tahu, bagaimana romo berjuang menderas nama buat cucu pertamanya, kamu akan bangga ditakdirkan lahir dari benihnya.”
“Saya mengerti. Tetapi saya harus menghormati suami saya. Dia punya hak memberi nama pada darah dagingnya.”
Bendungan yang menahan beban akhirnya meluber. Pelan-pelan air mata bergulir di pipi Respati yang telah kehilangan kemulusannya. Matanya kelabu. Benar, dia tak salah mendidik Palupi. Tetapi sungguh, dia tak menyangka akan sekokoh ini sikapnya. “Apakah kamu sudah bicara dengan suamimu soal nama itu?” suara parau meluncur dari tenggorokan Respati.
“Belum. Seperti Ibu menghormati sikap Romo, saya pun menghormati suami. Bukankah itu yang Ibu ajarkan? Saya menunggu waktu yang tepat untuk membahas soal nama Jawa dengan Bang Syarif. Pada saat itu baru saya akan usulkan.”
Hening menjaga jarak di antara ibu-anak.
“Ibu berharap suamimu mengerti.” Respati merendahkan suaranya. “Nama yang kita sematkan untuk anak kita adalah upaya melestarikan jati diri. Kelak mereka pasti akan menelusuri jejak budaya dan leluhurnya, setidaknya dimulai dari bertanya arti namanya,”
Respati merasa menemukan kalimat yang tepat. “Ciri khas daerah dalam nama itu akan selalu dibawa oleh si anak ke mana pun dia pergi, dan menjadi ciri khas di negeri manapun, dia akan dikenali sebagai anak Indonesia, khususnya Jawa.”
Palupi tahu, ketika ibunya telah berbicara dalam nada rendah, itu adalah perasaan penting yang keluar dari hati. Dia tidak menyela ketika ibunya melanjutkan, “Tetapi meski terlahir sebagai wong Jawa, kami tak ingin menjadi kolot. Masih ingat? Ketika kamu menyodorkan calon suami, pertanyaan romo waktu itu bukan kenapa bukan orang Jawa? Apakah sudah punya rumah? Dari keluarga apa? Tidak kan? Pertanyaan Romo hanya satu: apakah dia menjunjung tinggi kehormatanmu sebagai perempuan?
Terdengar isak kecil dari seberang.
Respati menahan diri agar tak larut dalam suasana. Dia menyadari, dalam dunia yang serba cepat dan tanpa batas saat ini, menjaga jejak kebangsaan melalui nama amatlah muskil. Nama berbau dunia luar seringkali lebih terlihat kekinian. Menjaga nama-nama Jawa tetap digunakan bagaikan menegakkan benang basah.
***
Makan malam yang seharusnya sederhana dan riang sebagaimana tiga tahun berjalan, tidak lagi malam ini. Palupi terlihat menahan gelombang di dadanya. Sementara Syarif Hidayatullah, sang suami, mengunyah makanan lambat-lambat seperti tak ada rasa dalam masakan itu. Suara televisi menyiarkan berita banjir di sana sini, membuat Palupi semakin tegang. Dia mematikan TV.
Lelaki campuran Bugis – Palembang yang meminang Palupi dengan seperangkat alat sholat dan perhiasan emas itu menyudahi makan malam dalam diam. Dia meneguk air putih lalu berdiri, tak ingin melanjutkan perbincangan yang sudah dimulai oleh Palupi sejak mereka duduk di ruang makan itu.
“Tunggu, Bang. Kita belum selesai,” sergah Palupi.
Syarif kembali duduk dengan enggan, jemarinya memain-mainkan gelas yang telah kosong.
“Kumohon Abang bisa menerima ini. Soal nama anak kita, dan soal upacara tingkeban yang diminta Ibu.” Suara lembut Palupi terdengar seperti rayuan.
Syarif menatap isterinya dalam-dalam. Isi kepalanya mengatakan tak ingin membahas soal nama anak, baginya itu harga mati. Orang tua berhak memberi nama anak masing-masing tanpa campur tangan siapapun.
“Memang tidak menyenangkan hidup sebagai anak tunggal.” Suara Palupi berubah menjadi tegas. “Ada kewajiban secara tidak tertulis untuk meneruskan adat, dan leluhur. Aku sudah berusaha menolak mereka soal nama dan tingkeban, tapi hasilnya aku bertengkar dengan Romo dan Ibu – sesuatu yang tidak pernah terjadi seumur hidupku.” Palupi tertunduk, air mata bergulir di sepasang pipinya.
Syarif menutup mulutnya dengan kedua tangan sambil sikunya bertelekan pada meja. Ada selembar rasa bersalah melintas di hatinya. Tetapi sisi lain menolak. “Bukankah setiap anak perempuan yang diserahkan kepada mempelai pria saat akad nikah, menjadi hak sepenuhnya sang suami?” suara Syarif pelan dan datar, tetapi Palupi menyahut dengan cepat.
“Suami memberi mahar pada isteri bukan berarti membeli.” Kalimat itu terdengar garang di telinga Syarif, perempuan ini seperti bukan Palupi yang biasanya. “Murah sekali jika seorang lelaki membeli perempuan dengan seperangkat alat sholat, lalu dia berhak sepenuhnya atas perempuan itu.” Palupi menatap tajam mata suaminya yang hitam kelam.
“Berapa biaya yang dikeluarkan lelaki untuk mendapatkan seorang perempuan dalam keadaan terbaik mereka? Lalu bandingkan dengan berapa biaya orang tua merawat anak perempuan itu sejak dia dalam kandungan, hingga usia pantas menikah. Berapa nilai modal yang ditanam?”
Kata-kata yang sudah tersimpan di mulut Syarif raib.
“Aku menyerahkan diriku padamu, suamiku, karena aku mencintaimu.” Berbaris-baris kalimat telah siap dilontarkan oleh Palupi, tetapi dia menjaga martabat suaminya.
Syarif terlihat makin membeku.
“Setelah seluruh cinta mereka tumpah ruah demi anaknya semata wayang, agar aku menjadi perempuan berpendidikan dan berbudi pekerti baik, sehat jasmani dan rohani, aku menyerahkan diri sepenuhnya untukmu secara suka rela. Sekarang, sulitkah bagimu menerima nama hadiah dari orang tuaku karena semata kau ayah bayi ini?”
Syarif melihat sepasang mata istrinya berkilat. Selama tiga tahun pernikahannya, Palupi tidak pernah bicara berapi-api seperti malam ini.
“Baiklah.” Akhirnya Syarif merendah. “Nama bayi pertama boleh memakai hadiah dari romo. Tetapi soal tingkeban, itu tidak ada dalam ajaran agama kita.”
Palupi berdiri gesit, tubuhnya terlihat tegap meskipun dalam keadaan hamil menjelang tujuh bulan. “Adat dan agama dua hal yang tak bisa menyatu, Bang. Mereka berjalan beriringan seperti rel kereta untuk mencapai satu tujuan, kerukunan.” Palupi meninggalkan Syarif sendirian di ruang makan dan berjalan cepat-cepat menuju kamar untuk menelpon ibunya.
***
Kyai Brajadenta, gamelan milik keluarga Wibowo, siang itu mengalun lembut di rumah joglo Wibowo. Gamelan yang ditabuh oleh sebelas lelaki dan beberapa perempuan tetangga itu menampakkan sisi terbaik dari sebuah pasugatan, jamuan untuk tamu-tamu yang dihormati. Suasana ramah dan penuh canda memenuhi joglo dan rumah induk yang rimbun oleh pepohonan. Orang-orang yang belum tentu setahun sekali berjumpa, hari ini berkumpul dalam suasana semarak.
Semalam telah dilakukan pengajian untuk mendoakan sang ibu dan janin dengan sajian makanan langka, tujuh buah tumpeng ditambah jajanan pasar, ketan kolak, pisang raja. Sekarang saatnya rangkaian upacara lengkap yang dimulai dengan siraman.
Sebuah sudut telah disiapkan dengan hiasan aneka kembang dan jambangan berisi air dari tujuh sumber dan bunga tujuh rupa: mawar, melati, kenanga, gading, sedap malam, kemuning, pacar banyu. Palupi dengan riasan sederhana dan kemben jumputan merah hati, menggunakan hiasan melati ronce menutupi pundak dan dadanya. Dia duduk di sebuah kursi kayu, siap memulai upacara siraman oleh para tetua termasuk keluarga besan yang jauh-jauh datang dari Makassar.
Syarif tak henti menebar senyum. Keluarga besar di Makassar ternyata menyambut baik upacara adat tingkeban ini. Para perempuan justru sangat senang dan sukarela mengenakan kebaya dan jarit, sedangkan para lelaki menggunakan blangkon dan beskap. Segala keriuhan itu menjadi sebuah tontonan menarik di mata adik bungsu Syarif, yang mengabadikan semuanya untuk santapan youtube.
*****