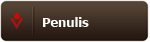Ulasan
PELUNCURAN DAN DISKUSI BUKU LOLONG ANJING DI BULAN
Ruang Seminar Driyarkara, 9 November 2018
Lolong Anjing di Bulan adalah novel pertama Arafat Nur yang saya baca. Ini baik karena saya tidak perlu membandingkannya dengan novel-novel Nur lain yang sudah lebih dahulu terkenal dan beberapa terbukti telah memenangkan berbagai penghargaan sastra.
Dari satu novel ini, semoga saya tidak salah menyimpulkan bahwa Arafat Nur adalah pengarang yang “hanya” bermodalkan cinta. Ia cinta pada dunianya – dunia sastra; ia cinta pada kehidupan; dan terutama ia cinta pada kemanusiaan.
Alam Aceh terbentang dengan nyata dalam novel Lolong Anjing di Bulan. Bagi pembaca yang terbiasa melihat pemandangan alam di Jawa dengan sawah, parit, dan tumbuhan tumpang sarinya, sungguh unik dan mengesankan panorama yang tergambar dalam novel ini. Ladang kunyit, kebun kelapa, sawah dan padi gunungnya. Pemandangan alam Aceh dan kehidupan petani serta penggarap kebun hadir di depan mata, seolah kita bisa bercakap-cakap dengan Nasir sang pencerita, kedua orangtuanya, saudara-saudara perempuannya. Kisah kakek dan nenek Nasir serta penderitaan yang dialami di akhir hidup mereka terbayang dengan jelas.
Karena bermodalkan cinta tadi, saya tidak mendapati penggambaran berlebihan tentang kekejaman, tubuh remuk, gelimang darah, dsb. Kezaliman tentara pemerintah maupun pemberontak tidak dikisahkan dengan kasar, tetapi justru menyentuh hingga mengaduk-aduk nurani kita.
Sejak awal, novel ini telah memberi tengara: Perang adalah kesia-siaan belaka. Perang adalah perayaan budaya kematian, padahal kita harus menjunjung tinggi budaya kehidupan. Setiap orang dipanggil untuk melindungi dan mencintai hidup, karena hidup itu anugerah Tuhan kepada manusia. Tuhan lah pemilik kehidupan manusia. Perang memungkiri semua itu.
Dari banyak pengisahan tentang sejarah suram Aceh yang ditulis dengan apik oleh Arafat Nur, yang paling mengesankan menurut saya adalah saat kakek Nasir panen pisang. Agak antroposentris, memang, tetapi pemerian ini berbicara banyak tentang kehidupan. Karena terbatasnya waktu, saya kutip beberapa saja:
Setiap tiga bulan sekali muncul sebuah mobil Chevrolet bak terbuka dengan membawa pekerja berpakaian gelap. Dua pekerja itu mencari sendiri tandan pisang yang tiba waktunya untuk dipanen. Dengan parang yang sangat tajam, mereka begitu lihai menebang batang pisang itu. Libasan parang pertama, dengan kekuatan terukur di tengah batang, membuat pohon itu tetap tegak. Tebasan kedua, yang miring, membuat pohon itu menunduk perlahan setengah rebah, seperti menyerahkan buahnya secara hormat. (Nur – Lolong Anjing di Bulan – h. 128)
Entah mengapa bagian ini begitu mengesankan buat saya. Metafora apa yang dibidik oleh pengarang, saya belum mendalaminya. Tetapi saya menduga bahwa alam bersikap ramah kepada kita kalau kita juga memperlakukan alam dengan baik. Kakek merawat dengan telaten kebun pisang itu hingga bisa menghidupi keluarga. Di kebun pisang itu pula Nasir kecil memperoleh pembelajaran pertama tentang arti kata melawan. Waktu itu dengan rasa takut luar biasa Nasir mengintip sekawanan tentara yang mengobrak-abrik kebun pisang kakek. Mereka mencari pemberontak yang bersembunyi tetapi tidak berhasil. Serdadu-serdadu itu kemudian berlalu sambil memanggul setundun pisang yang telah ranum. Pada titik ini Nasir paham mengapa pemberontak Aceh tidak takut pada serdadu. Mereka tidak percaya kalau tentara hadir untuk membela rakyat. Di mata Nasir kecil, perang timbul dari gairah untuk melawan. Gairah ini lebih kuat ketimbang rasa takut.
Langgam novel ini perdamaian terbukti dengan penggambaran yang berimbang antara ketakutan dan kebencian penduduk pada tentara di satu pihak, dan di pihak lain, orang-orang berseragam yang geram, gusar, dan penasaran, bertekad memburu pemberontak yang menyusup di mana-mana. Nur mencoba mengajak pembaca melihat bencana beruntun yang timbul ketika ada anggota keluarga yang bergabung dengan pasukan pembangkang. Ia menyaksikan satu demi satu orang-orang terkasih terenggut dari kehidupannya; semua itu gara-gara Panglima Sagoe bernama Arkam yang adalah pamannya. Tanpa ampun pasukan pemerintah menghabisi siapa saja yang dicurigai sebagai GAM. Maka ketika akhirnya Nasir memutuskan untuk angkat senjata. Tokoh kita ini melakukannya bukan untuk balas dendam. Si vis pacem, para bellum. Nasir ingin menyudahi budaya kematian karena ia merindukan kehidupan.
Akhirnya saya berkesimpulan bahwa melalui Lolong Anjing di Bulan, Arafat Nur hendak berpesan: Bacalah sebanyak mungkin buku-buku sastra. Sastra memperkaya batin meredam ketidakakuran. Contoh sudah diberikan, yakni buku-bukunya yang menunjukkan rasa cintanya yang mendalam pada jagad sastra, kehidupan, dan kemanusiaan.