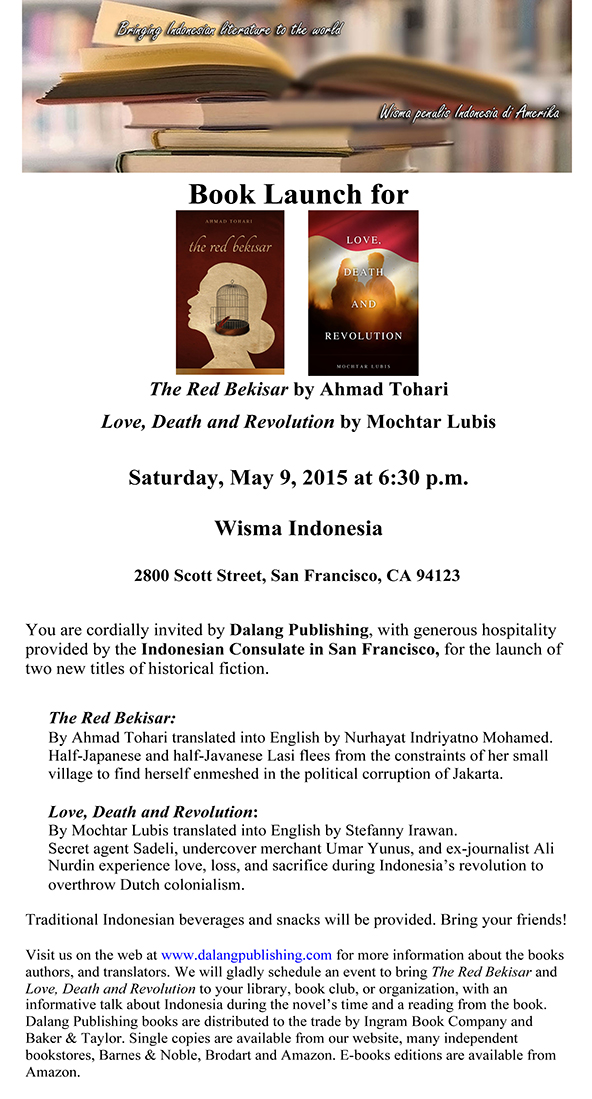Dalang Publishing & PGRI
Merayakan Bulan Bahasa
Dengan
Mengulang Soempah Pemoeda
Lian Gouw
Dalang Publishing
dalangpublishing@gmail.com
Selamat pagi Bapak-bapak dan Ibu-ibu.
Terima kasih banyak pada para pimpinan Universitas PGRI terutama Pak Prasetyo dan Ibu Maria Yosephin yang telah memberikan kesempatan ini kepada saya untuk membagikan suatu hal yang sangat memusatkan pikiran dan gerakan hidup saya pada saat ini: yaitu: melindungi bahasa kita dalam suasana gaya hidup yang lebih condong mengikuti arus dunia daripada menghargai dan merayakan kekayaan dan keindahan dari kebudayaan dan bahasa kita sendiri.
Saya sadar bahwa saya menghadapi banyak tentangan dari orang orang yang berpendidikan maupun dari “orang-biasa.” Namun, bagi saya, mengikuti semangat dan kejujuran panggilan hati lebih penting daripada meraih kemasyhuran umum.
Setelah terjadi beberapa bentrokan antara “kebandelan” saya dalam menahan pendapat saya dan pendapat umum (termasuk teman dekat dan kenalan yang berpendidikan di bidang bahasa) saya menggali diri untuk mencari alasan atas tujuan yang begitu mengusik saya.
Sebagian dari hasil “penggalian” itu adalah kesadaran atas pentingnya peran bahasa dalam hidup kita sehari-hari. Bahasa adalah alat yang paling diperlukan dalam berhubungan dengan sesama manusia. Membungkamkan seseorang adalah sama dengan menghancurkan jiwanya.
Dari zaman purbakala hingga sekarang pengacauan bahasa adalah senjata tersembunyi yang sangat ampuh untuk menumbangkan musuh.
Contoh: Tuhan di zaman purbakala menyerakkan orang-orang Babel dengan mengacaukan bahasanya, selama kita dijajah oleh Belanda, hanya orang yang mampu berbahasa Belanda secara lancar dan benar “dianggap,” pada perang dunia ke II orang Jerman dan orang Jepang memaksa masyarakat di negara-negara yang didudukinya untuk belajar bahasa Jerman dan Jepang, dan pada saat Indonesia mencapai kemerdekaan, Presiden Soekarno dengan tegas mengumumkan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Republik Indonesia.
Dengan kebijaksanaannya beliau mengerti bahwa kita sebagai bangsa yang tersebar di antara lebih dari 17.500 pulau-pulau dari Sabang sampai Merauke perlu bersatu untuk mampu mempertahankan diri dalam menghadapi negara-negara besar yang lain di dunia ini. Karena itu beliau membimbing kita, bangsa Indonesia, dengan lambang Bhinneka Tunggal Ika untuk bersatu di bawah satu bendera dan bersatu dalam menggunakan satu bahasa resmi, yaitu Bahasa Indonesia.
Saya sangat setuju bahwa bahasa apapun harus berkembang sehingga dapat bermanfaat dalam pelayanan bangsa dan negara yang berkembang. Perkembangan ini akan mengantarkan beberapa keadaan baru yang dengan sendirinya akan membangun kata-kata dan istilah-istilah baru. Nah di sinilah terletak tugas para ahli bahasa kita untuk mengatur dan membawa kata-kata ini dalam bingkai bahasa kita dengan memberikan perhatian pada irama bahasa kita dan cara berpikir jiwa kita. Hal ini memerlukan keahlian. Penanganan hal ini membutuhkan jauh lebih banyak kecerdasan daripada hanya menempelkan awalan dan akhiran dari bahasa Indonesia pada kata asing.
Penyebab dari hal ini dalam pendapat terbatas pribadi saya berasal dari ketidakmauan kita sebagai bangsa untuk mencari jalan keluar yang lebih tepat daripada hanya meniru atau menyalin dan juga karena kecenderungan kita untuk menampilkan diri sebagai orang yang berpendidikan di luar negeri.
Saya sering heran bahwa sepertinya tidak ada seorang pun yang terganggu dengan irama atau “bunyi” kata-kata seperti: memfokus – berkommunikasi – ngeprin – webset dll – kata-kata serapan yang lebih sering dan suka digunakan daripada: memusatkan perhatian – berhubungan – mencetak – situs dll.
Para ahli bahasa kita tidak hanya dibebani dengan tugas untuk mencari kata yang tepat namun sebagai anak bangsa juga bertanggung jawab untuk menjadi penjaga yang teliti dan tulus untuk gerbang kamus besar bahasa Indonesia.
Dari beberapa perbincangan yang saya lakukan khusus untuk membahas hal ini dengan berbagai ahli bahasa, guru, mahasiswa, pegawai negeri dan swasta, saya mendapatkan kesimpulan yang menyedihkan.
Jarang sekali saya bertemu dengan seseorang yang menunjukkan kekhawatiran pada pengrusakan bahasa kita oleh serapan bahasa asing. Kebanyakan dari antara mereka berujar, “Ya begitulah—apa lagi yang dapat kita lakukan?”
Pernyataan yang membuat saya langsung memekik, “Banyaklah yang dapat dilakukan! Terutama jangan mengekori para perusak bahasa ini, dan kedua melawan perilaku mereka dengan memberi contoh yang baik dan menolak ikut serta dalam perilaku yang tidak dapat patut itu.”
Ada juga jawaban yang lebih menyedihkan dan menjengkelkan saya. Bunyinya seperti ini: “Dengan use kata-kata itu, kita kan menunjukkan kita tidak ketinggalan zaman. Kita hidup now, bersifat global…, berpendidikan….”
Salah seorang mahasiswa berkata: “Me-use word bahasa asing kan cool, Bu!” Yaa…. Ampun! Jika anak muda ini adalah calon “tiang” masyarakat kita di kemudian hari — hasil didikan para orang tua dan guru sekarang ini — apa yang dapat diharapkan untuk masa depan bangsa dan negara kita?
Saya sedih dan prihatin memikirkan hal ini. Apalagi karena dengan memikirkan hal ini saya tidak mampu mengabaikan upaya nenek moyang kita yang mewarisi kita kemerdekaan yang dengan sendirinya memberikan hak kepada kita masing-masing untuk secara bebas menggunakan bahasa kita sendiri. Mungkin juga sukar sekali untuk orang-orang muda yang hanya menikmati hasil perjuangan pahit leluhurnya untuk dengan sadar berterima kasih terhadap kemerdekaan yang mereka nikmati. Mungkin juga karena mereka dilahirkan dalam keadaan negeri merdeka orang-orang muda itu lupa atau tidak punya ketertarikan untuk menghargai dan menghormati perjuangan leluhur dalam perilaku mereka sehari-hari.
Nah, beginilah keluhan saya terhadap penggunaan bahasa kita secara umum dalam semua kalangan; dalam berbicara maupun menulis, dalam hal-hal resmi maupun sehari-hari.
Mengujar keluhan adalah mudah sekali. Namun mencari jalan keluar dari masalah yang dikeluhkan adalah perkara yang lebih sulit. Saya bersikap bahwa keluhan tanpa diiringi usulan yang dapat mengatasi masalah yang dikeluhkan itu, tidak berguna. Dan jawaban saya pada si pengeluh selalu adalah pertanyaan: “Apa usulan Anda untuk mengatasi masalah yang dikeluhkan itu?” Karena itu, saya pun melontarkan pertanyaan itu kepada diri saya. Dan saya senang sekali ketika saya menemukan cukup banyak cara untuk memecahkan masalah ini.
Atas dasar jawaban yang terlontar oleh para mahasiswa itu dan kenyataan bahwa mereka adalah penerus masyarakat di masa depan dan menjadi bagian penting dalam perkembangan negara kita, saya bertanya: Apa yang menjadikan anak muda ini berpikir seperti itu? Apa alasan yang membuat dia berpendapat bahwa menggunakan kata-kata bahasa asing akan menampilkan dirinya sebagai seorang “terpelajar” atau “keren?” Dari perbincangan kami, saya mendapatkan beberapa kesimpulan:
- Kecenderungan umum pada saat ini adalah bahwa menggunakan kata-kata keinggrisan adalah tanda “terdidik” dan juga pernyataan bahwa sang pembicara pernah belajar di luar negeri atau cukup bergaul dengan orang asing.
- Tidak ada perasaan kasih atau bangga terhadap bahasa sendiri. Suatu sikap yang akan menghindari pemerkosaan kata-katanya.
- Kita sudah merdeka 73 tahun, namun kita masih merasakan dampak penjajahan yang menghapus kepercayaan dan kebanggaan diri kita dan, selama 350 tahun, telah “menyekoki” kita dengan kepercayaan bahwa segala yang kita miliki secara keberadaan tidak bernilai. Kita juga dibuat untuk meyakini bahwa hanya jika mampu meniru cara dan hidup mereka, ada kemungkinan kita dianggap sederajat.
Berdasarkan tiga kenyataan tersebut, saya menyimpulkan bahwa bahasa kita berada dalam keadaan yang genting karena:
Dengan pemahaman tersebut, apa yang dapat kita lakukan untuk memperbaiki keadaan buruk ini?
Saya kira tindakan yang paling penting adalah menyalakan kembali api perasaan kebangsaan hingga berkobar seperti di zaman perjuangan. Api yang berkobar-kobar dan memberikan masyarakat Indonesia yang sedang dicengkram dalam cakar penjajah semangat, harapan, dan keberanian untuk maju dengan kepercayaan diri. Api yang dinyalakan dan dipicu oleh Presiden Soekarno pada saat itu sekarang perlu dihidupkan kembali.
Dengan membangun kembali perasaan kebangsaan, kebanggaan dan keinginan untuk melindungi dan membela tanah air termasuk kepentingannya bisa tercapai, sedangkan perasaan kepercaan diri pun bisa sekaligus berkembang. Sekolah-sekolah mulai dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi adalah ladang penyemaian yang sempurna untuk menebarkan benih kebangsaan. Melalui mata pelajar ilmu bumi, sejarah, kebudayaan dan bahasa, perasaan dan kesadaran terhadap kebangsaan dapat dibangun.
Saya masih ingat bahwa di zaman penjajahan kami takut sekali menggunakan bahasa Belanda yang tidak baik dan benar. Betapa kami dihina jika menggunakan tata bahasa yang keliru, mengucapkan sebuah kata dengan tidak tepat.
Heran juga bahwa sekarang kita tidak mampu menerapkan aturan itu bagi bahasa kita sendiri. Kesadaran bahwa pelanggaran itu tidak hanya dilakukan oleh bocah yang masih kencur dalam pikiran, namun juga oleh para kaum dewasa dalam lingkungan pendidikan dan pemerintah, sangat menyedihkan.
Setelah seseorang meninggalkan bangku sekolah, ketertiban dalam menggunakan bahasa dapat dilanjutkan di lingkungan kerja. Di zaman penjajahan seseorang yang tidak mampu menulis surat dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar tidak mungkin mendapat kesempatan untuk melamar pekerjaan yang mendudukannya di depan meja tulis. Misalnya dalam lingkungan penerbitan mulai dari surat kabar, ke majalah, ke buku, penguasaan bahasa diperlukan. Nah apa yang dimaksudkan dengan penguasaan bahasa?
Dalam pengertian saya sebagai seorang penerbit, seseorang yang menguasai bahasa tidak hanya fasih dalam berbicara dan menulis tetapi juga mengerti apa yang dikatakan dan tertulis dalam bahasa itu. Seorang yang menguasai bahasa, selain dari mampu memahami juga mampu berfikir, merasa, melihat, mendengar dan menyentuh dengan menggunakan bahasa itu. Dengan lain kata, bahasa yang dikuasai adalah salah satu jalan dan sarana untuk hidup. Dan di-situ-lah tempat lahirnya penulis yang hebat.
Lee Young Li, seorang penyair Amerika yang lahir di Jakarta dalam karyanya berjudul “Immigrant Blues” —renungan sedih seorang perantau—berkata tentang belajar bahasa asing, “Practice until you feel the language inside you….” —berlatihlah hingga bahasa itu menelusup dalam jiwamu. Tidak terdengar, tidak tertulis, tidak terucap, namun, terasa. Hanya dengan keterkaitan dengan bahasa sedalam inilah, seseorang dapat mengaku “menguasai” bahasa.
Sebelum kita sebagai bangsa mengejar cita-cita menjadi penduduk dunia, khususnya berperan dalam dunia kesusasteraan, dan bercenderung merangkul kebudayaan dan bahasa asing, mari kita mendahulukan mencari pengertian kebudayaan sendiri dan penguasaan bahasa sendiri.
Namun pada zaman sekarang, kemampuan untuk menguasai bahasa-ibu pun bermasalah. Ada kemungkinan besar bahwa bahasa yang digunakan ibu dan ayah adalah bahasa kejangkitan. Masalah ini diperbesar dengan keputusan orang tua itu untuk menyekolahkan anaknya di sekolah antar bahasa yang dengan sendirinya menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar dan ada kemungkinan besar bahasa Indonesia tidak termasuk mata pelajaran.
Karena saya sepakat dengan inti suatu peribahasa dalam bahasa Inggris yang mengatakan: You need to walk the talk – yang berarti: jangan hanya berkata namun lakukan apa yang dikatakan, saya melakukan cara yang menurut pendapat saya mungkin dapat membantu menyelamatkan bahasa kita dari terhapusnya sebagai bahasa khusus dan mandiri. Dalam penggunaan bahasa sehari-hari dan secara khusus dalam pekerjaan sebagai penerbit, saya berusaha semampu saya untuk menggunakan bahasa yang baik dan benar. Saya mohon pengertian dari siapapun yang merasa gusar dan terbebani oleh perilaku saya ini yang semata-mata didasarkan pada perasaan kebangsaan dan cinta yang dalam bagi pada bangsa dan negara.
Sebelum memperkenalkan hasil kerja sama Penerbit Sanata Dharma dan Dalang Publishing terbitan karya Arafat Nur, Lolong Anjing di Bulan dan terjemahannya oleh Maya Denisa Saputra yang diterbitkan oleh Dalang Publishing dengan judul Blood Moon over Aceh, saya ingin menutup bagian acara ini dengan mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Bapak-bapak dan Ibu-Ibu dan mengundang para hadirin untuk berdiri dan bersama mengulang dan menghidupkan kembali sumpah suara rakyat Indonesia yang telah berumur sembilan puluh tahun. Marilah kita berseru: “Kami Poetra dan Poetri Indonesia, men
Terima kasih – semoga pernyataan ini diingat dan dilakukan dalam hidup sehari-hari hadirin sekalian.
***
Lima menit berikutnya akan digunakan untuk tanya jawab. Setelah itu saya secara singkat akan memperkenalkan Lolong Anjing di Bulan – karya Arafat Nur hasil terbitan Penerbit Universitas Sanata Dharma bekerja sama dengan Dalang Publishing yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh Maya Denisa Saputra dan diterbitkan oleh Dalang Publishing dengan judul Blood Moon over Aceh.
***
Kaum muda yang dilahirkan dalam keadaan negeri merdeka lupa atau tidak punya ketertarikan untuk menghargai dan menghormati perjuangan leluhur dalam perilaku mereka sehari-hari.
- Sebelum kita sebagai bangsa mengejar cita-cita menjadi penduduk dunia, mari kita mendahulukanlah mencari pengertian kebudayaan sendiri dan penguasaan bahasa sendiri.